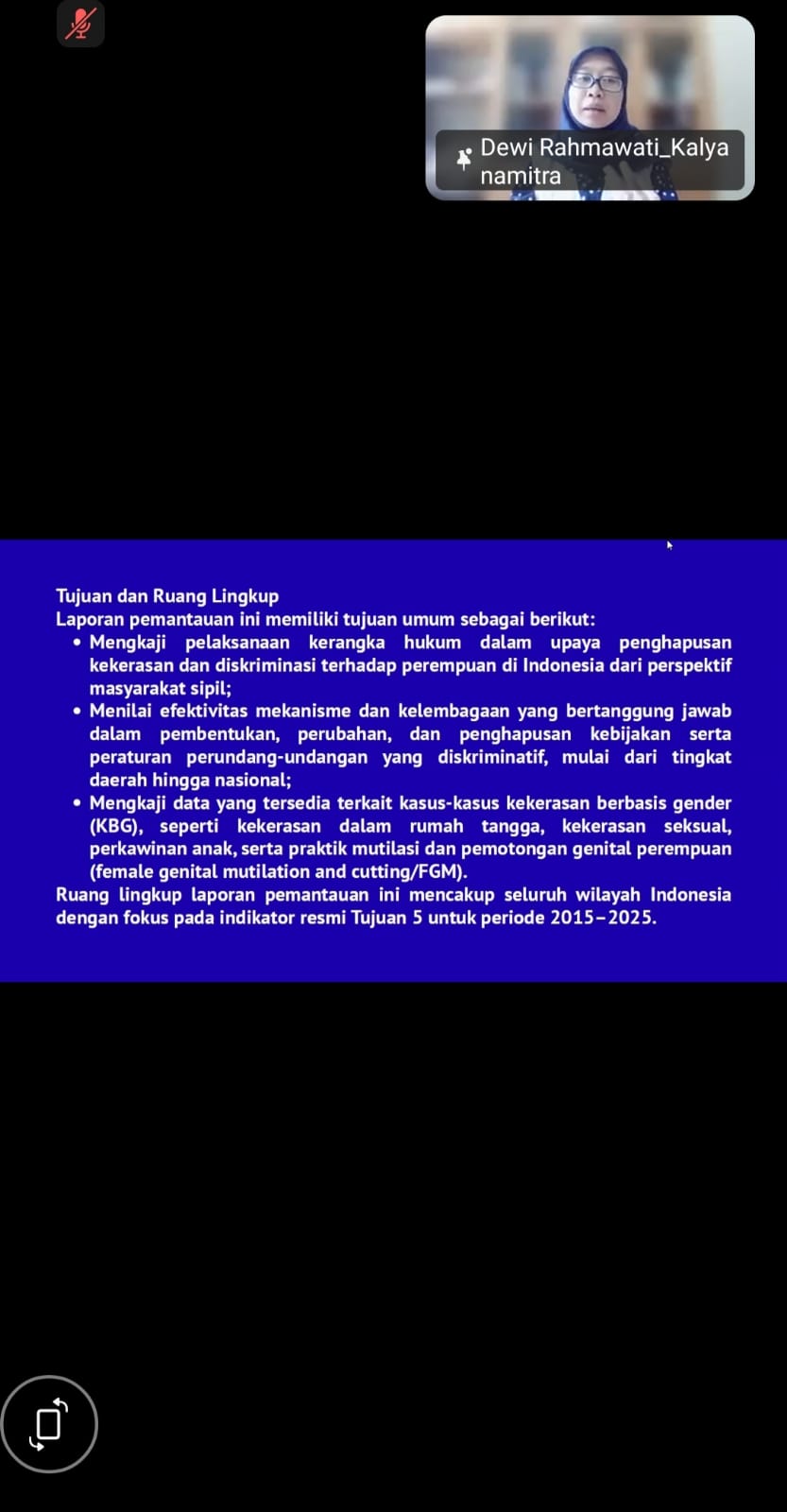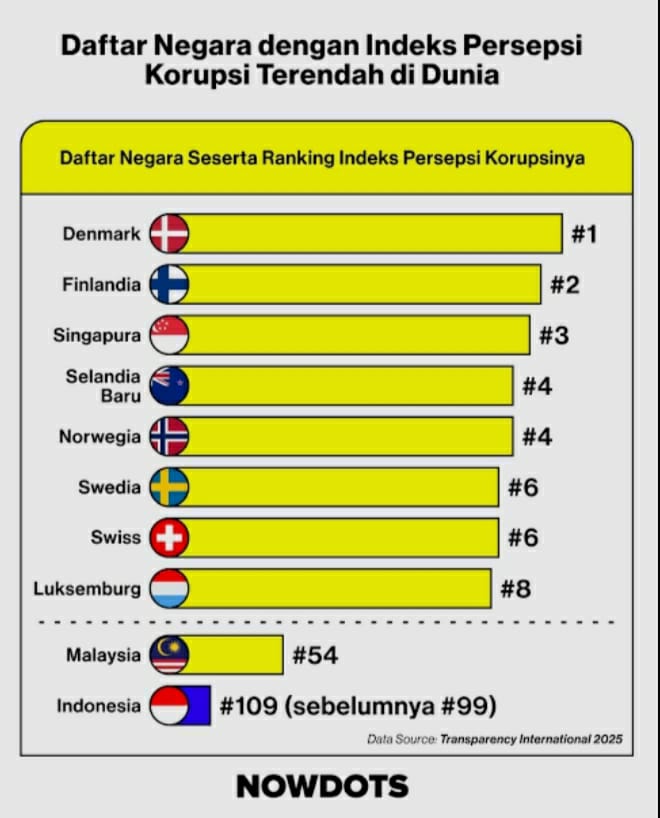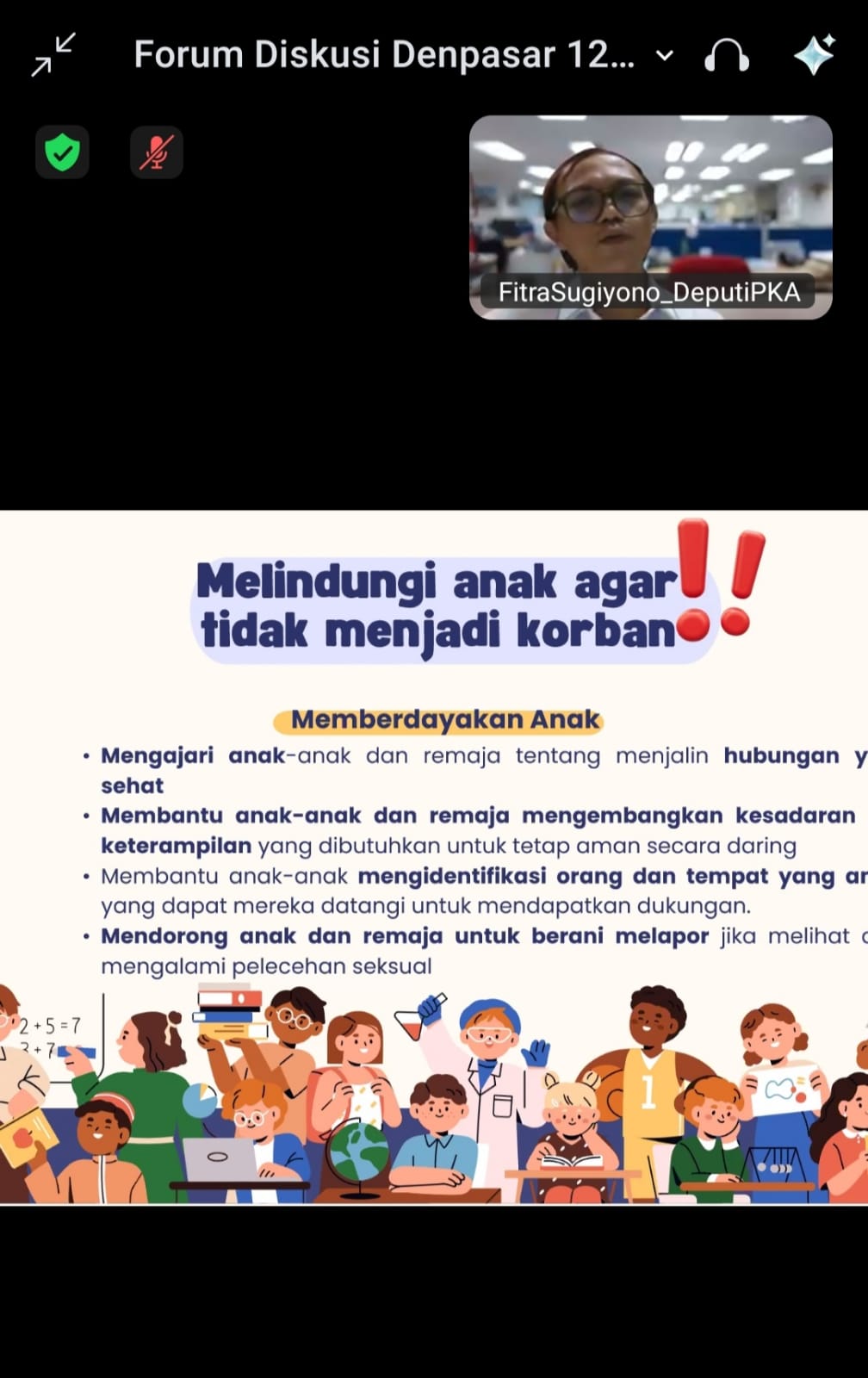Pendidikan adalah hak seluruh anak Indonesia. Keresahan panjang yang dirasakan oleh semua salah satunya adalah sistem zonasi yang diterapkan 10-12 tahun lalu. Padahal sudah dijelaskan di pembukaan Undang-undang Dasar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 6 UU Sisdiknas, tujuan pendidikan adalah demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif.
Namun begitu, secara operasional, ada problem sistemik yang menyangkut aturan yang digunakan selama ini adalah sekolah negeri melakukan seleksi. Asumsinya apakah negeri sama dengan sekolah swasta. Akhirnya karena sekolah melakukan seleksi maka perspektif teknis tidak strategis. Tidak ada tempat pemda untuk mengintervensi pada sistem pendidikan. Kemudian yang terjadi adalah rebutan kursi. Dalam situasi seperti itu maka anak-anak dengan modalitas lebih rendah/rentan/pelosok jadi kelompok dirugikan. Dan ada anak yang lebih diuntungkan. "Negara hadir sok netral. Ketika ketimpangan terjadi dan negara netral maka itu sebenarnya tidak ada keberpihakan," demikian dikatakan Bukik Setiawan, pemerhati pendidikan pada diskusi pendidikan yang dihelat oleh Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) pada Kamis (27/11). Kajian Kritis ini sekaligus rangkaian peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (16 HAKtPA).
Bukik kembali menyampaikan argumentasi, mengapa perlu mengubah sistem penerimaan murid baru sebab negara mewajibkan mencerdaskan bangsa, sekolah jadi ajang mobilitas sosial, negara tidak mampu menyediakan 100% kursi murid-murid. Kalau begitu, lantas bagaimana cara mendistribusikan yang sisanya untuk mencukupkan? Jawabannya adalah afirmasi 100%.
Ia kembali menyampaikan bahwa kesempatan setara bukan berarti sama rata dan sama rasa. Adil bukan berarti memberikan yang sama. Contoh yang paling sederhana adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka yang lebih mampu pasti akan menambah asuransi lain. Di pendidikan harusnya logikanya seperti itu. Hal itu terkait sosial ekonomi, kebutuhan murid termasuk penyandang disabilitas serta kewilayahan.
Dari situ harusnya ada prioritas/P1, P2, P3 yang disitribusikan oleh pemda/dinas, bukan sekolah. "Sekolah itu sama seperti pelayanan di rumah sakit. Kalau anak yang mendaftar lebih banyak dari kursi yang tersedia, maka pemda bisa kerja sama sekolah swasta, " ungkap Bukik. Menurutnya ada juga ketidakadilan sekolah yakni sekolah menerima yang miskin, difabel, namun uangnya sama alias BOS-nya sama. "Di usulan kami BOS-nya disesuaikan kerentanan anaknya. Misal P1 adalah 300 ribu, P2 adalah 200 ribu sehingga sekolah merasa fair. Apalagi misalnya, menangani anak difabel butuh penanganan lebih, " pungkasnya.
Pemkot Punya data e-SIK, Tinggal Jalankan
Zakaria dari Jalatera mengatakan bahwa kalau ingin memutus kemiskinan maka investasikan pada pendidikan anak. Menurutnya, keluarga miskin selalu berdampingan dengan warga miskin. Kalau hak anak tidak terpenuhi maka dia rentan miskin. Maka ketika kuota dibatasi mereka berebut aset. Jadi sebaiknya yang menentukan pilihan sekolah adalah pemda, apalagi Solo punya e-SIK yang sudah dikembangkan nasional. "Data nasional bisa salah menyebut angka kemiskinan 30%, di kabupaten saya juga 29%. Jadi yang dibutuhkan adalah siapa masyarakat miskin itu, tetapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin,"ungkap Zakaria. Terkait usulan bahwa sistem seleksi masuk sekolah yang melakukan adalah pemkot, ia setuju sebab sebenarnya kota Surakarta sudah siap dengan data kemiskinan dan bisa jadi pelopor. Artinya bagaimana sebenarnya pemda mendekatkan akses ini pada keluarga miskin sebab problem pendidikan makin komplek.
Zakaria menggambarkan di tahun 2021 angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sangat tinggi, maka pada waktu itu sarannya adalah dinas pendidikan "jemput bola". Sebab dengan membuktikan data di lapangan dengan verivikasi dan validasi, data ATS yang akhirnya bersekolah bisa dihapus.
Lantas ada pertanyaan, terkait beberapa problem sekarang terjadi dengan sistem zonasi maka seperti yang terjadi di SMP N 4 atau SMP N 9, di tingkat guru ada ekspektasi pada murid yang sudah rendah. Kaitannya sekolah mereka dekat wilayah Cinderejo dan satunya kelurahan Pajang, yang dalam data e-Sik termasuk kelurahan miskin. Stigma mereka terhadap warga miskin masih tebal.
"Dulu ada PKMS, kami temukan data 2000 orang yang harusnya tidak menerima tapi menerima. Yang nggak fair adalah kalau ada yang lebih miskin tetapi dia tidak dapat. Itu tidak fair. Di pendidikan lebih parah. Maka kalau membatasi jangan panjang dengan modalitas, semestinya dinas pendidikan kerja sama dengan dinas lain. Harusnya kalau disitu banyak anak, maka taman bermain butuh dibangun,"ujar Zakaria lagi. Maka ia menegaskan lagi bahwa sekolah tidak paham siswanya miskin atau tidak dan bersepakat bahwa sistem penerimaan siswa baru yang melakukan adalah pemkot dan tantangannya adalah menghilangkan stigma miskin serta dalam konteks pemkot ; modalitas dan datanya harus diperbaiki.
Istini Anggoro, narasumber dari Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo menyampaikan kesulitan anak difabel mengakses pendidikan di sekolah reguler, dekat rumah karena ketiadaan Guru Pendamping Khusus (GPK). Karena tidak ada GPK mereka bersekolah di daerah lain atau bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Di Surakarta masih ditemuinya anak dampingan mereka kesulitan bersosialisasi dan tidak diterima. Gurunya hanya berpesan "kalian harusnya bersyukur sekolah di sini". Masih ditemui sekolah yang tidak ramah disabilitas apalagi terkait kapasitas gurunya alias guru minim pemahaman disabilitas. Ada pelatihan pada guru namun dalam satu tahun dan hanya ada satu kali pelatihan.
Isti melakukan asesmen di beberapa sekolah. Ada yang dalam proses pembelajarannya disendirikan padahal bukan SLB. Padahal semua tahu, setiap anak semestinya mendapatkan hak pendidikan yang layak dan ini jadi perhatian bersama. Dari keluarga dukungan sangat minimal karena stigma cukup tinggi, artinya dalam keluarga ada bagian yang menghambat. Ia menegaskan terkait afirmasi sebenarnya bagus karena masih banyak anak difabel yang ditolak. "Anak kami sekolah di sekolah negeri, kalau olah raga tidak diajak dan hanya melihat anak-anak lain berolah raga,"pungkasnya.
Dwi Ariyatno, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang turut hadir dalam diskusi mengatakan bahwa SD, dan SMP cukup menampung siswa dari warga miskin. Ia merasa sudah memenuhi akses keadilan namun belum bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. "Masalahnya di kesadaran. Ekspektasi untuk mendidik anaknya. Sebagian sekolah kami dinilai kurang kualitas. Masalahnya masyarakat memilih yang swasta. Kaitannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masalah awal adalah mereka berebut belenggu sekolah negeri yang berkualitas. Bahkan miskin berebut miskin untuk sekolah berkualitas. Kita tidak membatasi preferensi masyarakat untuk memilih. Pertanyaannya, bagaimana memenuhi harapan bahwa pendidikan memenuhi ekspektasi?" ujarnya.
Menjawab penanya di sesi diskusi kembali Bukik menegaskan bahwa negara cenderung netral mengasihi meskipun kondisi anak berbeda-beda. Timbul pertanyaan, apakah itu adil atau keadilan yang kita inginkan? Di Surakarta bahkan tidak memadai lantas apakah kita biarkan? Atau mana anak-anak yang berisiko ketinggalan? Sementara negara masih membagi rata. Maka yang ia usulkan adalah sistem afirmasi, murid mana yang layak diberikan? Berikan pada anak yang rentan. Tidak terus berusaha mengayomi semuanya
Sedangkan Zakaria kembali memberi pernyataan ketika negara membangun regulasi hak pendidikan bagi difabel sekolah., sebenarnya bisa dibaca akar masalahnya yakni bagaimana perencanaan negara ini. Dalam konteks perencanaan negara bukan pada soal penampungan. Apakah mau dibikin secara bertahap atau tidak karena harus realistis.
Istini juga menanggapi bahwa ketika dirancang dan anggaran sudah ada, harapannya guru di sekolah inklusi mendapat pelatihan. Dan ketika anak difabel jadi keresahan dari orangtua maka itu jadi bentuk diskriminasi. Guru harus punya tools-nya, tidak bisa memakai ilmu kira-kira. (Ast)