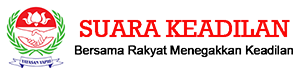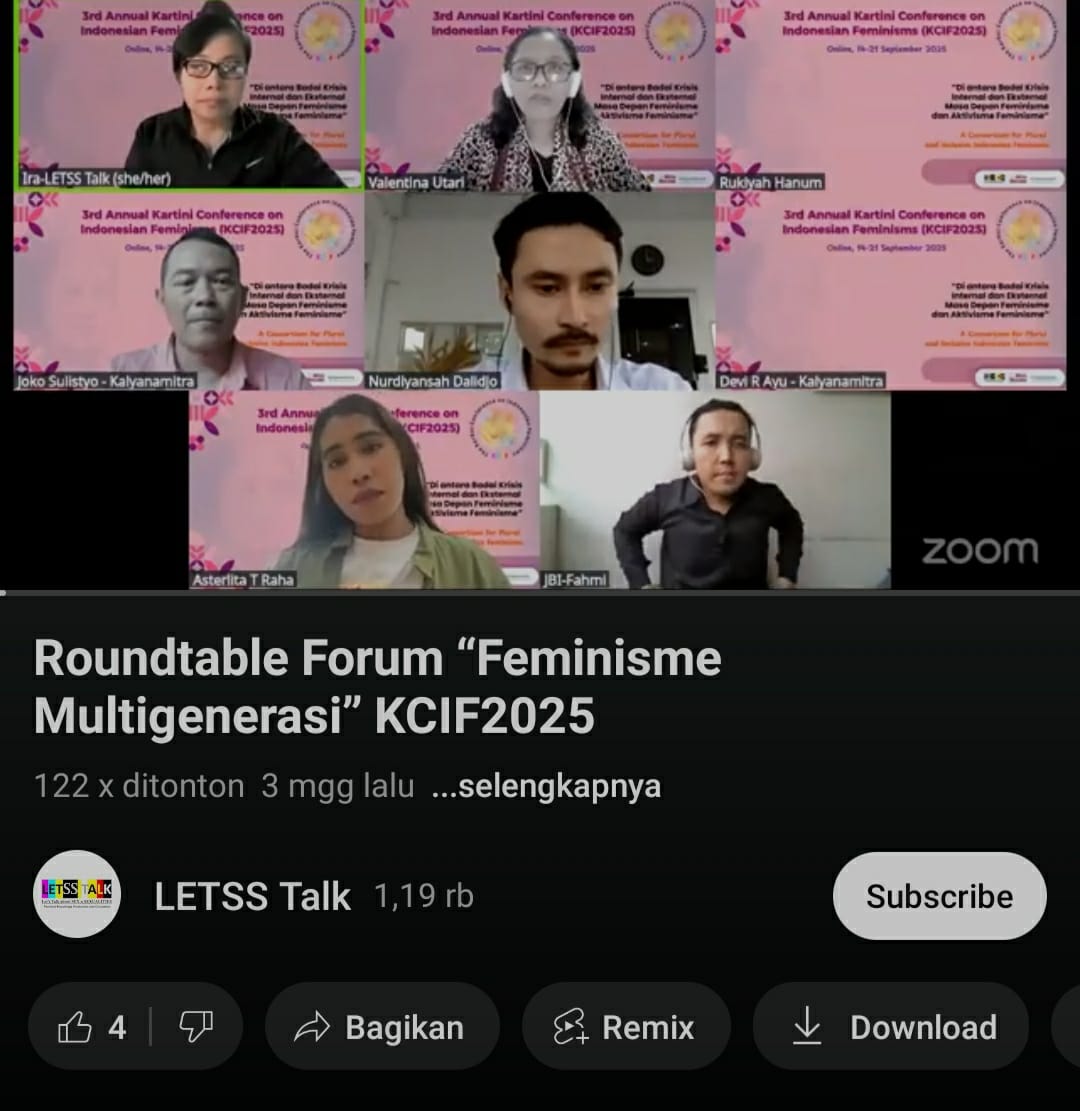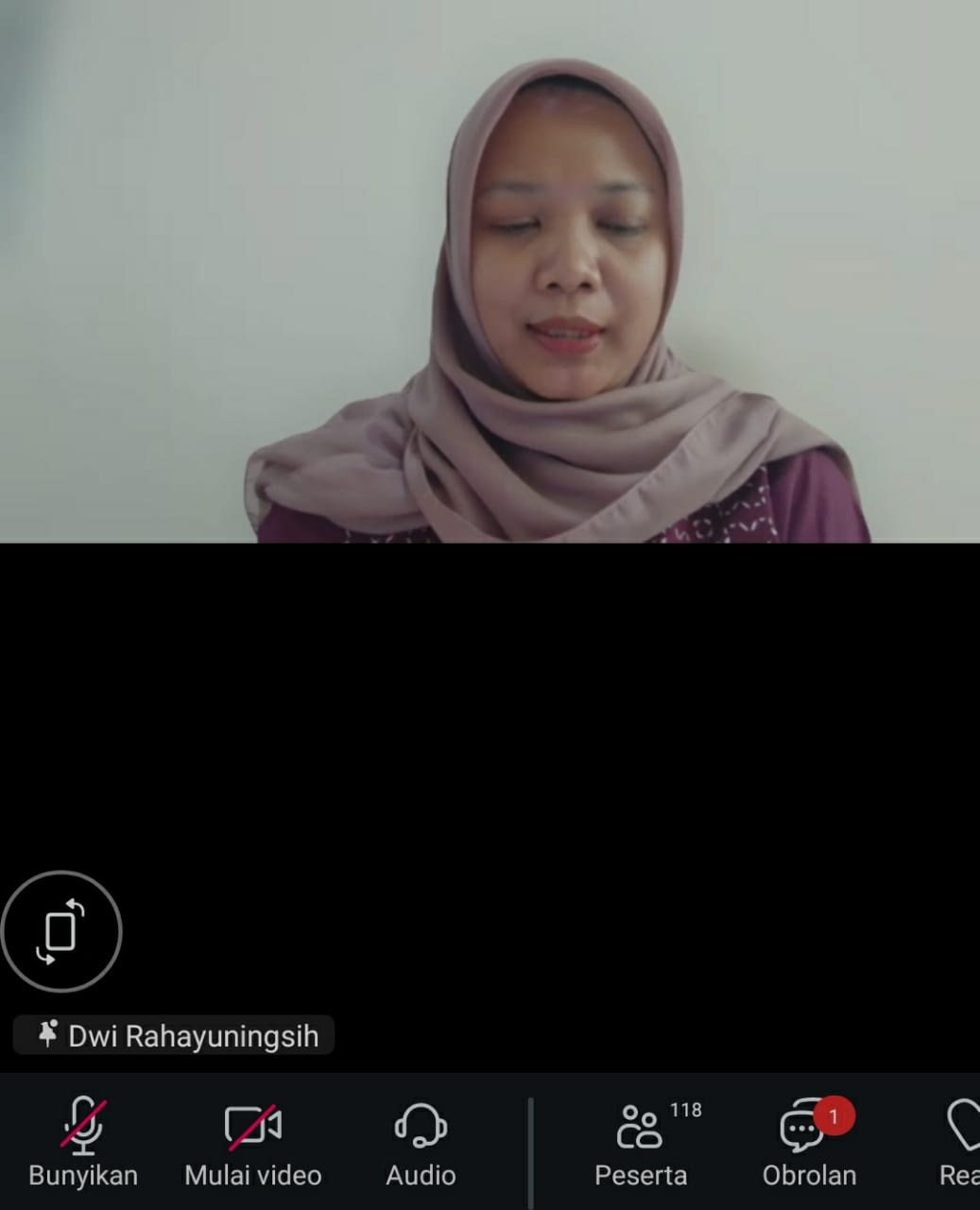Badai dalam sosial politik seringkali menekan aktivisme dan cenderung menyempitkan ruang-ruang sipil. Hal ini terjadi karena adanya kelelahan kolektif, bias relasi kuasa, dan fragmentasi solidaritas. Hal tersebut lantas memunculkan gerakan feminisme di Indonesia. Merujuk pada sebuah pertanyaan, bahwa figur mana yang dianggap sah menjadi rujukan feminisme, bagaimana feminisme dipahami, dan seperti apa gerakan politik ke depan, LETSS TALK Bersama Mitra Wacana dan Kalyanamitra membuat gelaran bertajuk Kartini Conference on Indonesia Feminism 2025 (KCIF 2025) dengan tema “Di antara Badai Krisis Internal Dan Eksternal: Masa Depan Feminisme Dan Aktivisme Feminis.” KCIF 2025 dilaksanakan mulai 14-21 September 2025.
Pada KCIF 2025, terdapat 56 sesi panel paralel (Parallel Session) dengan berbagai tema dan dua sesi khusus (Special Plenary Sessions). Lebih 350 orang menjadi presenter/panelis/pembicara/fasilitator dan 1000 orang melakukan registrasi untuk berpartisipasi sebagai peserta KCIF2025.
Salah satu sesi dalam KCIF 2025 adalah Roundtable Forum Feminisme Multigenerasi. Panel ini dilaksanakan pada Selasa (16/09) pukul 15.00 – 17.30 WIB. Narasumber yang hadir pun hadir dari beragam generasi, yakni Myra Diarsi, aktivis gerakan perempuan, Biyung Komunitas Feminis GAIA, Rukiyah Hanum dari Pegiat HAM dan Isu Perempuan; Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh 2024-2029. Joko Sulistyo, Manajer Keorganisasian Kalyanamitra, Nurdiyansah Dalidjo, Penulis/Manajer Tim Project Multatuli, Asterlita Tirsa Raha, aktivis Perempuan Halmahera, Salma Rizkya Kinasih, seorang peneliti Independen dan Kolektif SWEG (Sawit Women Educational Group), dan Clara Ruel Eugene, Founder PERAN (Pentingnya Toleransi). Dan dipandu oleh moderator yakni Valentina Yulita Utari, Ph.D. peneliti the SMERU Research Institute.
Myra Diarsih: Perintis Gerakan Feminisme Indonesia yang memiliki perjalanan panjang
Diawali dengan Myra diarsih yang membagikan pengalamannya menjadi seorang perintis gerakan feminisme di Indonesia dimana perjalanan panjang dan kompleks dalam membangun gerakan Perempuan. Myra menceritakan bahwa gerakan feminisme saat itu tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang represif di bawah rezim Orde Baru. Rezim yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun itu disebutnya sebagai kekuatan otoritarian yang berhasil membungkam gerakan kiri pasca tragedi 1965. Dalam situasi itulah, gerakan perempuan muncul sebagai bagian dari arus alternatif yang menentang narasi tunggal pembangunan dan ideologi negara.
Di tahun 1980, Gerakan berawal dari organisasi non-pemerintah. Kalyana Mitra pada tahun 1984, dengan fokus lembaga adalah perempuan, buruh, dan masyarakat miskin kota. Kalyana Mitra sejak awal menjadi ruang alternatif yang dibentuk oleh pelajar dan mahasiswa untuk merespons ketimpangan sosial dan politik, khususnya terhadap buruh perempuan yang mengalami penindasan struktural. Myra juga menceritakan bahwa awalnya, kegiatan gerakan lebih banyak berfokus pada konseling korban kekerasan terhadap perempuan. Namun seiring waktu, fokus melebar ke isu-isu geopolitik yang lebih luas, mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi perempuan dalam berbagai lapisan sosial dan struktural. Myra menceritakan di era 1980an, pendekatan feminisme banyak mengkritisi kebijakan developmentalisme model pembangunan ekonomi yang mengabaikan dampak sosial terhadap kelompok rentan. Sehingga memperjuangkan kelompok miskin dan rentan tidak dengan pemerintah namun menjalin kemitraan dengan donor untuk kemandirian gerakan. Gerakan yang dilakukan juga bersifat gerakan sendiri dan bukan driven by donor.
Rukiyah Hanum: Tantangan Gerakan Feminisme di Aceh
Hanum menjelaskan bahwa perjuangan feminisme di Aceh memiliki tantangan yang kompleks dan unik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Namun, feminisme di Aceh juga kerap dianggap sebagai produk Barat, sehingga muncul kecurigaan dan resistensi terhadap gerakan tersebut, terutama di wilayah dengan identitas keagamaan dan adat yang kuat seperti Aceh. Hanum menceritakan pasca perjanjian damai Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik panjang di Aceh, Aceh mendapatkan status sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus. Hal ini memberikan kewenangan bagi Aceh untuk menerapkan kebijakan lokal, termasuk penerapan hukum berdasarkan syariat Islam melalui berbagai kanun.
Dalam konteks ini, perjuangan hak-hak perempuan menjadi semakin rumit. Hanum menceritakan bahwa di Aceh, berlaku tiga sistem hukum sekaligus: hukum adat, hukum positif nasional, dan hukum syariat Islam. Tumpang tindih ketiga sistem hukum ini menciptakan kendala besar, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. “Tantangan paling besar adalah dominasi patriarki dan tafsir agama dalam penerapan hukum. Seringkali kasus-kasus kekerasan seksual justru ditangani di luar pengadilan formal melalui mekanisme adat, yang tidak memberikan keadilan bagi korban,” ungkapnya. Hanum menyoroti bagaimana kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual di Aceh lebih banyak diselesaikan melalui qanun jinayah, yang merupakan aturan berbasis syariat, dibandingkan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Padahal, UU TPKS secara nasional dianggap sebagai kemajuan signifikan dalam perlindungan korban kekerasan berbasis gender, termasuk pemenuhan hak-hak pemulihan, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikologis.
Namun dalam praktik di Aceh, pasal dalam qanun jinayah menyatakan bahwa jika terdapat aturan yang sama dalam undang-undang lain, maka yang berlaku adalah qanun jinayah. Meski begitu, perjuangan terus dilakukan. Bersama jaringan aktivis, Hanum menceritakan bahwa akan tetap melakukan advokasi agar perempuan Aceh dapat mengakses perlindungan dari UU TPKS. Salah satu fokus utama adalah mendorong revisi terhadap qanun jinayah, terutama pasal-pasal yang membatasi akses terhadap sistem hukum nasional.
Joko Sulistyo: Gerakan Feminis adalah Membangun Empati dan Mendorong Kesetaraan
Joko menyampaikan refleksi mendalam mengenai bagaimana gerakan feminisme tidak hanya relevan bagi perempuan, tetapi juga penting untuk dipahami dan dijalani oleh laki-laki. Joko menjelaskan bahwa feminisme pada dasarnya adalah ruang untuk menjadi diri sendiri. "Feminisme mengajarkan kita untuk kembali kepada jati diri kita, baik sebagai perempuan maupun laki-laki, tanpa beban konstruksi sosial yang membatasi,” ujarnya. Menurut Joko, masyarakat kerap kali membentuk standar tertentu terhadap peran gender, Baik laki-laki maupun perempuan tumbuh dalam tekanan sosial yang membatasi ekspresi dan peran mereka. Joko juga menyoroti bagaimana kerja-kerja perawatan, seperti mengurus rumah, anak, atau merawat orang tua, sejak dulu selalu diidentikkan sebagai tugas perempuan. Joko menegaskan bahwa ini adalah tugas kemanusiaan yang bisa dan seharusnya dikerjakan siapa pun, termasuk laki-laki.
Penting bagi laki-laki untuk menyadari bahwa mereka tidak akan pernah mengalami apa yang disebut sebagai “pengalaman khas perempuan” seperti menstruasi, kehamilan, dan melahirkan. "Menjadi feminis bagi saya adalah tentang membangun empati dan simpati. Ketika perempuan mengalami menstruasi atau melahirkan, kita sebagai laki-laki harus bisa memahami dan menghargai rasa sakit serta kebutuhan mereka," ungkapnya. Joko menekankan bahwa kesetaraan bukan soal siapa yang lebih kuat atau berkuasa, tapi tentang menyamakan posisi dan tanggung jawab. Joko pun membagikan pengalamannya saat memberikan pelatihan gender kepada peserta laki-laki dan melakukan pendekatan dengan laki-laki dimulai dengan pertanyaan beban yang ditanggung sebagai lelaki seperti harus kuat, mencari nafkah, dan tidak boleh mengeluh. Namun joko mempertegas bahwa hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang kadang disadari dan mengajak para laki-laki untuk mulai merefleksikan kembali konsep “menjadi laki-laki” yang selama ini dibentuk oleh masyarakat.
Nurdiyansah Dalidjo: Harapan bahwa Adanya Kesetaraan yang Lebih Inklusif dan Interseksional
Nurdiyansah menjelaskan bahwa pertemuan kali ini merupakan ruang perenungan baik secara personal maupun kolektif. Dian menyoroti bahwa feminisme tidak lagi bisa dipahami secara eksklusif sebagai gerakan untuk perempuan saja, melainkan harus berkembang menjadi gerakan multigenerasi dan lintas identitas. Dian menyampaikan bahwa berbicara soal gender tidak lagi bisa dibatasi dalam kerangka biner antara laki-laki dan perempuan. Dalam kenyataannya, terdapat spektrum identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda, yang juga mengalami penindasan dan marjinalisasi akibat sistem patriarki yang sama. Dian juga menjelaskan bahwa kini feminisme memiliki spektrum yang lebih luas, dari generasi feminis lama yang membangun landasan awal, hingga generasi kontemporer yang bersandar pada kompleksitas demografis, geografis, dan sosial budaya.
Dian menyoroti bahwa masih ada problematika dalam gerakan feminisme itu sendiri, terutama ketika masih muncul pemisahan atau segregasi antara kelompok identitas. Dian mengajak untuk melihat ke arah pemikiran post-strukturalis, yang menolak konsep identitas tunggal, stabil, dan biner. Dian menekankan bahwa kelompok perempuan, queer, disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok minoritas lainnya menghadapi penindasan struktural yang berlapis. Dalam situasi tersebut, tidak ada pilihan lain selain saling merawat untuk membangun keberlangsungan hidup, komunitas, dan gerakan itu sendiri.
Kemudian Dian juga menyinggung terkait tantangan internal yang kini dihadapi feminisme, terutama berkaitan dengan eksistensi kelompok queer dalam gerakan ini. Dian mengkritik munculnya fenomena Trans-Exclusionary Radical Feminism (TERF) atau kelompok yang menolak mengakui transpuan sebagai perempuan dan trans laki-laki sebagai laki-laki. Menurutnya, padangan ini berlawanan dengan semangat inklusivitas feminisme yang seharusnya menerima keberagaman identitas gender.
Dian menyadari bahwa menyatukan feminisme dengan pemikiran queer (feminist queer thinking) masih menjadi tantangan di Indonesia. Dian mengungkapkan bahwa tetap optimis dengan kekayaan budaya, multikulturalisme, dan keberagaman masyarakat Indonesia, serta ada ruang untuk membangun gerakan yang lebih menyatu. Dian mengharapkan bahwa gerakan ke depan tidak perlu untuk memisahkan antar gender, namun gerakan harus menjadi ekosistem yang inklusif, saling merawat, dan mudah diakses bagi siapapun yang ingin ikut terlibat.
Asterlita Tirsa Raha: Dari Halmahera dan Pergolakan Diri dalam Gerakan Feminisme
Asterlita mengawali dengan menceritakan dirinya menemukan Gerakan feminisme adalah dari rasa marah yang ditemukannya saat merantau keluar dari kampung halamannya. Tahun 2014, saat berkuliah di Sulawesi Utara, Aster pertama kali mengenal istilah feminisme. Aster menjelaskan bahwa feminisme sebagai ruang tumbuh yang memberinya makna, bukan hanya untuk memahami ketimpangan, tapi juga untuk pulih dari trauma pribadi dan penindasan struktural yang dialami sejak kecil.
Aster bercerita bahwa menyaksikan bagaimana Perempuan di Halmahera, khususnya perempuan adat, menghadapi tekanan dari perusahaan tambang nikel. Industrialisasi besar-besaran tidak hanya merampas tanah dan ruang hidup, tapi juga membungkam suara perempuan melalui kekerasan, kriminalisasi, dan ekonomi. “Pernah ada perempuan yang hampir ditembak karena mempertahankan tanahnya. Dia dikriminalisasi oleh perusahaan. Dan banyak mama-mama adat yang hanya bisa diam, terpukul, tak berdaya. Kompensasi diberikan kepada mama adat untuk dijadikan alat untuk membungkam perjuangan mereka,” ujarnya.
Aster menjelaskan bahwa ketimpangan pun terjadi di Halmahera, dimana tidak ada sinyal dan Listrik sehingga tidak mudah untuk mengakses informasi. Dan hal tersebut lantas membuat aster tidak merasa layak karena kurangnya akses pengetahuan. Aster juga menyampaikan bahwa feminisme tidak hanya membantunya menganalisis pengalaman hidup dan ketertindasan kolektif, namun juga mengakui feminisme membantunya sembuh dan sebagai penyintas konflik horizontal Islam-Kristen di tahun 2000, yang meninggalkan luka sosial mendalam di komunitasnya.
Aster percaya, meski banyak perempuan di Halmahera tidak bisa membaca buku atau mengakses internet karena keterbatasan infrastruktur dan tradisi, mereka tetap bisa memiliki semangat feminis, asal ada ruang dan dorongan untuk membangun kepercayaan diri. Aster juga berharap bahwa gerakan bisa menyala dan semangat feminis bisa hadir dan tumbuh di desa terpencil.
Salma Rizkya Kinasih: GEN Z yang Tumbuh dari Ruang Digital dan Lapangan hingga Solidaritas Perempuan Buruh Sawit
Salma menceritakan bahwa inisiatif ini tumbuh dari kesadaran kolektif akan minimnya ruang perempuan dalam forum-forum buruh sawit. Karena hal tersebut, Sawit Women Education Group (SWEG) menjawab hal tersebut. Salma menceritakaan saat awal terjun ke lapangan dan menyadari bahwa diskusi-diskusi buruh didominasi oleh suara laki-laki. Maka dari itu, dibutuhkan ruang aman dan setara di mana suara perempuan, terutama buruh perempuan sawit, bisa lebih terdengar dan diorganisir. “Dari situ, kami mencoba menjembatani kawan-kawan di Jawa dengan perempuan-perempuan di lapangan. SWEG menjadi tempat bertemunya berbagai pengalaman: dari ibu-ibu sawit hingga anak-anak Gen Z yang mungkin awalnya hanya terlibat lewat digital,” jelasnya.
Salma menjelaskan bahwa di tengah maraknya label terhadap aktivis Gen Z yang dianggap hanya aktif di media sosial dan tak mengakar, SWEG justru menjawab tudingan itu dengan praktik nyata. “Seringkali kita dilabeli oportunis, bergerak sendiri-sendiri, atau sebagai aktivis Twitter saja. Padahal, kami justru belajar banyak dari lapangan dan dari pengalaman orang lain,” ujarnya. Salma menyampaikan bahwa Gen Z sering kali dianggap hanya aktif di media sosial dan tak mengakar, yang sebenarnya gen z belajar banyak dari lapangan dan orang lain. Baginya, feminisme bukan hanya soal teori atau kebutuhan personal, tetapi juga soal solidaritas dan kerja kolektif, dari lapangan hingga ruang digital.
Salma juga menjelaskan bahwa gen Z seringkali mengalami “patahan memori” kehilangan jejak atas sejarah panjang gerakan perempuan akar rumput. Salma menjelaskan bahwa SWEG mencoba merajut kembali benang itu, menciptakan ruang pertukaran yang saling menguatkan. Salma menekankan bahwa feminis Gen Z hari ini banyak bergerak di ranah digital, tapi kesadaran akan pentingnya konteks lapangan juga makin tumbuh. SWEG berupaya mendokumentasikan bagaimana feminisme bisa bekerja langsung di lapangan dan menjawab isu-isu konkret: dari lingkungan, relasi kuasa, sampai persoalan kelas.
Clara Ruel: Gerakan Gen Alpha dalam Menyuarakan Feminisme
Ruel menceritakan bahwa dirinya berusia 15 tahun dan merupakan seorang pelajar SMA di Yogyakarta. Ruel menceritakan bahwa gen Alpha penting untuk menyuarakan feminisme, dimana feminisme bukan sekadar topik diskusi orang dewasa, melainkan gerakan penting untuk melihat dan melawan ketidakadilan, terutama yang dialami oleh perempuan. “Feminisme itu penting karena membantu kita memahami bahwa ketidakadilan itu nyata, dan perlu dilawan,” ujarnya.
Ruel menceritakan mengenai ketertarikannya terhadap feminisme lewat ketekunannya membaca surat-surat R.A. Kartini. Ruel menceritakan bahwa pada awalnya tertarik pada semangat Kartini memperjuangkan pendidikan di tengah lingkungan sosial dan budaya yang patriarkal. Namun saat memasuki SMA, risetnya berkembang.
Ruel menceritakan mulai mendalami isi surat-surat Kartini dari aspek ekonomi dan politik dan menyadari bahwa ketidakadilan gender bukan hanya soal budaya, tapi juga terkait erat dengan sistem ekonomi dan politik yang timpang. Ruel menjelaskan bahwa gen Alpha berbeda dengan generasi sebelumnya di mana dahulu bergerak melalui organisasi atau turun ke jalan, namun gen Alpha lebih nyaman berjuang lewat platform digital, media sosial, dan komunitas sebaya.
Ruel menilai bahwa ruang digital bisa menjadi jembatan penting untuk memperluas pemahaman feminisme, yang kini tak lagi terbatas pada isu perempuan, tapi juga isu lingkungan, ekonomi, dan keragaman identitas. Ruel juga menekankan bahwa pentingnya Gerakan feminisme lintas generasi agar pengetahuan feminisme dari generasi terdahulu tidak terputus, melainkan diadaptasi menjadi bentuk-bentuk baru yang relevan. Ia juga berharap bahwa Gerakan feminisme ke depan bisa menginspirasi perubahan nyata di masyarakat dan kebijakan publik. Bagi Ruel, feminisme bukan hanya narasi kesetaraan, tapi juga alat untuk membangun dunia yang lebih adil dan manusiawi.(Renny Talitha Candra)