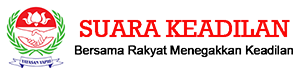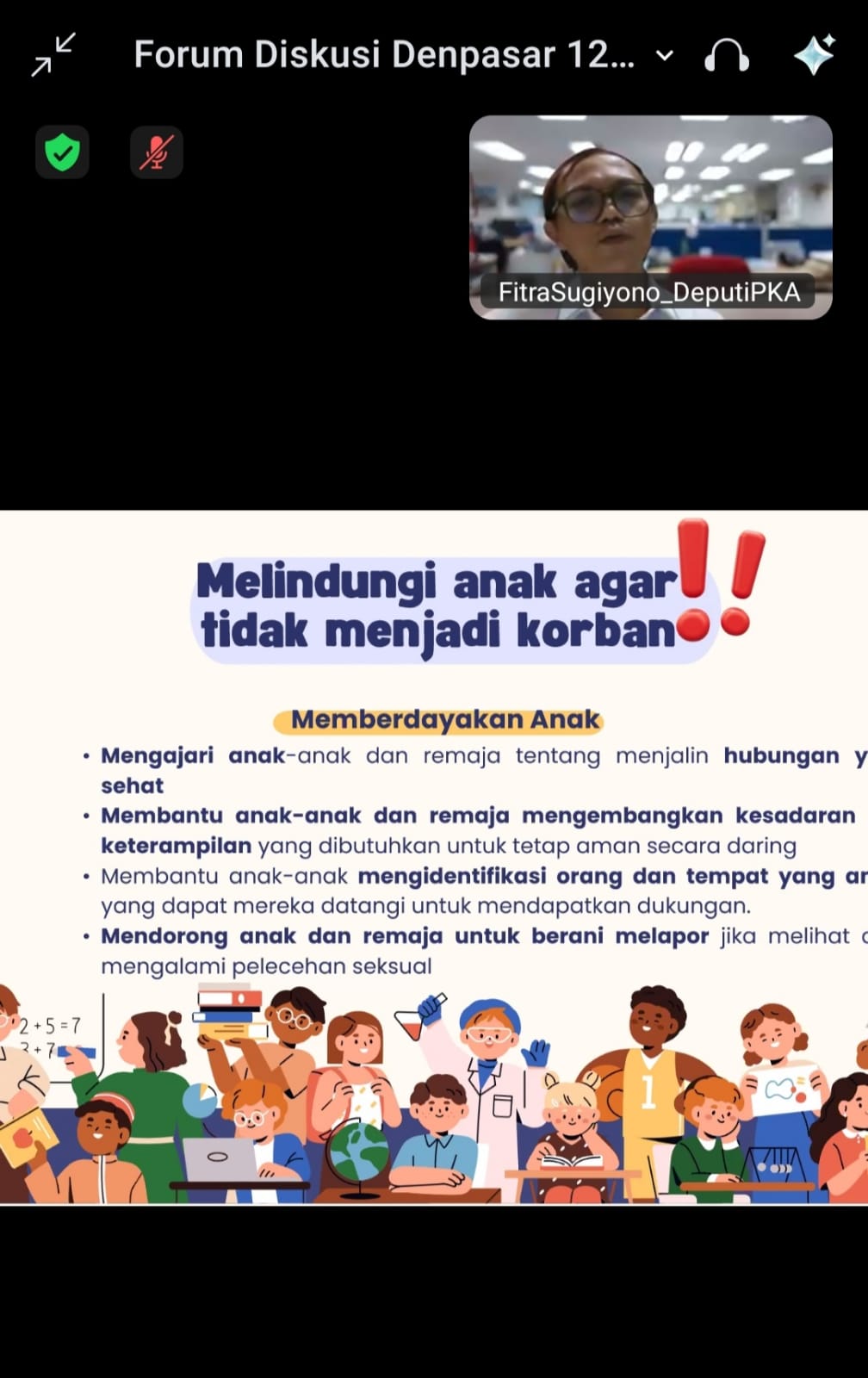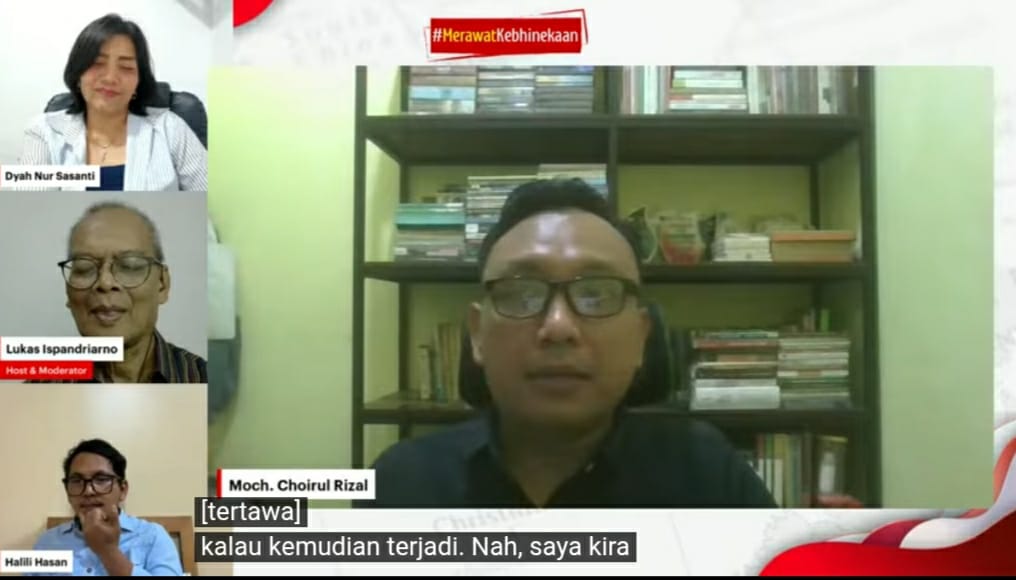Perkara 130/PUU-XXIII/2025 telah memasuki sidang ke-5 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon. Sidang lanjutan dari perkara tersebut kembali digelar pada Selasa, (21/10/2025). Sidang terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diajukakan oeh Raissa Fatikha dan Deanda Dewindaru, dua penyintas penyakit kronis karena merasa hak-hak mereka tidak dijamin akibat tidak diakuinya penyakit kronis secara eksplisit dalam definisi disabilitas.Meski tak terlihat secara kasat mata, seharusnya juga diakui sebagai difabel.
Pada sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 13 Agustus lalu, pemohon bernama Raissa Fatikha mengatakan jika ia merupakan penyintas Thoracic Outlet Syndrome (TOS) selama 10 tahun ini.
Saat itu, dia mengaku seringkali merasa nyeri berkelanjutan di tangan, pundak, dan dada kanan atas dengan intensitas yang berfluktuasi, sehingga membatasi mobilitas kendati tetap berupaya aktif melakukan edukasi publik terhadap penyakit tersebut.
Raissa melanjutkan, kondisi serupa juga dialami pemohon bernama Deanda Dewindaru yang merupakan penyintas penyakit autoimun Guillain-Barré Syndrome, Sjögren’s Disease, dan Inflammatory Bowel Disease selama tiga tahun terakhir.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu saksi pemohon, Fadel Noorandi, penyintas talasemia mayor, yang hadir dalam persidangan ke-5 kali ini. Sejak bayi, ia hidup dengan kebutuhan transfusi darah seumur hidup dan efek samping berat, seperti kelelahan kronis, pembesaran organ, serta gangguan fungsi tubuh lainnya. Fadel mengatakan bagaimana hambatan yang dialaminya tidak tampak secara fisik, tetapi nyata membatasi keterlibatannya dalam pendidikan dan pekerjaan.
“Banyak dari kami ditolak bekerja hanya karena hasil tes medis, padahal kami bisa produktif jika diberi akomodasi yang layak,” terang Fadel.
Ia menekankan bahwa difabel bukan hanya terlihat dari kursi roda atau tongkat, melainkan dari kemampuan fungsional yang terhambat oleh penyakit kronis, seperti kanker, penyakit autoimun, atau talasemia. Sayang sekali, kenyataan ini belum mendapatkan pengakuan hukum yang tegas dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016, yang dipandang para pemohon masih terlalu sempit dalam memaknai difabel fisik.
“Kalau kami harus menjelaskan setiap kali bahwa penyakit kami menyebabkan keterbatasan fungsi tubuh, kami merasa kelelahan ganda. Tidak hanya melawan penyakitnya, tapi juga menjelaskan terus-menerus hak kami,” ujar kuasa hukum mereka, Reza, dalam sidang ke-4 sebelumnya.
Dalam kesempatan sidang tersebut, anggota Komisi III DPRRI, Sari Yuliati, hadir secara virtual menyampaikan pernyataannya bahwa penetapan status disabilitas harus melalui asesmen klinis. Menurutnya dokter sebagai tenaga medis yang kompeten memiliki wewenang untuk menilai apakah kondisi penyakit kronis seseorang memenuhi kriteria disabilitas.
Ia mengingatkan bahwa tidak semua penyakit kronis menimbulkan keterbatasan fungsional, dan memperluas definisi disabilitas tanpa batasan yang jelas bisa menyulitkan implementasi kebijakan. DPR RI, lanjut Sari, menilai tidak ada pelanggaran konstitusi dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Disabilitas. Mereka pun meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.
Berbeda halnya dengan suara dari ahli yang diajukan Pemohon yakni Bahrul Fuad, Komisioner Purna Komnas Perempuan dan aktivis hak-hak difabel, menjelaskan bahwa pendekatan hukum terhadap disabilitas tidak boleh kembali ke paradigma medis yang sempit. “Disabilitas itu bukan semata-mata berasal dari kondisi tubuh, tapi dari interaksi antara keterbatasan seseorang dan hambatan lingkungan. Ketika negara hanya mengakui disabilitas yang tampak, kita mengabaikan jutaan orang dengan keterbatasan tak terlihat,” papar Bahrul.
Bahrul mencontohkan penggunaan instrumen Washington Group Questions (WGQ) yang lebih menekankan pada hambatan fungsional, bukan sekadar diagnosis medis. Menurutnya, penjelasan Undang-Undang yang hanya menyebut ‘gangguan gerak’ sebagai disabilitas fisik sudah ketinggalan zaman.
Pernyataan dari ahli lainnya, M. Joni Yulianto dari SIGAB Indonesia, lebih menekankan bahwa perkara ini bukan tentang label, melainkan tentang akses. Bahwa pengakuan penyakit kronis sebagai ragam difabel bukan untuk membuka keran klaim baru, tetapi untuk menjamin bahwa mereka yang benar-benar mengalami hambatan hidup bisa dilindungi oleh negara. “Kita tak bisa terus membiarkan orang dengan penyakit kronis terkatung-katung di wilayah abu-abu regulasi. Undang-Undang ini sudah berjalan hampir satu dekade, tapi mereka belum juga punya ruang yang pasti,” ujar Joni. Menurutnya, penafsiran yang sempit hanya akan melanggengkan ketimpangan. Ia menegaskan bahwa perluasan makna disabilitas bukan berarti semua penyakit kronis otomatis masuk kategori itu, melainkan membuka pintu untuk asesmen yang adil dan inklusif. (Ast)