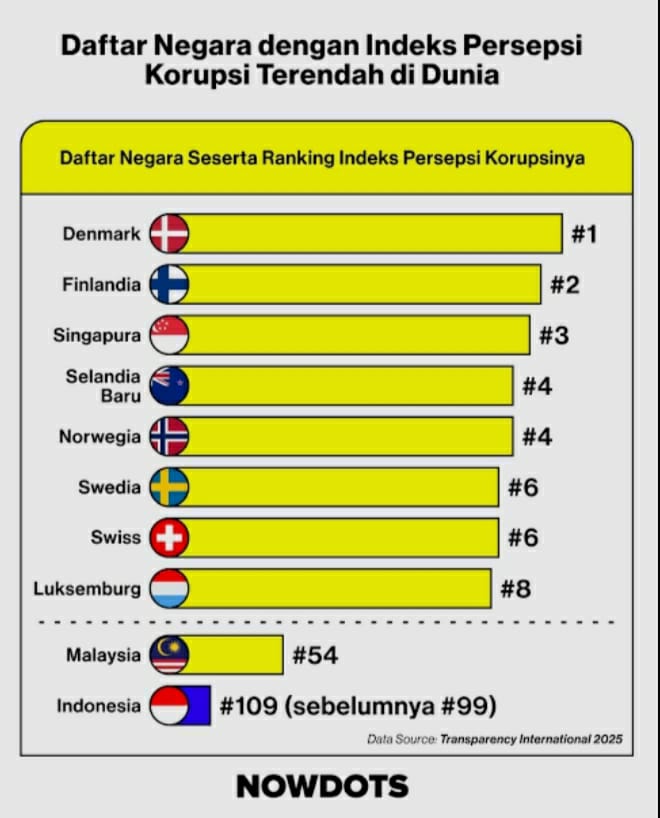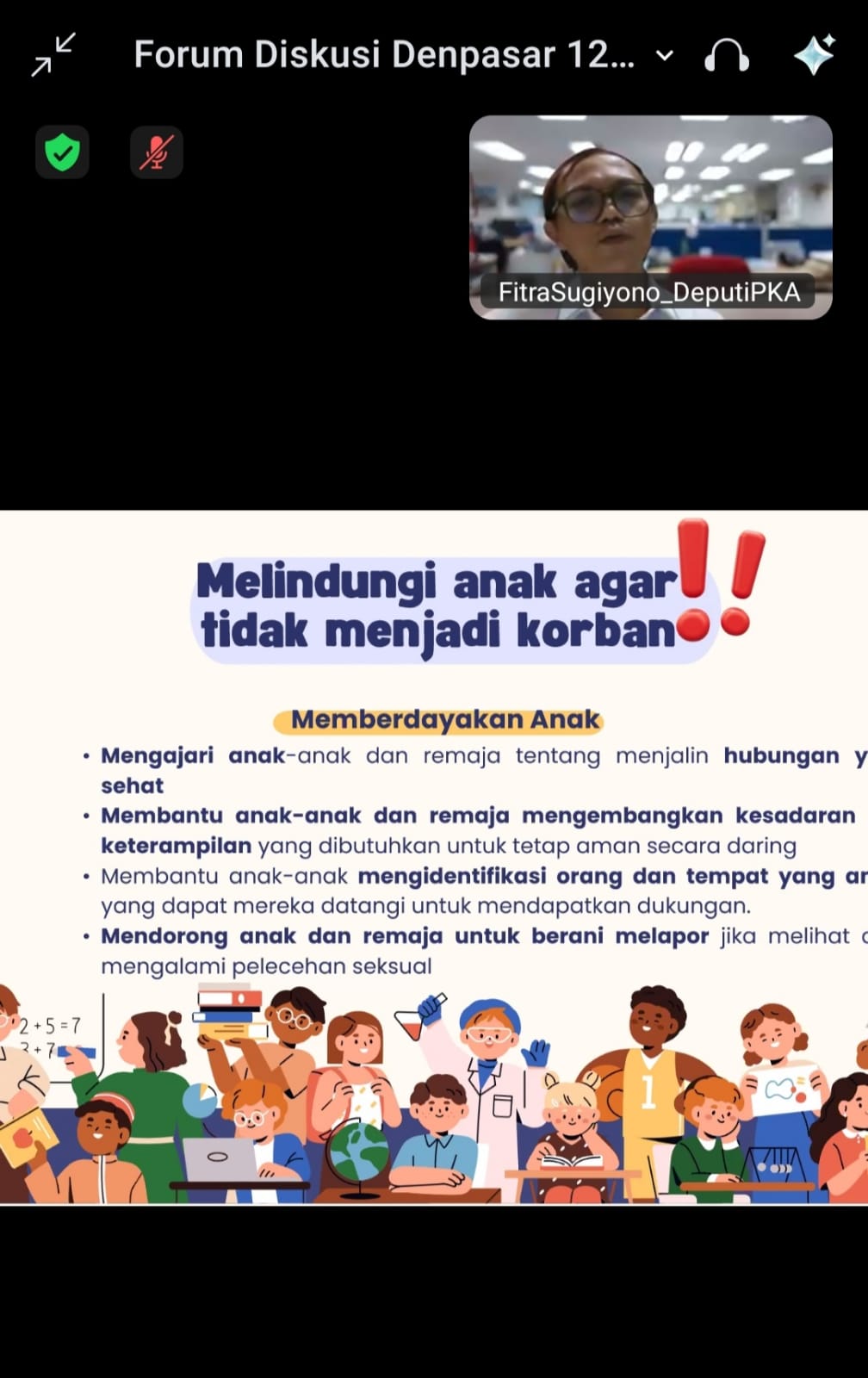Film Pangku sukses membuat saya menangis, hampir di setiap adegan. Ini pengalaman emosional personal sebenarnya. Bagaimana tidak, di awal adegan saja penonton sudah diperlihatkan bagaimana seorang perempuan hamil yang menumpang truk untuk mencari kerja, dikata-katai sebagai pembawa sial.
Hanya gara-gara ban truk menggembos di perjalanan. Bukannya tetap menolong, tapi dua orang laki-laki awak truk ini seperti mengumpankan Sartika, si perempuan untuk mencari kerja di daerah sekitarnya_dengan mengarahkan jalan_seakan-akan bilang dalam hati, "ya sudah, kamu perempuan hamil nggak jelas, kalau mau kerja ya di situ". Hhmm...
Pengambilan gambar yang sangat detail sebenarnya dimulai dari awal adegan, saat Sartika (yang diperankan oleh Claresta Taufan) turun dari truk terlihat ia memakai rok, yang bagian bawahnya tampak sisi depan lebih pendek, menandakan bahwa di pemakai baju sedang hamil besar. Sutradara yang sangat jeli dan detail. Dari setiap tatapan dan ekspresi Sartika yang dingin di menit-menit awal, serta rautan wajah dua laki-laki sopir dan kenek yang datar meski di suasana emosi marah atau anyel, tepatnya. Sebenarnya ini adalah sinyal dari perjalanan cerita ke depan yang sunyi, suwung, datar seperti karakter orang Jawa (semoga saya tidak bias) pada umumnya, padahal para nelayan yang tinggal di Pantura dengan suhu panas terik, bukannya tabiatnya sering kasar? Mungkin pengecualian. Pengambilan judul film "Pangku" seakan meneguhkan bahwa film ini tentang Jawa, tentang budaya yang sering dikonotasikan sebagai halus, namun patriarki sangat kuat.
Sartika kemudian tinggal bersama Bu Maya, si empunya warung kopi yang sambat jika warungnya sekarang sepi, tergeser oleh karaoke yang menawarkan hiburan lebih moderen. Ia boleh tinggal di sana hingga Bu Maya membantu kelahiran anaknya. Kemudian Sartika jadi buruh tani, menyiangi rumput dan tanaman padi sehabis panen, sambil membawa anaknya bekerja, dengan upah yang sangat minim bahkan tidak cukup untuk membeli beras. Akhirnya dengan berat hati, ia ambil keputusan itu : bekerja kepada Bu Maya sebagai pemandu, pendamping minum kopi, sampai tandas di isapan terakhir. Ia masih malu-malu dan berusaha menjaga tubuhnya, agar misi bekerjanya terjaga : hanya sebagai pemandu, teman si pengopi.
Tapi apa lacur, Sartika tertarik kepada Hadi pelanggannya, yang suka memberi oleh-oleh empat ekor ikan lebihan. Lebihan ya, artinya ia tidak mengambil yang bukan jatahnya, alias tidak mengkorupsi dagangannya (pastinya milik orang lain) untuk diberikan pada Sartika, Bayu anak Sartika dan Bu Maya beserta sang suami. Sungguh sebuah ironi, keluarga Bu Maya yang tinggal di pinggiran pantai utara, kampung nelayan, tapi jarang makan ikan, terbukti, mereka berempat tidak ada yang tahu apa nama ikan yang mereka santap tersebut.
Sekali lagi, film Pangku bisa saya katakan Jawa sentris, sebagaimana terlihat Bu Maya, yang diperankan sangat bagus oleh Christine Hakim. Meski di dalam hatinya panas membara karena sang suami sudah tidak bekerja lagi, dan hanya mampu mengumpulkan sampah plastik yang tidak dijualnya, namun tetap menghormati sebagai seorang istri: menyajikan makan dan minum. Meski hubungan suami istri itu bisa dikatakan silent treatment. Nyaris di sepanjang film, Pak Jaya, suami Bu Maya tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pernah mendengar kakek atau nenek kita orang Jawa yang memilih diam-diaman kala satu sama lain ada ketidakcocokan? Saya mengira demikian pula hubungan suami istri ini. Namun Pak Jaya adalah manusia sempurna karena memiliki sikap welas asih dengan turut mengasuh Bayu, membuatkan gerobak mie ayam bahkan tak dapat menahan air mata ketika Sartika dan Bayu pamitan hendak pindah ke rumah Hadi, usai Sartika dinikahi Hadi. Aktor Jose Rizal Manua membawa karakter tersebut dengan sangat baik.
Bayu, yang terbiasa hidup dengan minim percakapan, atau bisa dikatakan terlalu hati-hati untuk berbicara, kecuali saat terbangun dari tidur, ia berkata kepada ibunya, sepertinya begini " Aku nggak suka ibu kerja dengan dipangku-pangku".Ia melihat ibunya dalam konteks bekerja.
Bayu lebih memilih curhat dengan Gilang_diperankan oleh Devano Danendra_yang kehidupannya lebih parah lagi, tanpa orangtua dan keluarga serta menerima apa adanya ketika dirinya mendapat perlakuan kasar dipukul oleh juragan. Apakah demikian, bahwa kekerasan itu lebih mudah dilampiaskan oleh orang yang memiliki kuasa, atau orang yang merasa lebih tinggi derajatnya kepada orang yang terpinggirkan, miskin, yatim, dan nir perlawanan?
Apiknya, film Pangku tidak memperlihatkan orang-orang itu sebagai bagian individu yang cengeng, merasa jadi korban, menye-menye, atau bahkan berbalik jadi brutal. Tidak. Budaya Jawa dengan latar di tahun 90-an akhir belum bergeser, setidaknya pada lapisan masyarakat di situ. Sehingga, kegelisahan Gilang berbuah kreativitas : ia keluar dari kerja kuli, lantas jadi tukang parkir sambil membuat layang-layang yang bisa ditukar dengan rupiah. Senyatanya, ia bisa kok keluar dari lingkaran kekerasan oleh juragan.
Sama juga yang dialami oleh Sartika, ketika menyadari bahwa ia bukan satu-satunya perempuan di kehidupan Hadi. Ia hanya dijadikan pelampiasan nafsu dan kesepian panjang suami yang ditinggal istri bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Dengan dalih apa pun : Hadi ingin punya anak, ingin mengentaskan ke kehidupan yang lebih layak, padahal sebenarnya akar masalahnya sama :tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Hadi yang mengambil kuasa atas diri Sartika. Mau bukti? Lihat saja senyum sadis bak serigala yang terus-menerus di-shoot oleh sutradara. Pengambilan gambar secara close up ke wajah Hadi yang berpenampilan agak kalem_mungkin Reza sang sutradara tidak ingin menghilangkan karakter Fedi Nuril di film-film sebelumnya_namun sifat kalem itu terbantahkan dengan senyum jahat.
Karakter jahat Hadi yang diwakili hanya oleh lirikan mata, semakin menasbihkan bahwa film Pangku adalah film tanda-tanda. Penonton diminta untuk mencermati tanda, raut ekspresi wajah, percakapan-percakapan untuk memainkan emosi. Bahkan emosi marah Sartika ketika pergi meninggalkan rumah hanya diwakili oleh linangan air mata, dan bagaimana tekadnya mendorong gerobak mie ayam yang batal digunakan. Tidak ada teriakan marah-marah atau silat lidah antara Sartika dan Hadi. Tatapan kosong Hadi mengarah kepada Sartika dan Bayu, serta istrinya adalah representasi dari kekalahan laki-laki patriarkat di ambang bimbang.
Saya kira, film ini bercerita tentang kisah yang panjang sekali, tidak hanya kekerasan terhadap perempuan tetapi kekerasan struktural yang melahirkan kemiskinan, keluarga yang timpang karena tidak ada peran ayah, tentang otoritas tubuh perempuan, tentang peralihan zaman dan masih banyak lagi yang bisa kita cermati. Dan yang penting untuk digarisbawahi adalah tentang bagaimana bertahan dalam kehidupan. Reza Rahadian, sebagai sutradara dalam debutnya, saya kira bisa membawa para penonton, tidak hanya ke puncak emosional saja, tetapi spiritualitas tingkat tinggi, tanpa menggurui. (Astuti Parengkuh)