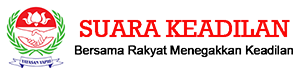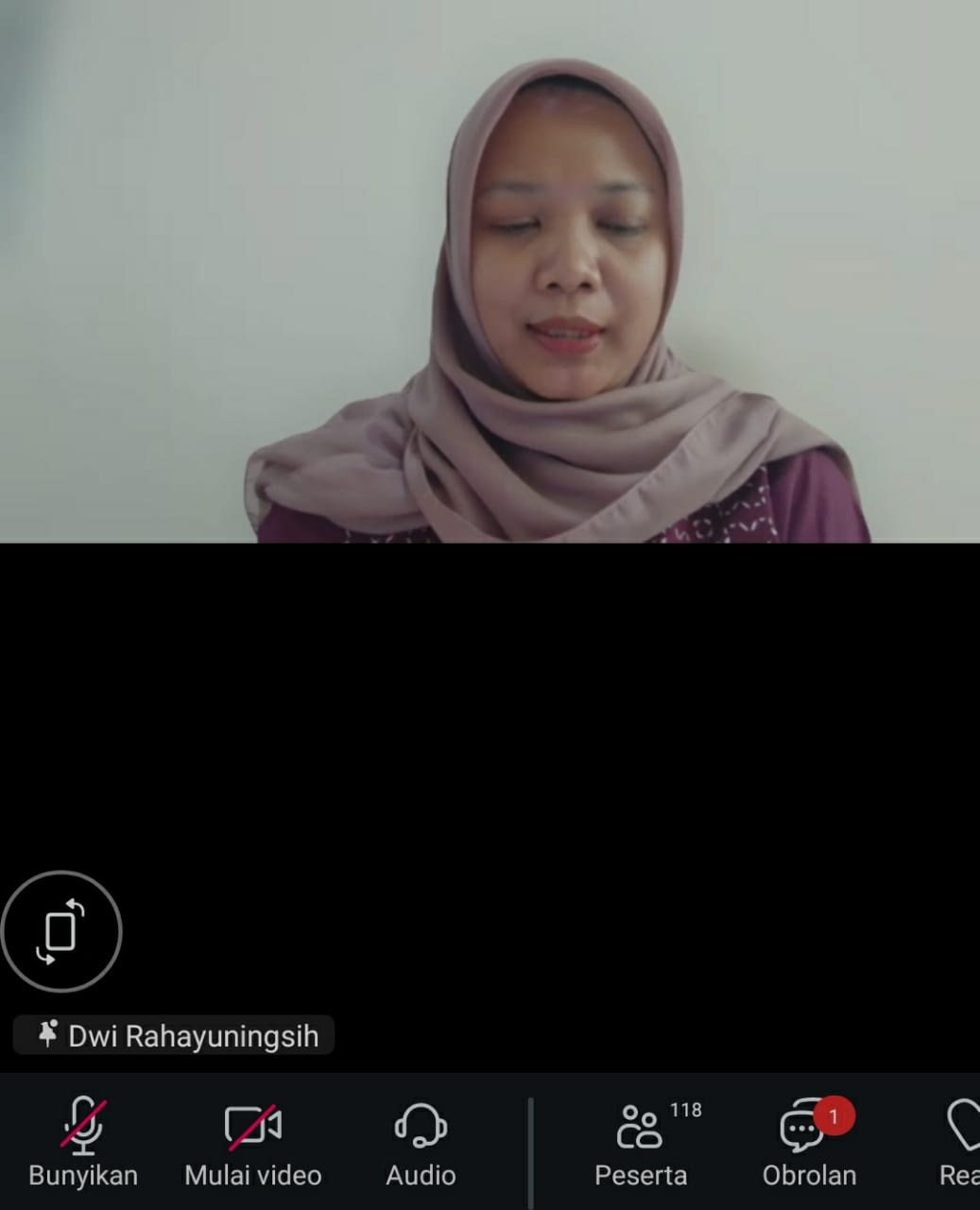Sebuah diskusi penting mengenai Gender Transformative Approach (GTA) dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia digelar di Kantor Bappeda, Mojokerto, Kamis (2/10). Acara yang diinisiasi oleh UN Women, ActionAid, Oxfam, dan sejumlah organisasi kemanusiaan serta masyarakat sipil lain ini menyoroti bahwa integrasi perspektif gender dalam penanggulangan bencana harus bergeser dari sekadar respons kebutuhan yang berbeda menuju transformasi struktural yang adil dan inklusif bagi semua.
Diskusi ini menghadirkan perwakilan dari berbagai lembaga, termasuk Yulies Puspitaningtyas (UN Women), Fitri Riyanti (Kelompok Perempuan Cahaya Tangguh), Rachmawati Husein (AP-KI/Unsur Pengarah BNPB), dan Maria Lauranti (Oxfam in Indonesia), serta para aktivis disabilitas.
Dari Sensitif Gender menuju Transformatif Gender
Yulies Puspitaningtyas dari UN Women menegaskan bahwa integrasi gender harus melampaui pendekatan sensitif gender atau responsif gender. Pendekatan Gender Transformatif berupaya secara eksplisit memperbaiki ketidaksetaraan gender, menghapus hambatan struktural, dan memberdayakan populasi rentan.
"Pendekatan multidimensi fokus pada upaya mengatasi hambatan hukum, kebijakan, sistem, dan layanan, serta mendorong alokasi sumber daya yang lebih adil," jelas Yulies. Sementara itu, pendekatan feminis yang diusung UN Women menekankan tiga hal utama: mendorong perubahan hubungan kekuasaan, mengatasi ketimpangan struktural, dan memposisikan perempuan sebagai pemimpin dalam ketahanan pembangunan.
Transformasi gender dipahami sebagai proses perubahan yang disengaja dan sistematis untuk menghapus ketidakadilan berbasis gender, berfokus pada perubahan struktur (peran dalam kepemimpinan), norma (menghapus stereotip diskriminatif), dan praktik (pendidikan inklusif dan solidaritas).
Tantangan Implementasi dan Keterlibatan Simbolik
Rachmawati Husein dari AP-KI/Unsur Pengarah BNPB menyoroti bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun konsep Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (GEDSI) telah diperkenalkan, penurunan kebijakan dari pusat ke daerah masih lemah.
"Inti dari diskusi ini adalah pergeseran dari sekadar kesetaraan simbolik menuju perubahan struktural dalam hubungan kekuasaan," tegas Rachmawati. Keterlibatan perempuan dalam forum PRB sering kali masih bersifat simbolik—hanya untuk memenuhi formalitas kuota tanpa ditempatkan pada posisi strategis yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah tidak responsif gender, terbukti dari kurangnya pertimbangan terhadap kondisi spesifik perempuan, seperti keterbatasan akses informasi kebencanaan.
Perempuan dan Kelompok Rentan di Ruang Kemanusiaan Perkotaan
Fitri Riyanti dan Maria Lauranti, menyoroti tantangan khusus di wilayah perkotaan dan pasca bencana. Fitri Riyanti menekankan pada Kesenjangan Urban yakni pertumbuhan ekonomi akibat urbanisasi menciptakan ketimpangan akses terhadap bantuan sosial, dukungan UMKM, dan informasi bagi perempuan lokal dan kelompok risiko lainnya, seperti perempuan penyandang disabilitas. Infrastruktur publik pun belum sepenuhnya ramah gender dan ramah disabilitas (contoh: ketiadaan ruang laktasi, toilet yang tidak terpisah dengan baik).
Terkait kekerasan berbasis gender pasca bencana, Maria Lauranti dari Oxfam menekankan bahwa bencana memperburuk situasi, menyebabkan lonjakan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi. Oleh karena itu, pencegahan KBG harus terintegrasi sejak tahap mitigasi hingga pemulihan. Oxfam mempraktikkan hal ini dengan mengalirkan mayoritas dana pasca bencana langsung ke organisasi perempuan lokal dan jaringan penyandang disabilitas, seperti LBH APIK Sulteng dan SAPDA.
Strategi Maju: Twin-Track Approach dan Advokasi Berbasis Data
Diskusi menyepakati bahwa transformasi memerlukan strategi multi-level dan berkelanjutan:
1. Pendekatan Ganda (Twin-Track Approach): Perubahan harus diintervensi dari struktural (kebijakan dan kelembagaan di tingkat atas) dan kultural (kesadaran dan diskusi di tingkat akar rumput) secara beriringan.
2. Penguatan Data: Penggunaan Rumah Data Keluarga atau data terpilah gender dan disabilitas menjadi kunci untuk analisis kebutuhan yang akurat dan pengajuan program yang terukur dalam forum perencanaan pembangunan.
3. Kepemimpinan dan Kapasitas: Mendesak penguatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di posisi strategis PRB, sekaligus melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai sekutu dalam menantang maskulinitas patriarkis.
4. Institusionalisasi Inklusi: Menciptakan ruang baru seperti Kampung Siaga Bencana Inklusi yang mengintegrasikan perspektif interseksionalitas—memasukkan kebutuhan disabilitas, lansia, anak, dan kelompok minoritas ke dalam seluruh sektor PRB.
5. Advokasi Berkesinambungan: Diperlukan peran perantara yang jelas untuk menghubungkan cerita akar rumput dengan advokasi kebijakan di tingkat atas, memastikan alokasi anggaran responsif gender untuk mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana.
Dari proses diskusi dapat disimpulkan bahwa mencapai desa atau kota tangguh yang adil menuntut perubahan paradigma mendasar, di mana kesetaraan gender dan inklusi sosial dipandang sebagai tujuan utama dari seluruh intervensi PRB, bukan sekadar pelengkap. "Kalau kita ingin desa tangguh, maka harus tangguh untuk semua. Laki-laki dan perempuan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi," tutup salah seorang lead fasilitator. (Vera)