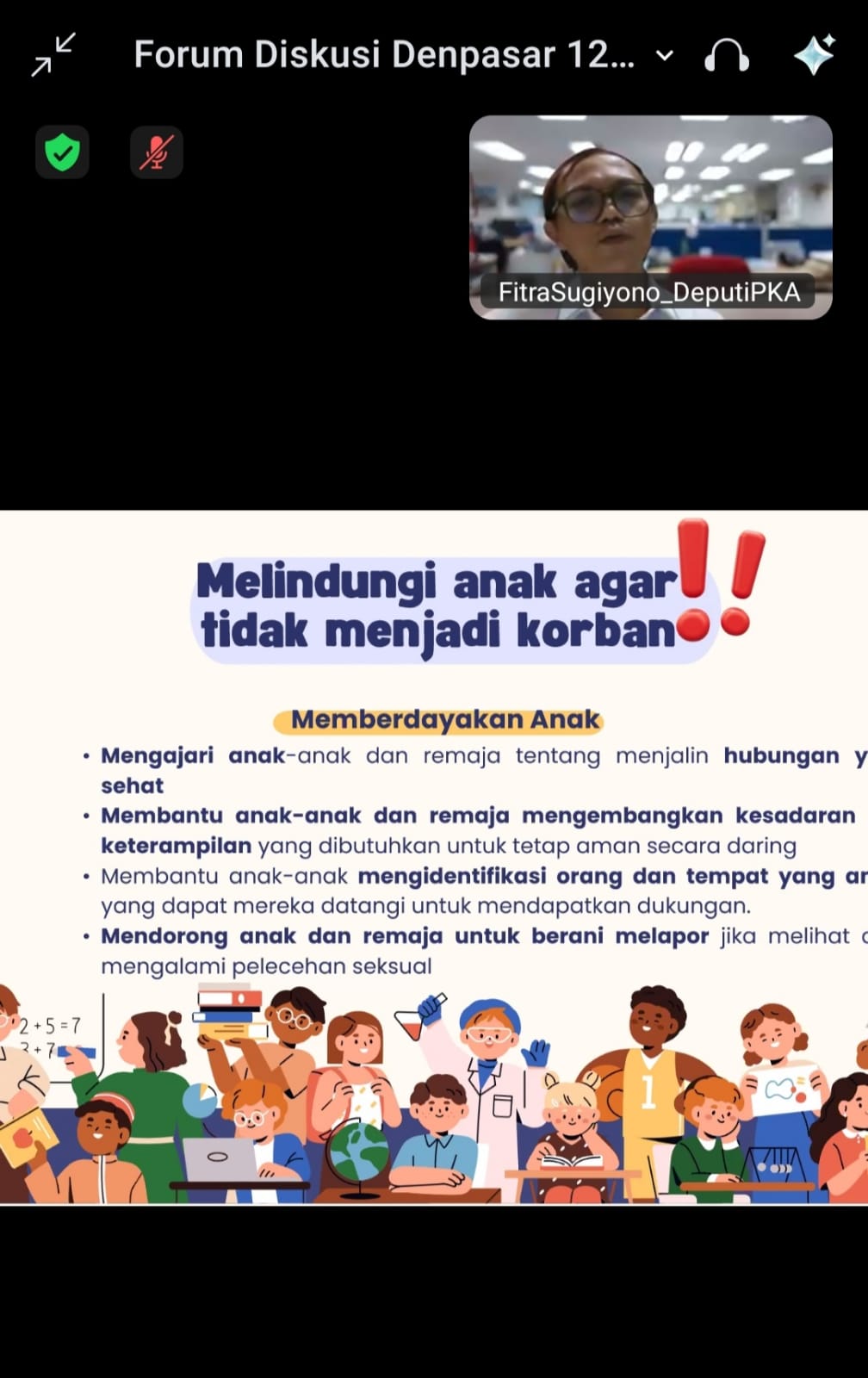Mengawali talkshow pada peringatan International Women’s Day (IWD) 2025, Sabtu (22/2), Girl Up Universitas Sebelas Maret, melalui moderatornya Fatimi Hanum Sabila, mengetengahkan tiga kasus kekerasan yang menimpa perempuan, dua di antaranya viral di media sosial. Kasus pertama yakni mahasiswa PPDS Universitas Diponegoro, kedua adalah kasus tragis penjual gorengan Sumatera Barat, dan sebuah kasus kekerasan yang tidak viral. Menjajagi pendapat para peserta, panitia membagkan kuis mentimeter untuk diisi para peserta. Puluhan jawaban terpampang di layar.
Di antara jawaban itu adalah yang membedakan kasus-kasus tersebut adalah ketika masuk media sosial dan viral, maka akan ditangani dengan serius meski tidak selesai dengan adil, karena hanya untuk menjaga nama baik institusi. Yang tidak viral tidak ditangani dengan serius, sangat jauh pula dari keadilan. Ada lagi jawaban yang tidak viral, kasus dilimpahkan ke kejaksaan dengan tanpa tanda bukti hanya terkena kasus pencabulan
Husni, salah seorang peserta mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) mengungkapkan bahwa denga viralnya kasus tersebut yakni pada kasus pertama menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam program PPDS lantas menunggu viral dulu agar terlihat publik atau sebenarnya sudah ada kasus tapi tidak diurus oleh pihak berwenang alias acuh tak acuh. Kemudian kasus kedua (perempuan penjual gorengan) keviralan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meraup keuntungan dari dari sesuatu yang buruk. Lantas pertanyaannya, apakah setelah kasus viral korban mendapatkan keadilan? Tidak. Harusnya ada keadilan bagi korban yakni tenang dan mendapatkan ketenangan.
Sesi kedua talkshow menghadirkan narasumber Fitri Haryani dari Yayasan SPEK-HAM. Menanggapi tentang masalah keviralan dan respon aparat kepolisan, ia menyatakan bahwa supremasi hukum belum ditegakkan. Ini dibuktikan dengan adanya tiga kasus, dua di antaranya ada tindak lanjut berdasar ada aksi dulu. Padahal menurut Fitri, keadilan itu harusnya tanpa adanya kasus viral pun, harus ditegakkan.
Ia menambahkan di era digitalisasi, setiap orang ingin memberikan kabar dengan berbagai situasi dalam keadaan baik,karena ketidaktahuan, bahkan tangung jawab seperti apa, maka hal ini berdampak bagi korban. Fenomena masyarakat yang butuh aktualisasi dan validasi, itu seperti dua sisi, yang satu sisi positif dan negatif. “Seseorang yang mengabarkan semuanya ke media sosial buat apa? Bombastis? Validasi?”tanya Fitri.
Lantas bagaimana di era digitalisasi merespon saat ini? ada UU ITE yang membuktikan bahwa pemangku kebijakan memberi respon. Apa yang harus diperbaiki? viralitas bisa dilakukan dengan tujuan. Tujuan itu untuk membedakan apakah untuk mengakses keadilan atau hanya untuk viralitas. Juga terkait kode etik siapa yang akan ditayangkan sebab dalam etika jurnalisme itu menyangkut bagiamana seseorang memberikan inform consent. Di sini ada sisi yang terlepas, bagaimana mempublikasikan terkait viralitas. Harusnya minta konfirmasi kepada yang bersangkutan dan kalau ada keluarga maka harus minta konfirmasi pula. Sayangnya, pengetahuan tersebut tidak banyak diketahui oleh masyarakat.
Fitri menambahkan bahwa dalam publikasi, tidak boleh asal comot. Apalagi beritanya plagiat, yang tidak mencantumkan sumber. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebab itu melanggar hak-hak seseorang.Jejak digital itu suatu hari akan muncul. Bukan hanya dengan keluarga terdekat tetapi diketahui orang secara umum. Ada kode etik bagi seorang jurnalis terkait pemberitaan. Contoh ketika jurnalis memberitakan tentang bunuh diri atau memberitakan tentang perang pasti ada disclaimer atau peringatan trigger.
Hanum sebagai moderator kemudian bertanya apakah sistem hukum terlalu bergantung pada keviralan? Jawaban Fitri adalah iya dan tidak. Tinggal bagaimana untuk melakukan acces to justice. Ia mencontohkan salah satunya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) misalnya pada kasus TPKS. Ada yang betul-betul harus dipegang yakni kerahasiaan. Hal ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan, soal psikologis. Di satu sisi Aparat Penegak Hukum (APH) perlu menyimpan atau menghapus berkaitan soal rekam digital misalnya, gunanya untuk penguat kasus tersebut, itu hanya diberikan pada orang yang berkepentingan saja. Artinya siapa yang bisa mengakses, siapa yang bisa mengikuti, ada ketentuannya. Bahkan seorang pendamping hukum pun tidak boleh menyebut nama, dan bahkan nama wilayah. Seseorang bisa dituntut berkaitan kode etik.
SPEK-HAM dalam menangani sebuah kasus terkait konten di TikTok, pernah mengirim surat ke kepolisian dan dalam waktu yang sama juga ditembuskan Kapolda, Kapolri meminta untuk melakukan take down dan jika tidak dilakukan maka ada tuntutan.
Lantas pertanyaannya, apa risiko viralitas dalam peradilan? Dan apakah berdampak pada persidangan. Fitri menjawab bahwa keviralan kasus memperkuat bukti karena diakui yakni bukti digital, kalau berkaitan arahnya ke hukum. Kalau ada hal-hal salah satu sisi, ada Undang-Undang Informasi, Transaksi Elektronik ( ITE) dan KUHP. Perlu dibuktikan pula apakah konten di dalamnya berpengaruh di masyarakat. Karena belum ada yang melihat dampak di masyarakat terkait berita viral tersebut sebab yang dilihat adalah dampak viralnya.
Hal lain adalah bagaimana situasi dan kondisi di masyarakat. Kalau kemudian harus viral, lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak memahami media sosial. “Kalau terus-menerus berlangsung ini bahwa satu sisi, ada penegakan hukum tetapi kok harus viral dulu,”terang Fitri.
Lantas bagaimana publikasi menguatkan publik? Jawabannya adalah tergantung caption atau deskripsi singkat. Karena ada caption yang tidak memiliki perspektif kepada korban. Akhirnya bukan empati yang didapatkan tetapi kata-kata stigma, misalnya terkait penampilan korban, kata-kata yang menyakitkan yang kemudian sesuatu yang menyakitkan bagi korban : gambar yang dipertontonkan, visual yang diperlihatkan. Tentu hal ini berpengaruh. “Masyarakat kita hanya mengikuti dan cepat sekali merespon tanpa mempertimbangkan apa yang dilakukan. Tanpa ada deskripsi singkat yang berperspektif kepada korban,”jelas Fitri. Ia juga memberikan jawaban untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian media sosial, yakni agar masyarakat banyak belajar literasi digital. Sehingga tahu, apa yang penting saat memberitakan, apa yang kaitannya dengan FOMO. Karena situasi saat ini jika melihat perkembangan sangat cepat dan mendadak yang tidak dibarengi literasi, apalagi tekanan globalisasi, dan kapitalisme yang tidak dipahami, semua orang pegang gawai tapi tidak tahu manfaatnya.
Lantas, bagamana solusi atau tips, jika berhadapan dengan korban kekerasan? Jawabnya adalah : jangan menghakimi, cukup menjadi pendengar yang baik, kalau menerima cerita tanpa menyalahkan korban, cukup mempercayai, tanpa harus menginformasikan ke orang lain.Jika butuh rujukan, maka akseskan mereka dengan mencari informasi ke lembaga layanan yang melakukan pendampingan dan yang terakhir adalah memperbanyak literasi.(Ast)