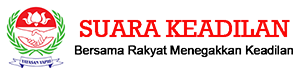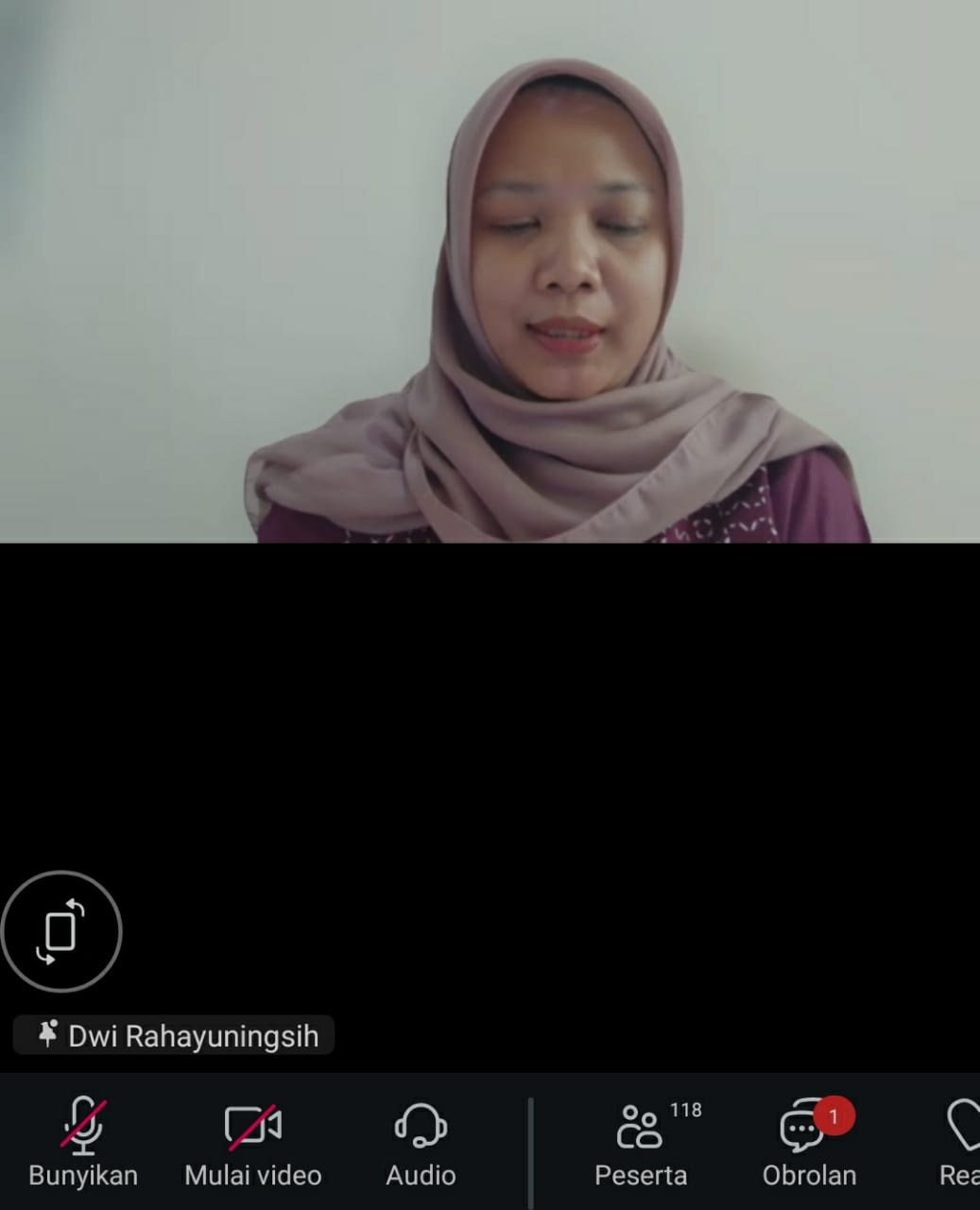Penetapan Fungsi Hutan Adat (HA) harus mengikuti mekanisme adat sebagai subjek hukum, tidak lagi mengikuti mekanisme negara. Yang terjadi saat ini adalah, sudah masuk kawasan hutan adat namun mekanisme masih sebagai hutan negara (lindung, konservasi, dan lainnya). Padahal masyarakat adat sudah memiliki fungsi zonasinya sendiri. Demikian dikatakan oleh salah seorang peserta workshop harmonisasi kebijakan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat oleh Dewan Kehutanan Nasional didukung Asia Foundation, Rabu (9/7).
Enika, peserta lain menyatakan bahwa ia dan kelompoknya mendorong pengakuan HA sejak 2002 menggunakan Surat Keputusan (SK) Bupati, sekarang setelah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ia mengulang dari awal untuk mengajukan Masyarakat Hukum Adat baru masuk Hutan Adat sebab HA ini adalah hak kelola tapi kalau masuk Perhutanan Sosial (PS), dia jadinya hanya bisa akses kelola. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang rimba (suku anak dalam) yang dia hidup secara nomaden sehingga tidak ada hutan adat, yang ada hanya ruang jelajah? Maka usulan revisi Permen LHK nomor 9 Tahun 2021 harus mempertimbangkan juga masyarakat adat yang masih nomaden.
Kalau sudah ada Masyarakat Hutan Adat (MHA) maka pemerintah daerah wajib melindungi hak- hak masyarakat hukum adat termasuk hutan adat. MHA harus melakukan pemetaan wilayah. Jika kemudian di MHA ada “kehadiran pemerintah” lantas jika ada investor yang tiba-tiba melakukan kegiatan dalam HA, lalu bagaimana?
Moderator workshop sebelum memulai acara merangkum hasil diskusi sebelumnya yakni dari para pihak yakni akademisi dan NGO, Permen LHK belum menjadi solusi konflik Perhutanan Sosial, Permen belum diatur memadai dalam regulasi, pendampingan perlu diperkuat, Perhutanan Sosial (PS) di kawasan konservasi dan areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dinilai sebagai kemunduran, verifikasi sebaiknya mencakup pemetaan areal, bukan sekedar cek administrasi, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan perlu diperjelas peran, fungsi dan benefit sharingnya, aspek kawasan masih tertinggal, aspek bisnis perlu insentif, modal, dan dukungan pentahelix.
Bambang Hendroyono (Ketum Presidium DKN), dalam sambutannya mengatakan jangan ada lagi disharmoni antar regulasi. Antara Undang-undang Cipta Kerja (UUCK), PP 23, dan Permen 9 tentang Hukum Adat perlu dilihat kembali dimana disharmoninya. Ia juga mengatakan UUCK harus mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 34 dan 35, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) melalui Perda kurang maksimal, ada peran Bupati dan Gubernur yang perlu dibuat Surat Keputusan (SK), Negara harus hadir sehingga terwujud percepatan perhutanan sosial, Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat harus diprioritaskan.
Ricardo Simarmata dari Forum Komunikasi Kehutanan Sosial (FKKM) menyampaikan hasil kajian yang difokuskan pada aspek hukum. Ia juga menyatakan bahwa peraturan perundangan-undangan dulu tidak sebanyak saat ini. Capaian penetapan HA masih jauh dari target, adanya pergeseran pengakuan deklaratoir dan ada disharmoni regulasi tentang pengakuan (Perda atau jenis produk hukum daerah). Dan bahwa seharusnya ada penetapan hutan adat dan area hutan adat (area ulayat atau area kelola) serta enetapan subjek dan objek sekaligus.
Sedangkan dari Ditjend Perhutanan Sosial mengatakan bahwa latar belakang revisi UU 41/1999 dan Permen LHK No.9/2021 adalah untuk percepatan dan peningkatan kualitas perhutanan sosial dan peningkatan kolaborasi.
Dari workshop tersebut kemudian bisa disimpulkan bahwa, Permen LHK nomor 9 tahun 2021 harus direvisi dengan mengeluarkan Skema Hutan Adat yang berdiri sendiri, negara hadir dalam bentuk perlindungan dan berperan agar wilayah adat tidak berubah fungsi, proses validasi dan verifikasi dokumen serta lapangan baik pengakuan dan perlindungan MHA dan Penetapan Hutan Adat dapat dilakukan bersamaan (berjalan paralel), jadikan putusan MK no. 35 sebagai payung hukum dan mulailah menyusun naskah akademik revisi PP 23. (Yosi Krisharyawan/Ast)