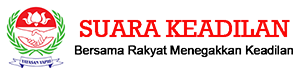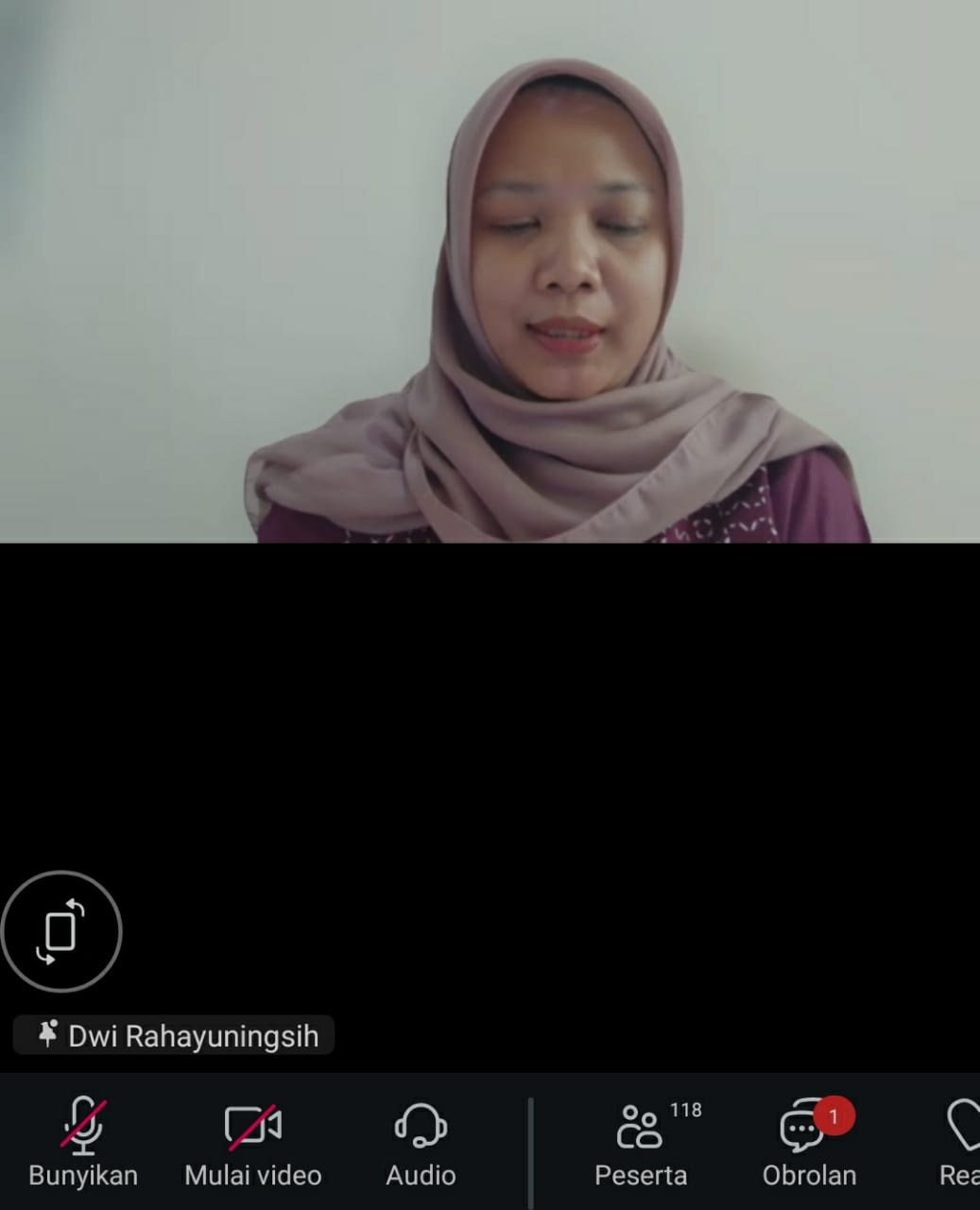Krisis iklim yang saat ini dialami oleh semua makhluk, seringkali dipahami sebagai kondisi darurat yang datang dari alam. Padahal sebenarnya akibat dari aktivitas manusia yang mengakibatkan dampak. Hal itu sudah bisa dilacak jauh ke belakang ketika manusia memiliki peradaban untuk membuka hutan. Lantas di abad 15-16 ada revolusi pengetahuan sehingga terciptalah mesin, dan jejak karbon bertambah.
Lalu siapa yang memformulasikan perubahan iklim?Alexander von Humbolt peneliti dari Jerman melakukan perjalanan di Amerika Latin dan di sana ia menemukan ada pergerakan tumbuhan yang menuju ke tempat tinggi. Selain itu, ada crossing tiping points atau menabrak batas yang tidak bisa diperbaiki lagi, meninggalnya terumbu karang di Australia karena ketahanan pangan yang berasal dari laut menurun. Demikian dikatakan Dewi Candraningrum dalam diskusi secara daring tematik Krisis Iklim dan Keadilan Gender pada Jumat (18/7) yang dipandu oleh Maulani Rotinsulu.
Dewi mengatakan bahwa krisis iklim mengakibatkan suhu bumi, laut, mengalami kenaikan. Contohnya : curah hujan yang di Eropa di bawah 200 ml menjadi 800 ml per tahun. Krisis iklim juga berakibat terganggunya sistem hidrologi.
"Di Indonesia hilangnya tutupan hutan untuk sawit,juga karena tambang dan untuk pembangunan infrastruktur. Dulu sudah dikenalkan istilah ecofeminisme, bahkan kami menerbitkan serial ecofeminism tapi tidak ada yang peduli, "ungkap Dewi.
Menurut catatan, dunia mengalami gelombang panas pertama dan jutaan orang mati. Dan fakta bencana Iklim di Indonesia adalah : 1. 2.989 bencana iklim per tahun (BNPB 2023), 2. 99% bencana hidrometerologi banjir, longsor dan kekeringan dan emisi karbon naik 30% sejak 2000 (KLHK), 6 dari 10 provinsi berdampak sebab wilayah agraris dan pesisir.
Diakui memang sistem ekonomi Indonesia adalah eksploitatif, ekstratif dan ketimpangan global. Bukan isu teknokrat saja, bukan bencana alam saja, tapi isu generasi dan lintas benua. "Kita berutang pada anak cucu kita karena kita ambil apa yang ada pada mereka," tegas Dewi.
Krisis iklim, terlebih dampak pada perempuan disabilitas adalah mengalami kerentanan ganda, bahkan multi sebab mereka ditinggalkan dalam pengambilan keputusan, sistem peringatan dini, dan akses informasi. Dewi, yang juga orangtua dengan anak disabilitas mengatakan bahwa perempuan disabilitas rentan mengalami hambatan mobilitas, hambatan evakuasi, dalam pemberian bantuan juga mengalami diskriminasi, risiko di tempat pengungsian alami eksploitasi, akses layanan kesehatan dan kesejahteraan, dan pendamping banyak ditinggalkan dan dianggap tidak penting.
Satu catatan penting lagi, 7, 1 juta perempuan disabilitas di Indonesia (BPS 2023) hidup di wilayah rawan bencana misalnya gunung Merap, pesisir utara Jawa, NTT, Kalimantan, dan lainnya. Mereka semua hampir tidak dilibatkan dalam kebijakan adaptasi iklim.
Lantas apa yang bisa dilakukan? Begitu pertanyaan salah satu peserta yang langsung dijawab yakni dengan melibatkan komunitas adat karena mereka penjaga paling baik dari hutannya, mendukung moratorium sawit dan transisi energi bersih, menggunakan metode revitalisasi sistem air misalnya lumbung air, sumur resapan, kolam tadah hujan, dan terasering.
Sedangkan metode dalam menggali pengetahuan adat bisa dengan brainstroming, mendokumentasikan life story atau kisah perjalanan hidup.Dewi pernah melakukan penelitian di Desa Keningar. Di dekatnya ada desa Bantengan yang pada zaman dulu memiliki banyak mata air yang disediakan alam untuk hewan banteng yang banyak hidup di sana. Namun, eksploitasi alam telah mengakibatkan mata air banyak yang hilang.
"Bencana ke depan tidak terbantahkan maka kita harus beradaptasi. Kalau kemanusiaan kita shut down one day, atau 1000 tahun, tidak akan mengembalikan adanya terumbu karang dan apakah poin hak air bersih dan sanitasi terkaver? Maka dibutuhkan kapasitas beradaptasi dan mobilitas dan evakuasi kesehatan serta pengetahuan dasar, "pungkas Dewi. (Ast)