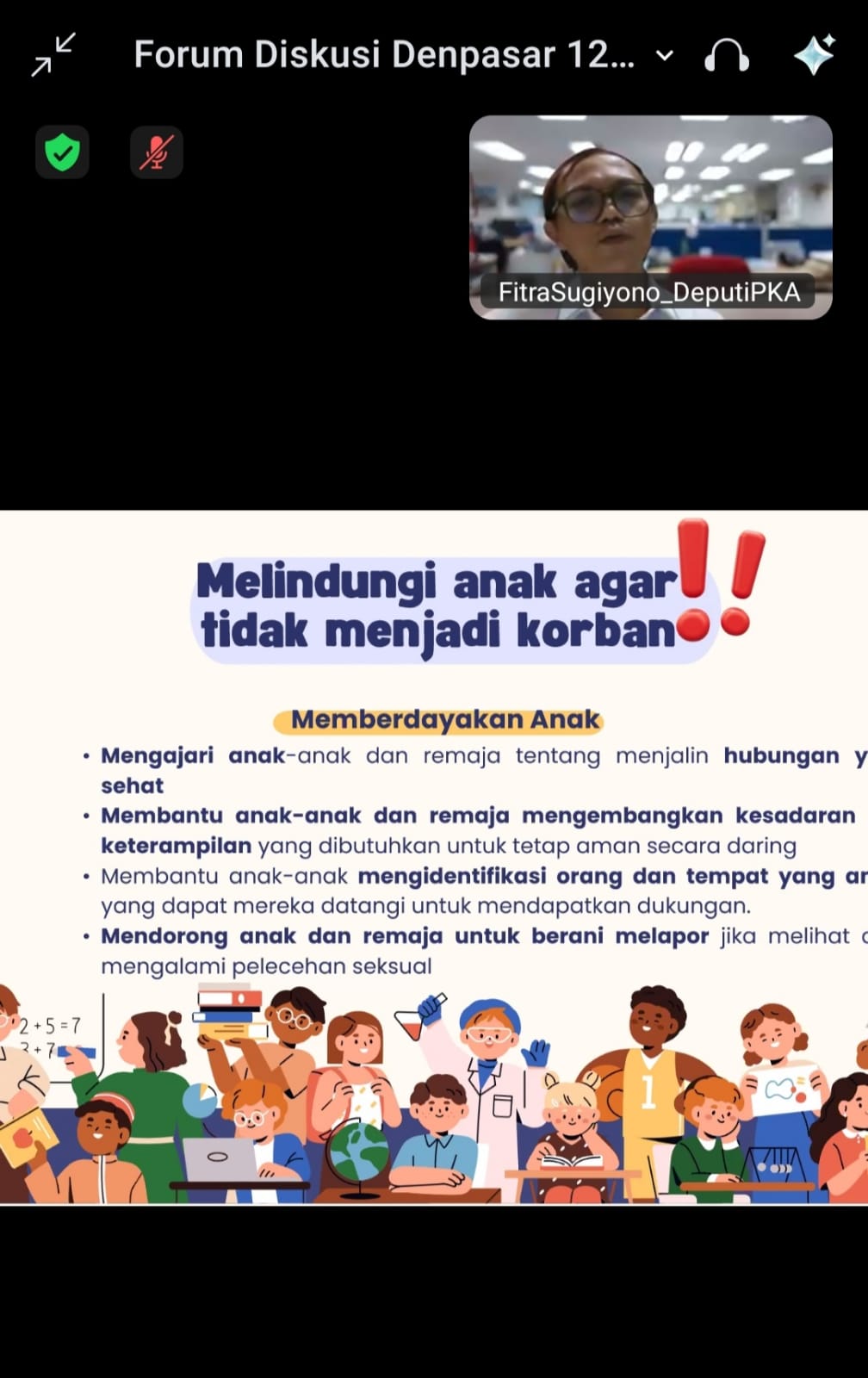International Women's Day (IWD) atau Hari Perempuan Sedunia yang setiap tahun diperingati pada tanggal 8 Maret menandai keberanian bagi perempuan dan anak perempuan seluruh dunia untuk bangkit dan menuntut tindakan yang menjadikan dunia lebih setara dan lebih baik bagi semua orang. Momen ini penting bagi masyarakat global untuk merayakan pencapaian perempuan di berbagai bidang. Selain itu, IWD juga menjadi momentum untuk menyerukan tindakan nyata dalam mempercepat tercapainya kesetaraan gender.
Dilansir dari laman International Women's Day, tema Hari Perempuan Internasional tahun 2025 adalah “Accelerate Action” atau “Percepat Aksi”. Tema ini menekankan pentingnya langkah cepat, konkret, dan kolaboratif untuk mengatasi hambatan yang menghalangi kesetaraan gender di seluruh dunia.
Menurut laporan dari World Economic Forum, dengan laju kemajuan saat ini, dunia membutuhkan waktu hingga tahun 2158- lebih dari lima generasi- untuk mencapai kesetaraan gender penuh. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa upaya yang lebih signifikan, kesenjangan gender akan terus berlangsung dan bahkan dapat memburuk. Kesetaraan gender bukan hanya masalah perempuan, tetapi juga merupakan isu yang memengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara global.
Ketimpangan gender dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti representasi perempuan di bidang politik, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, hingga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Oleh karena itu, tema “Accelerate Action” menjadi panggilan bagi individu, organisasi, dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan perubahan yang berarti.
Percepatan aksi seharusnya bukan menjadi hal yang sulit di era serba digitalisasi seperti saat ini. Berbagai media bisa menjadi alat untuk upaya mencapai kesetaraan, belum lagi ketika diikuti oleh kreatifitas masyarakat khususnya anak muda. Demikian obrolan yang terjadi di siaran podcast Ngobrol Bareng Yaphi (NGOPHI) 18/3 yang disiarkan oleh YouTube Yayasan Yaphi.
NGO-PHI edisi ke-19 bersama Dorkas Febria dan Christina Vera sebagai host menghadirkan Luxy Nabela Farez, founder Pusat Studi Perempuan Solo (Pukaps) dan Ika Hana Pertiwi, relawan Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Solo Raya. Tak hanya mengulik bagaimana seharusnya terjadi kesetaraan tetapi juga inklusivitas seperti yang diceritakan oleh Luxy bagaimana Pukaps mengakomodir di setiap acara diskusi yang melibatkan teman Tuli maka mereka berusaha menghadirkan Juru Bahasa Isyarat (JBI) meski tantangannya adalah soal biaya sebab kelompoknya merupakan komunitas, yang belum memiliki projek secara khusus mengangkat isu difabel.
Luxy menambahkan di IWD tahun ini komunitasnya secara internal melakukan refleksi bahwa melihat ke dalam diri masing-masing perempuan adalah awal langkah, sebelum mengadvokasi orang lain sehingga tercapai kesetaraan. Lain cerita Hana yang mengaku bahwa IWD tahun ini adalah yang pertama ia peringati bersama komunitas, dan ia mengartikan bahwa makna IWD adalah kelahiran kembali atau kelahiran kedua bagi perempuan. Kebetulan Hana dan KPSI Simpul Solo Raya belum lama ini juga mendapatkan pelatihan tentang kesetaraan gender serta Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) sehingga nyambung ketika itu menjadi bahasan di IWD kali ini.
NGO-PHI tak hanya berbincang tentang bagaimana gerakan perempuan untuk kesetaraan dengan cara berjejaring atau berkolaborasi tetapi juga merembuk tentang fenomena yang saat ini tengah mencuat yakni "We Listen, We Don't Judge". Istilah ini pertama kami muncul di media sosial tiktok. Lalu berkembang pula di Instagram yang kemudian memunculkan kalau bisa dikatakan adalah sebuah gerakan tentang bagaimana perilaku mendengarkan tanpa menghakimi. "Semudah mendengar, lantas tidak membandingkan cerita yang kita alami atau membandingkan cerita orang lain,"kata Luxy yang dibenarkan oleh Hana bahwa ketika kita mendengar cerita atau masalah orang lain, dengan tidak menghakimi. Bahkan kadang respon jawaban dari kita ternyata tidak mereka butuhkan. Kadang mereka hanya membutuhkan respon dalam bentuk gerakan tangan : menepuk pundak, memeluk, atau jika dilakukan lewat telepon bisa menggunakan tone-tone tertentu misal : "iya, he em" yang menunjukkan sebuah kehadiran di sana.
We Listen, We Don't Judge juga upaya untuk mengurangi penghakiman yang bahkan hadir ketika ada kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak dengan menyalahkan pakaian yang dikenakan korban atau dalih apapun dengan tujuan tetap menyalahkan perempuan.
Ngo-phi kali ini juga bercerita bahwa "We Listen and We Don't Judge" adalah upaya-upaya untuk menghapus stigma. Seperti yang diutarakan oleh Hana, bahwa sejak 2010 KPSI telah memiliki media sosial Facebook sebagai sarana edukasi bagi difabel mental. Namun seiring berjalan waktu, stigma muncul justru dilakukan oleh konten kreator misalnya dengan membuat konten yang menyudutkan difabel mental misalnya menjadikan mereka objek charity saja, atau dengan tujuan untuk konten lucu-lucuan. Berulangkali pula Hana dan komunitasnya mengingatkan di media sosial bahkan lewat japri, terkait konten-konten yang hanya mengobjektivikasi difabel mental. Dan bagaimana meminimalisir stigma difabel mental dengan memilih istilah difabel psikososial, atau Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODPP) meski di dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan dua istilah yakni Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
(Ast)