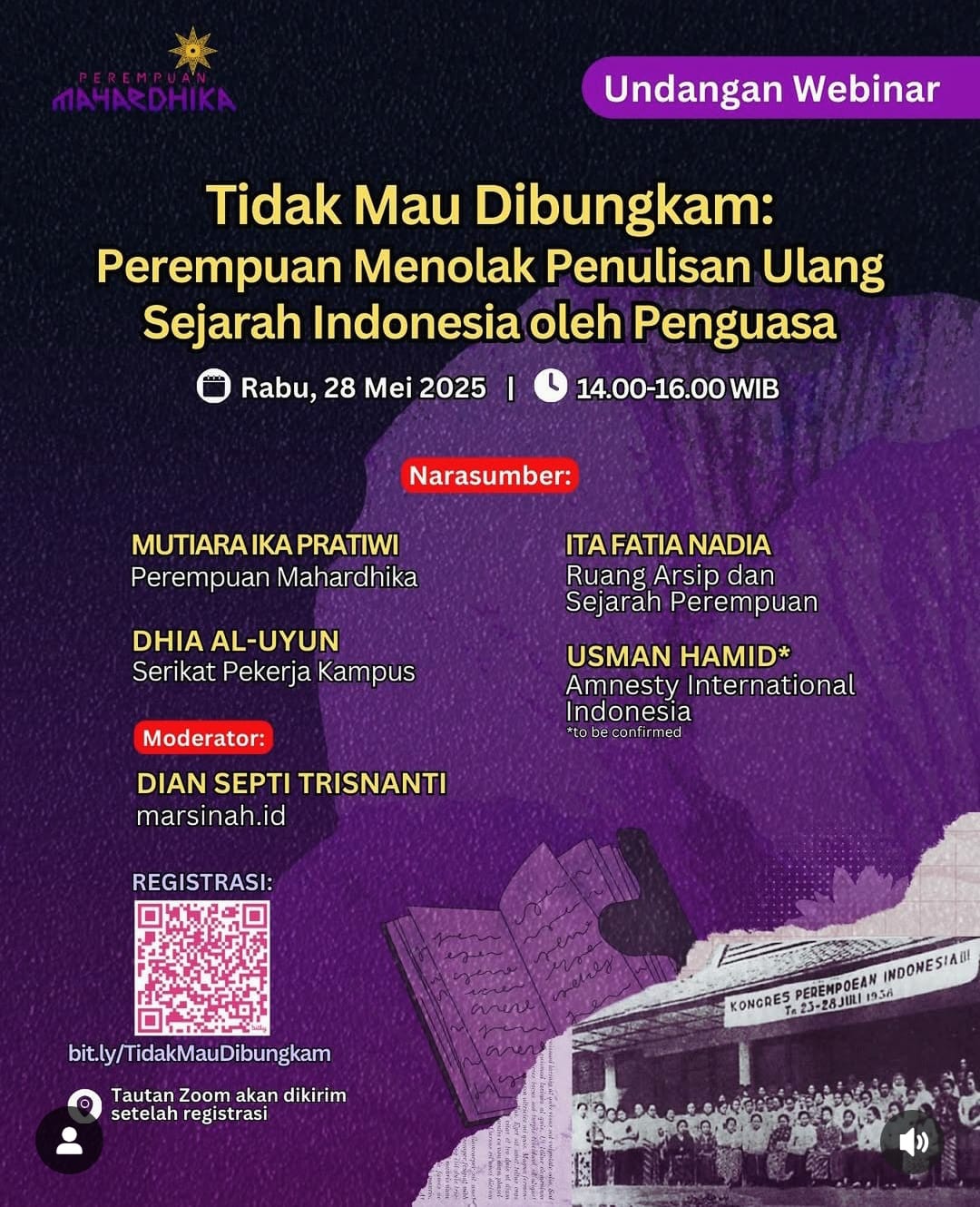Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyelenggarakan diskusi publik terkait kebijakan palsu krisis pangan, Selasa (17/9), dengan melakukan refleksi 10 tahun ini, banyak kebijakan tetapi 10 tahun ini pula muncul antitesis-antitesis kebijakan seperti krisis pangan dan lain-lain.
Seperti diketahui, pemerintahan Prabowo-Gibran, masterpiece kebijakannya adalah pangan, termasuk Food Estate. Lantas bagaimana refleksi kebijakan pangan pada 10 tahun terakhir?
Martin Hadiwijaya, Komnas FIAN yang juga anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan bahwa pembahasan terkait ini penting sebab pihaknya mengkampanyekan hak atas pangan dan bagaimana negara memastikan produksi pertanian dan pangan bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional dan rakyat. Ini catatan kalau di Konvensi Hak Ecosob mewajibkan negara salah satunya memenuhi hak atas standar hidup yang layak dan hak atas lingkungan. Selain itu perlu diluruskan tentang konsep hak atas pangan. Konsep inti adalah kewajiban negara melakukan langkah-langkah untuk memastikan hak atas pangan dan gizi. Kedua larangan untuk tindakan kemunduran sebab berdasar catahu KPA ada kemunduran yakni meningkatnya petani gurem dan banyak hal lain dilakukan pemerintah yang melanggar HAM seperti berkurangnya lahan pertanian karena luas hutan dijadikan lahan sawit dan tambang yang jumlahnya bertambah serta dampak krisis iklim bagi masyarakat pesisir.
Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat sangat minimun dan mereka mengeruk sumber daya yang ada. Konsep ini telah banyak terjadi pelanggaran oleh pemerintah saat ini. Harusnya perlu untuk merumuskan kembali agar hak pangan dan gizi bisa terpenuhi. Ini artinya apakah program makan siang tidak menjawab pertanyaan?
"Kita melihat program ini untuk memenuhi hak atas pangan dan gizi. Sebab tidak ada proses yang clear. Sasarannya perempuan dan ibu hamil dan beberapa kelompok rentan. Jebakan yang salah karena untuk menjawab stunting tapi stunting ada proses sirkuler yang harus diputus dengan memberi pangan ibu hamil, "terang Martin.
Menurutnya program makan gratis tidak melihat masalah pra produksi dan pasca produksi dari pangan. Anggaran 70 Triliun dicampur dengan anggaran pendidikan. Tidak ada desentralisasi yang bisa saja akan menjadi masalah di kemudian hari. Di India, ada pelintasan publik, yang tidak hanya masyarakat sipil memasak dan membaginya tapi ada dewan pangan yang terdiri dari masyarakat sipil dan pemerintah. Ada satu billion dollar budget nasional.
Juga terjadi di Brazil untuk program, 30% untuk beli hasil dari pertanian keluarga. Kalau dilihat tren yang saat ini berjalan adalah food estate. Dan di sana ada multifungsisasi aparat keamanan : ada upaya membangun dapur sehat. Artinya ada food estate ala-ala aparat. Ini adalah sebuah ancaman besar. Makan gizi gratis bisa gagal, karena ada ancaman korupsi dan ancaman jerat korporasi. Dalam kampanye makan gizi gratis ada e commerce yang muncul. Itu jerat korporasi untuk mengambil keuntungan. Sebaiknya makan gizi gratis harus terintegrasi dengan sekolah. Ada makanan yang dimasak di dapur mereka sendiri untuk setiap kali memasak. "Yang saya lihat, program makan siang sekolah mengintegrasikan keluarga sekolah ikut terlibat di Brazil. Kita perlu untuk mengkonsolidasikan kembali, "jelas Martin.
Persoalan lainnya adalah Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Pangan, Undang-undang tentang Petani bahkan Undang-undang tentang Sawah Berkelanjutan tetapi 10 tahun belakangan ini tidak ada political will dari pemerintahan karena dianggap tidak menguntungkan mereka. Itu hampir mirip bagaimana Undang-undang Pokok Agraria yang tidak dilaksanakan. Seperti kiasan yang disampaikan oleh WALHI bahwa kawasan industri lebih luas dibanding kawasan perikanan. Juga tidak ada peraturan dari Undang-undang perlindungan petani yang gunanya untuk panduan perlindungan petani dan nelayan dan itu tidak dilakukan pemerintah karena dianggap tidak menguntungkan mereka.
Lantas apakah Food Estate adalah Solusi? M. A. Mahrus darI PUSAKA menjawab bahwa saat ini bergaung dalam koalisi soal food estate termasuk FIAN. Ada ladang gambut dan lainnya. Lantas bagaimana dengan Papua? masuknya project ini seperti pendidikan. Jauh sebelumnya food estate di Papua sudah ada namun gagal.
Tahun 2022 ada beberapa temuan yakni beberapa sumber pangan berkurang karena alih fungsi hutan dan membawa mereka pada temuan tentang gizi dan kesehatan dan terseret dalam aroma uang. Berminggu-minggu ke lahan perusahaan hanya untuk mengais sisa-sisa. Lantas ada pula satu kejadian proses pelepasan tanah di rumah yang dipenuhi oleh aparat.
Mengapa TNI ikut? Karena Inpres membolehkan bahkan jajarannya, dan ini semakin menambah rumit konflik.
Dalam diskusi yang menghadirkan host Benni Wijaya lantas muncul pertanyaan terkait food estate apakah problematik atau gagal di lapangan? Ada pernyataan bahwa ini soal paradigma hukum. Kajian hukum menjadi masalah karena dia hanya digunakan sebagai instrumen pembangunan dan dicangkok dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lantas bagaimana dengan food estate? Tentang hal itu ternyata bukan hanya kesalahan praktik saja, tetapi dalam konteks di Papua tidak begitu dan di tempat lain tidak sama.
Ada Peraturan Pemerintah yang mengatakan bahwa negara bisa mengambil alih lahan hanya karena ia ditetapkan sebagai PSN. Ini yang kemudian disebut otokratik legalism dalam kebijakan negara. Tujuannya untuk memperbesar kekuasaan moda dan kekuasaan politik hanya untuk kelompoknya. Otokratik legalism ini, dia berjalan sesuai hukum dan seolah sudah benar, tetapi sebenarnya sudah melanggar prinsip negara hukum bahkan ke arah otoritarianisme.
Hasil Temuan Kompas yang Justru ada Kebijakan Penyeragaman Korporasi Pangan dan Import
Ahmad Arif, jurnalis Kompas dalam diskusi menjabarkan bagaimana pengamatannya di lapangan. Dari kasus di Papua menurutnya yang mestinya diubah adalah haluannya. Mereka dipaksa menanam padi, contohnya adalah masyarakat Merauke yang tidak membeli jadinya membeli. Secara pengentasan gizi buruk, hasil buruan dijual untuk beli beras. Yang untuk anak anak mereka tinggal kulitnya saja. Mereka makan dengan kualitas lebih buruk dari sebelumnya.
Di daerah Sulawesi Tenggara cetak sawah juga terjadi. Menurut Arif, konsep pangan yang dijalankan pemerintah mengubah sistem pangan yang ada sehingga terjadi defisit beras dan konsumsi meningkat. Sepuluh tahun terakhir, dengan naik turun angka impor, defisit beras semakin meningkat . Masyarakat yang sistem makan semula bernama dipaksa beras. Dan hampir semua wilayah tidak berhasil karena kondisi lahan beda. Mengubah gambut di Kalimantan menjadi sawah butuh belasan tahun dan produksinya tidak sebagus di Jawa dan Bali. Inilah contoh kegagalan food estate dan tidak ada evaluasi.
Arif menambahkan bahwa peminggiran pangan sudah ada sejak zaman kolonial misalnya terjadi di Mentawai. Sistem pangan diubah dengan cetak sawah supaya bisa dikendalikan. NTT juga begitu dan di zaman orde Baru jadi komoditi politik. Orang yang masih makanan lokal kemudian dianggap miskin. Itu mindsetnya yang ditanamkan. Dari semua yang terjadi, maka literasi tentang pangan wajib diberikan kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah harus berubah. Jadi selama ini padi dipakai untuk kepentingan politik yakni bantuan beras yang memicu petani malas menanam tanaman lokal. Kebijakan pemerintah tidak mendorong itu untuk membuat kebijakan serius guna mengembangkan pangan lokal. Sehingga menjadikan Indonesia importir gandum terbesar di dunia. Impor beras Indonesia 2-4 juta ton dan terakhir di angka 5 juta. Harusnya ada upaya pemerintah mendorong pangan lokal sebagaimana dilakuan untuk padi misalnya, harusnya bisa dilakukan.
Persoalan sistem pengelolaan pangan konon dikelola mafia pangan yang ugal-ugalan. Lantas bagaimana temuan Ombudsman? Apa saja temuannya?
Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman RI menyatakan bahwa tugasnya pada dasarnya : pencegahan dan pemberantasan mal administrasi melalui metode pengawasan.
Ia melihat bahwa terjadi kehilangan konektivitas antara petani dan importir padahal sesungguhnya bisa dibangun misalnya industri bawang hitam dari bahan bawang putih dari China.
Menurut Yeka problem yang dihadapi saat ini adalah tingginya demand dan lemotnya lahan yang terbatas. "Satu-satunya food estate yang berhasil ya zaman Soeharto dengan program transmigrasi, " ungkapnya.
Sekarang yang menjadi kekhawatiran Ombudsman adalah mengawasi dan korektif tapi tidak cukup membatasi kebijakan publik. Lahan gambut sejuta hektar mengapa ada TNI? Menurutnya secara pribadi, pemerintah itu setengah memaksa "Pokok e harus berhasil" karena pemerintah itu modelnya makin dihina makin berusaha untuk gagal. Jadi tujuannya untuk gagal.
Lantas bagaimana upaya mensejahterakan petani? Subsidi pupuk misal, dan bagaimana pertanggungjawaban? Jawabnya adalah ribet karena sistem pendataan tidak dibangun dengan basis transparansi. Di Pemilu 5 tahun ada program pemutakhiran data yang nilainya 6 T. Kemensos juga punya data dipakai untuk bagi-bagi sembako dan mereka punya tenaga pendamping di setiap desa. Namun untuk pupuk tidak ada. Pupuk yang kebutuhannya segede itu tidak ada instansi pemerintah yang bertanggung-jawab. "Pembangunan di bidang pertanian dibiarkan karena tidak jelas. Dulu ada penyuluh yang ada komando, dengan program jelas. Sekarang tidak ada. Mengapa? karena otonomi daerah. Kemiskinan ini karena ada otonomi daerah. Tetapi ketika kita tanya persoalan bukan hanya pupuk tapi pengairan dianggap pertanian bukan wajib. Begitu jawaban dinas. Yang dianggap wajib :pendidikan, jalan tol saja, "ungkap Yeka.
Padahal menurutnya lagi, kalau kita impor itu artinya di negara asalnya sana mestinya kelebihan produksi dan harusnya sampai di sini harganya murah, mengapa mahal-mahal? Karena ada fee tertentu. "Bagi saya sistem demokrasi ini bertanggung jawab pada pemerintahan, " ungkap Yeka lagi.
Dewi Kartika, Sekjend KPA menyatakan bahwa pada kuartal 1,2,3 sektor pertanian masih diminati dan 148 juta orang masih bekerja di sektor pertanian. Namun nyatanya ada sistem pertanian dan pangan sejak awal salah kaprah karena tidak menyentuh hal-hal yang penting sejak awal.
Problem secara nasional dan global ketahanan pangan digembar-gemborkan gemborkan, padahal stok pangan yang ada itu tidak cukup karena tidak membicarakan produsen pangan yakni petani dan nelayan.
Sektor pertanian petani kita semakin kecil dan saat ini ada 17 juta petani gurem. Guremisasi belum ditambahkan buruh tani dan petani penggarap. Mereka masuk hang mana?
Menurut Dewi, Food estate dan makan siang gratis adalah program yang sebenarnya adalah pemiskinan petani yang sistemik dari hulu ke hilir dibikin sistem . Bagaimana soal beban mafia tanah yang selalu ketemu oligarki dan di tanah politik, itulah yang sukses menggolkan Undang-undang Cipta Karya, maka menurut Dewi, tidak heran kalau program ketahanan pangan pelaksananya adalah tentara.
Dari sistem pangan dibuka kemudian dibuka kran impor dan ini sistemik sekali. Sensus pertanian yang dilakukan pemerintah sudah ada guremisasi karena petani dijauhkan dari alat produksinya yakni tanah. Lantas pupuk menjadi bisnis pengusaha. Kartu Tani dibagi tetapi tidak bisa untuk mengakses pupuk. Artinya semua sistem dibikin sedemikian rupa sehingga petani termarjinalisasi.
"Maka penting untuk dicatat soal kemandirian bangsa kita guna memproduksi pertanian sendiri. Butuh perubahan paradigma, kultur, kebijakan bahwa produksi pangan diproduksi oleh pertanian sendiri, " pungkas Dewi Kartika. (Ast)