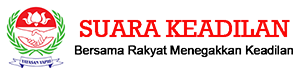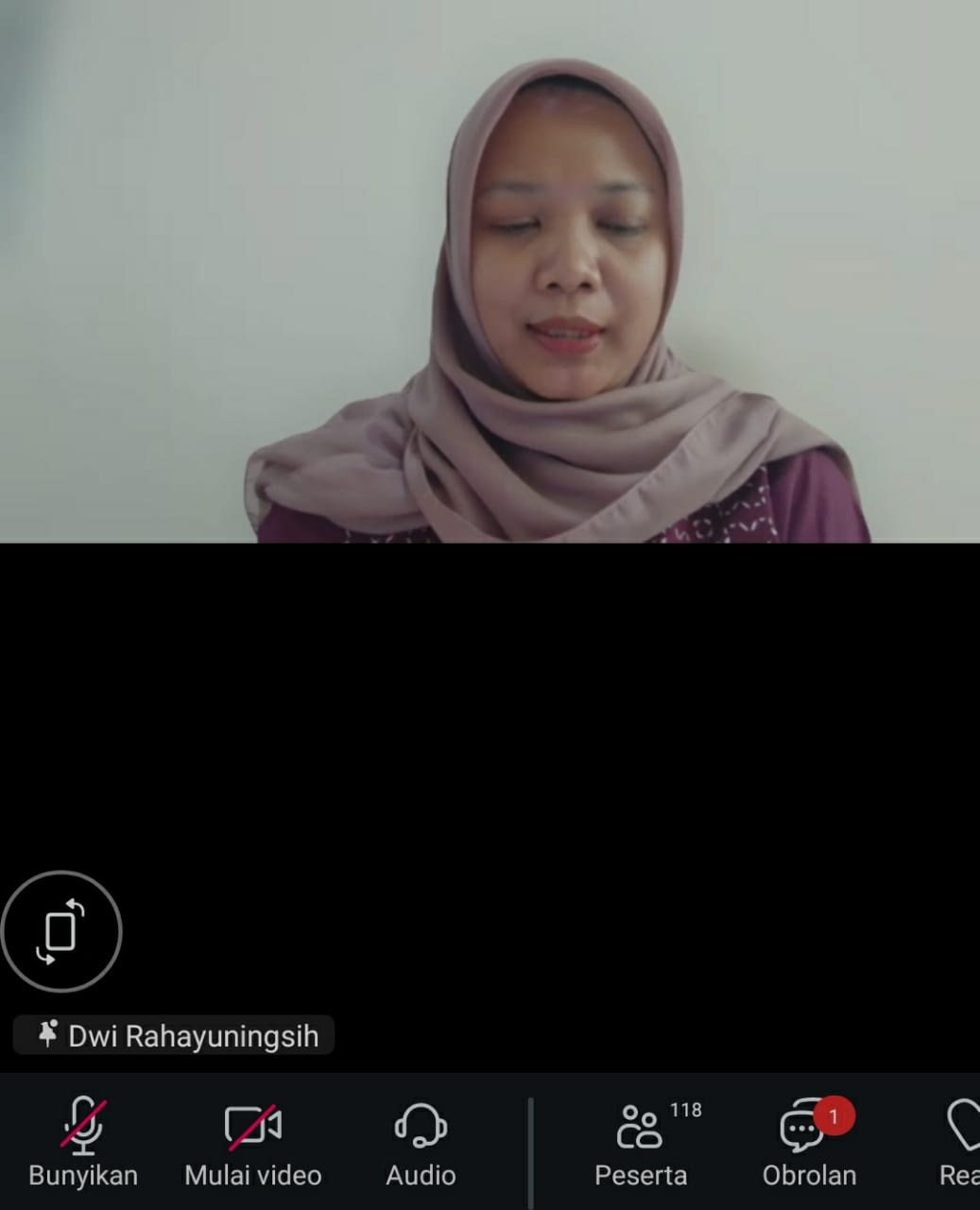Restorative Justice. Istilah ini sedang marak menjadi bahan pembicaraan diberbagai media setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membahasnya dengan memberikan contoh yang dinilai tidak tepat.
Dalam Rapim Polri yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2021, Mahfud MD membahas mengenai prinsip Restorative Justice atau keadilan restorasi untuk menciptakan harmoni publik. Menurutnya Restorative Justice merupakan cerminan budaya hukum Indonesia yang tidak hanya menekankan pada ‘mencari kemenangan’ tetapi bagaimana hukum dapat menciptakan harmoni dan kebersamaan. Mahfud MD memberikan contoh penerapan Restorative Justice pada kasus perkosaan, "Misalnya begini, ada Siti namanya diperkosa, kalau mau hukum tegas, pemerkosanya si Amin tangkap masuk pengadilan, selesai, tapi Restorative Justice tidak bicara itu, Restorative Justice mengatakan ini kalau kita nangkap Amin si pemerkosa lalu diumumkan bahwa dia memerkosa si Siti, keluarga Siti hancur. Oleh sebab itu dulu di hukum adat itu ada istilah sudah diam-diam saja kamu lari, biar orang nggak tahu, maka dulu ada kawin lari, untuk apa? restorative, agar orang tidak ribut, agar yang diperkosa tidak malu terhadap seluruh kampung, kawin di sana, di luar sana. Itu contoh Restorative Justice, membangun harmoni.” Pernyataan Mahfud MD inilah yang mengundang kritik dari berbagai pihak.
Paradigma Restorative Justice memang menjadi lensa baru di tengah penegakan hukum di Indonesia yang masih terkesan hanya sebagai alat memenjarakan pelaku tindak pidana tanpa memedulikan hak-hak yang harus didapatkan oleh korban tindak pidana. Namun, sudah tepatkah ketika penerapan Restorative Justice hanya dipahami dengan batasan ‘tidak memenjarakan pelaku’ dan dalam kasus perkosaan justru diterapkan dengan cara menikahkan pelaku dengan penyintas kekerasan?
Prinsip Restorative Justice semakin dikenal di Indonesia sejak secara tertulis diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip ini diterapkan secara teknis melalui proses diversi. Hal yang paling mendasar dari prinsip ini adalah upaya untuk memulihkan korban, pelaku, dan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana. Bahkan tidak hanya termaktub di dalam hukum nasional, prinsip Restorative Justice juga tampak di dalam penerapan hukum adat yang ada di beberapa wilayah Indonesia, seperti: Peradilan Gampong di Aceh, awig-awig di Bali maupun budaya bakar batu di Papua.
Menurut Eva Achjani Zulfa (2011:75), tujuan pelaksanaan Restorative Justice ada dua yaitu: 1.Tujuan utama dari pelaksanaan Restorative Justice adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana. 2, Tujuan lain yang diharapkan dari Restorative Justice adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.
Selaras dengan hal tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dalam keterangan persnya pada Kamis (18/2/2021) menyatakan bahwa nilai Restorative Justice hadir sejalan dengan gerakan penguatan hak korban, titik sentralnya adalah menyelaraskan pemulihan korban dengan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang memupuk pertanggungjawaban pelaku, untuk mencapai harmoni agar proses penyelesaian sengketa tersebut bersifat memulihkan atau restoratif. Restorative Justice bukan soal membungkam hak korban untuk mendapatkan harmoni semu di masyarakat.
Melihat dari rumusan tujuan Restorative Justice maka dapat disimpulkan bahwa menikahkan pelaku perkosaan dengan korban bukanlah penerapan yang benar dari Restorative Justice, karena hal ini tidak menciptakan harmoni yang sesungguhnya namun akan semakin menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban.
Penerapan Restorative Justice harus didasari dengan pemahaman yang benar akan prinsip dan esensinya sehingga tidak kembali menjadi pisau tajam bagi para korban yang seharusnya menjadi titik sentral dalam upaya penyelesaian yang adil.
Ubi jus ibi remedium (Di mana ada hak, disana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya apabila hak tersebut dilanggar). (Dorkas Febria Krisprianugraha)
Referensi:
Zulfa Eva Achjani. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: Lubuk Agung.
https://news.detik.com/berita/d-5379267/pernyataan-mahfud-contohkan-restorative-justice-kasus-perkosaan-dikritik/2