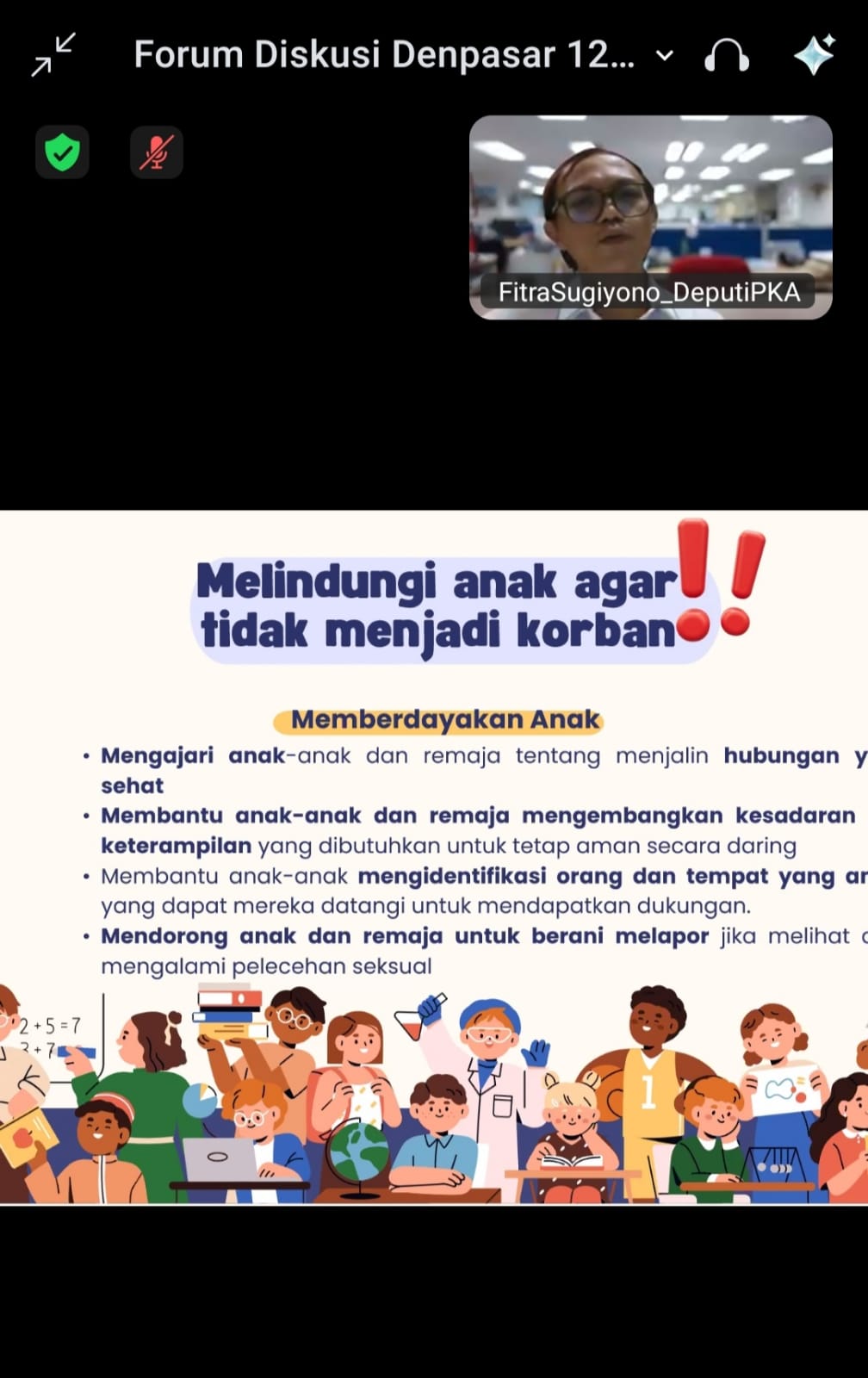Bukik Setiawan, pakar pendidikan yang saat ini tinggal di Solo dan berkhidmat di Sanggar Anak Jati (Sajati), pada acara Ngobrol Bareng Yaphi (NGO-PHI), disiarkan oleh YouTube Yayasan YAPHI, yang dipandu oleh Adi C. Kristiyanto dan Astuti di akhir Mei lalu mengatakan Sajati adalah salah satu tempat belajar yang percaya bahwa pendidikan kontekstual itu kunci masa depan anak-anak. Beberapa pertanyaan lahir dari kegelisahan tentang pendidikan, dan kami tuliskan kembali secara utuh untuk dinikmati pembaca. Semoga mencerahkan.
Astuti : Masalah mendasar apa yang dihadapi oleh masyarakat Solo utamanya, atau masyarakat urban, terkait pendidikan. Padahal kota menawarkan banyak peluang sekaligus banyak risiko buat anak-anak. Jadi di kota itu ada pertarungan antara tradisi dengan teknologi?
Bukik Setiawan : Kalau kita bicara Solo yang tradisinya kuat, kita ingin melestarikan tradisi. Tapi di sisi lain kita juga ingin beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ini terkait dengan risiko alami dan risiko buatan. Musibah yang bernama bencana itu sifatnya bencana alami misalnya pada Sungai Bengawan Solo. Sesungguhnya itu bukan sesuatu yang alamiah tapi buatan manusia. Dan pencemaran itu sesuatu yang menjadi musibah karena perilaku dan kebiasaan manusia, dan anak-anak kota, menghadapi keduanya, yakni kesempatan yang banyak dibandingkan anak desa misalnya akses belajar pada sumber belajar lewat interaksinya dengan berbagai tokoh itu jauh lebih mudah di kota.
Saya besar di Papua, 6 tahun SD ya hanya di desa itu. Interaksinya juga hanya dengan orang desa. Jadi ketika kita mendengar atau melihat di layar televisi tentang tokoh budaya atau tokoh lain, eh ngomong tentang arsitek atau desainer itu misalnya, ya hanya ada di layar televisi, sesuatu yang tidak terjangkau. Tapi ketika di Solo, interaksi dengan tokoh-tokoh, belajar tentang itu sesuatu yang yang bisa saja dilakukan, misalnya, kebetulan dengan Pak Jokowi di pasar ketemu. Atau dengan tokoh di jalanan atau di warung makan. Sesuatu kemewahan yang dimiliki oleh anak-anak kota meskipun di sisi lain ancaman risikonya juga jauh lebih besar. Masyarakat urban butuh model pendidikan yang khas, tidak bisa semata-mata yang mengikuti standar nasional.
Adi C. Kristiyanto : Kalau standar nasional itu kan standar minimal yang perlu diajarkan kepada anak-anak tetapi anak-anak menghadapi situasi yang berbeda?
Bukik Setiawan : Solo menghadapi situasi yang berbeda dibandingkan anak-anak pada umumnya. Meskipun ada yang berbeda, kita juga perlu peka bahwa anak-anak nelayan, juga anak petani itu yang butuh model pendidikan yang berbeda. Kalau pentingnya pendidikan kontekstual karena real yang dihadapi oleh anak-anak kita sesuatu yang khas dengan tempat atau wilayah hidup mereka.
Jadi lebih menarik karena di Solo ternyata tidak hanya satu budaya, yang kemudian kita temukan dan pahami karena ditulis sebagai Kota Urban, banyak orang masuk ke Solo membawa budayanya. Banyak orang masuk ke Solo membawa nilai-nilainya tentunya ini menjadi satu.
Yang memang unik dan menarik, banyak hal risiko-risiko seperti yang disampaikan ini bisa untuk bisa masuk dan melakukan intervensi terhadap masyarakat kota Surakarta. Dengan menghadapi keunikan dan ke berbagai macam yang ada, kalau pendidikan yang pada umumnya sekarang yakni reguler itu tidak masuk. Kalau istilah saya itu di satu vitamin segala macam.
Kalau saya mengistilahkan pendidikan yang reguler sekarang itu seperti kita menyiapkan ayam broiler disterilkan. Kenyataan itu sangat terbatas lebih banyak mengandalkan buku teks, kemudian diukur dengan ukuran-ukuran yang tidak bermakna buat masyarakat, yang ukurannya nilai 10, nilai 100, memang kalau anak nilanya 100 nanti dia hidupnya bagaimana. Apa yang membedakan dengan yang tidak 100? Sebenarnya untuk berkontribusi tidak bisa dilihat dari situ. Jadi, kalau menurut saya, pendidikan yang reguler itu kayak menyiapkan ayam-ayam jadi ayam broiler karena ayam broiler memang kelihatan "wah" kalau dipamerkan. Kalau dilihat kan ijo royo-royo tapi sebenarnya sangat rentan, karena kalau ada makanan kotor sedikit terinfeksi, dan segala macam rentan dengan pengaruh-pengaruh negatif. Nah, seperti itu, padahal yang kita inginkan sebenarnya ayam kampung yang tahan banting, yang siap menghadapi dinamika ketika ada kesulitan. Ada tantangan mereka bisa mikir, mereka bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat yang dibutuhkan oleh yang berguna buat dirinya sendiri maupun buat lingkungan sekitar. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan pendidikan ala ayam broiler tadi, sudah ada pendidikan kritisnya.
Adi C. Kristiyanto : Alam proses pendidikan ala ayam boiler tadi ini tentunya kan juga kemudian akan timbul permasalahan-permasalahan. Jadi yang memang bisa hidup dengan cara ayam boiler, mereka tentunya akan tampil dengan nilai-nilai bagus ketika ditampilkan. Kalau mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan pendidikan semacam ini, akhirnya mereka bermasalah dengan pendidikan itu. Kemudian muncul anak putus sekolah, anak tidak sekolah yang selama ini kita menandainya dengan anak itu malas, nggak mau belajar, nggak masuk sekolah. Tentunya permasalahannya tidak seperti itu. Sebenarnya pendidikan yang seperti apa, yang memang diharapkan untuk tidak yang ditawarkan ayam broiler tadi?
Bukik Setiawan : Anak putus sekolah dan anak tidak sekolah adalah salah satu fenomena. Kita perlu menyalakan tanda bahaya bahwa pendidikan kita itu tidak relevan. Kalau melihat di angka partisipasi untuk sekolah dasar itu relatif sudah 100% kita sudah mencapai itu. Tetapi ketika masuk ke pendidikan menengah SMP maupun SMA itu tiba-tiba drop karena sebenarnya ada perlawanan yang tidak kasat mata, tidak dibunyikan, juga mungkin kurang bisa kurang disuarakan itu adalah yang relevansi pendidikan. Banyak pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang buat apa anak saya sampai harus SMA? Sudah, cukup saja membantu orang tuanya di kebun. Dia cerita, tetangganya lulusan SMA, si anak juga pendapatannya sama. Ada perlawanan-perlawanan seperti itu yang seringkali kita salahkan adalah orang tuanya. Orang tuanya kurang kesadaran tentang menyekolahkan anak-anak. Sistem pendidikannya memang tidak menjawab perusahaan dan kebutuhan masyarakat itu jadi kalau kita ingin menyelesaikan angka putus sekolah selain dukungan beasiswa dan segala macamnya, untuk sebagian masyarakat penting itu adalah menggerakkan pendidikan agar menjadi lebih relevan buat masyarakat. Atau misalnya bicara urban, bukan hanya masyarakat kelas menengah ke atas tapi semua lapisan masyarakat. Saya barusan dari Pasar Gede dan ada anak muda yang baru lulus kuliah tapi dia langsung action punya banyak upaya, berkebun, bikin es, bikin macam-macam, jadi langsung tahu dunia seperti apa. Jadi ketika membuat pendidikan, yang ketika lulus itu anak-anak sudah tahu bahwa dia bisa berkontribusi apa buat masyarakatnya.
Ada dua sisi internal, juga paham lingkungan eksternal, peluangnya apa, tantangannya apa, sistem dukungan yang ada di masyarakat apa yang bisa dipakai, dengan sistem seperti apa. Sehingga ada jawaban terhadap keresahan kita terhadap angka putus sekolah terutama angka tidak sekolah yang di pendidikan dasar. Memang harus pakai beasiswa, tapi pendidikan menengah itu banyak orang tua yang sebenarnya masih memadai, tapi untuk apa sih, karena ya sama saja. Saya ketemu di Trenggalek, guru curhat yang bilang bahwa ada orangtua berkata anaknya mending ngarit. Saya ketemu orang tua di Kabupaten Batu, juga orang tuanya juga ada yang mempertimbangkan mending anak saya langsung belajar berkebun, ngurusi sayur yang potensial itu, atau harus menghabiskan waktu di sekolah yang itu tidak relevan dengan sayurnya.
Astuti : Dengan realitas dan ritme hidup masyarakat Surakarta, lantas apa yang bisa dilakukan terkait Pendidikan?
Bukik Setiawan : Kita punya kita punya Pasar Gede. Pertanyaannya seberapa banyak sih pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak Solo darinya? Berapa anak Sriwedari menerapkan pengetahuan dari Sriwedari itu? Padahal orang datang ke sini, orang luar kota datang ke Solo, ke Pasar Gede ambilnya keunggulan di situ artinya Pasar Gede itu menawarkan praktik-praktik baik, yang bisa menarik minat orang-orang dari berbagai daerah, tapi malah dijauhin oleh pendidikan kita. Kalau pendidikan kontekstual, malah justru menjadi sebagai salah satu sumber belajar. Kalau bisa Sanggar Anak Jati, anak-anak datang observasi ke Pasar Gede, melakukan wawancara dengan para pedagang dan mereka belajar banyak, bagaimana sayur itu didatangkan dari daerah. Jam berapa datangnya ke Pasar Gede. Terus bagaimana mengolahnya. Bagaimana menyimpannya dan bagaimana menawarkannya, bagaimana melayani pembeli, dan masih banyak sekali. Meskipun kita tradisional, dari sebuah restoran itu, misalnya, mereka bisa membedakan mana yang perlu dirawat mana yang tidak perlu dirawat. Nah, itu ilmu kehidupan yang sebenarnya penting buat dipelajari oleh anak-anak kita. Tapi ya karena belajar dari buku teks yang namanya pasar adalah definisi, mana sih tempat berkumpulnya orang melakukan transaksaksi di pasar. Padahal di pasar interaksi variasi banyak sebenarnya.
Tujuan pendidikan kan itu mendekatkan pada masyarakat. Jadi sekolah itu sebenarnya institusi yang relatif baru 300-400 tahunan lalu. Jadi, pendidikan pada masa sebelum sekolah itu ada namanya “ngenger” kalau di Jawa. Tapi sebelumnya itu ada dua “ngenger” : ke orang tuanya sendiri sama mereka dan sama orang lain atau yang dianggap lebih tinggi stratanya. Kalau anaknya petani ya ikut bapaknya bertani, melakukan observasi. Ada kemerdekaan buat para santri memilih pondok yang mana, milih belajar dari kyai siapa itu, ada kemerdekaan. Jadi harusnya sistem pendidikan kita itu bisa memfasilitasi yang lebih sistematis dan lebih banyak sumber belajar. Dibandingkan belajar hanya pada satu orang tua karena kalau satu orang tua ini, kelemahannya dulu anak petani akan selamanya jadi petani terus, anaknya nelayan akan jadi anak nelayan terus. Nasib seperti diwariskan.
Pada dasarnya jauh lebih fleksibel untuk menghadapi keterbatasan sumber daya. Kalau yang sekarang semuanya harus memenuhi standar dan standar itu misalnya ruangan belajarnya harus seperti apa, kayak menyiapkan kandang ayam broiler. Kalau ada angin sudah langsung masuk angin. Kalau kita bicara kesenjangan sebenarnya lebih masuk akal pendidikan kontekstuallah untuk menjembatani perbedaan-perbedaan dan keragaman. Kalau soal nilai soal ujian sendiri ada satu titik itu memang penting nilai ujian. bahwa dalam pekerjaan kita juga mengenal namanya sertifikasi profesi, tapi perlu kita bedakan mana kebutuhan untuk ke pekerjaan. Ketika kita bicara profesi misalnya mau ujian pengacara, harus hafal, harus menguasai, harus bisa argumentasi, itu memang kekunci. Kemudian harus dibawa ke pendidikan di semua level. Jadi pada satu titik saya percaya bahwa perlu ada sertifikasi, perlu ada ukuran-ukuran yang kuantitatif, terukur, untuk masuk ke profesi, levelnya SMA ke atas. Sementara di kita itu dari SD pun sudah diminta untuk memenuhi standar kuantitatif itu. Padahal apa efeknya, kalau orang dewasa yang gagal sama anak yang SD yang gagal, itu psikologi ada proses kematangan dirinya untuk bisa belajar menerima kegagalan sebelum nanti dia 18 tahun. Tapi anak SD, anak TK itu Kan masih tumbuh bahwa dia gagal menjawab atau gagal untuk membuat suatu produk saja sudah itu orang gurunya udah setengah mati untuk membangkitkan semangat anaknya, apalagi harus gagal di ujian standar.
Berbeda peruntukannya jadi kapan digunakan untuk secara ketat di kehidupan orang dewasa itu bekerja dan kapan untuk tidak digunakan, yang lebih menggambarkan karakteristik anak tersebut, kelebihan dari anak tersebut. Jadi bukan menggambarkan pencapaian terhadap standar.Karena masih proses untuk menjadi dewasa, proses itu menjadi manusia utuh jadi tidak langsung. Itu menggambarkan, oh, di TK dia lebih suka untuk bergerak dibandingkan duduk diam. Ada anak yang lebih suka berbicara dibandingkan diam saja. Ini kekuatan anak tapi juga memfasilitasi anak itu untuk berani mencoba.
Eksperimen area belajarnya sampai benar-benar tidak bisa melukis ya karena experience-nya, tidak semata-mata karena penilaian pribadi. Sementara anak-anak kan masih masih berproses, berubah-ubah justru butuh ruang eksplorasi dan experience. Kalau umur 18 ada ujian standar saya setuju tapi kalau belum 18 saya tidak setuju.
Astuti : Karena kita juga tergantung kebijakan juga, lantas bagaimana?
Bukik Setiawan : Support yang pertama, basis pertamanya adalah pendidiknya. Pendidikan pada anak itu sistem support kebijakan yang model apapun sebenarnya masih bisa disiasati oleh pendidik tersebut. Di era dulu masih ujian nasional, teman-teman yang bergerak di pendidikan kontekstual juga tetap tidak lepas harus menyiapkan anaknya dan bersepakat bahwa anaknya itu perlu tumbuh kembang sebagai anak bukan sebagai manusia dewasa. Mereka membantu anaknya untuk menyikapi Ujian Nasional secara sesuai kebutuhan. Mereka ada yang menjadikan itu lebih sebagai otentiknya mereka. Ada yang mengalokasikan waktu belajarnya, jadi kelas 1 sampai kelas 5 sampai semester awal kelas 6 itu proses belajarnya kontekstual. Kemudian di semester terakhir persiapan untuk ujian nasional dan anak-anak tetap terbantu untuk menjadi diri sendiri di tengah situasi yang tidak di tengah kebijakan yang tidak ideal tersebut. Jadi, masih bisa di kata kunci yang tadi di pendidiknya. Meskipun kalau kebijakannya lebih progresif, lebih mendekat belajar, itu akan sangat membantu pendidik itu untuk pendidikan anak-anaknya.
Astuti : Guru Belajar Foundation, bagaimana ini Pak Bukik awalnya turut mendirikan yayasan ini?
Bukik Setiawan : Latar belakang saya di isu pendidikan. Terus, setelah jadi dosen waktu itu ada sejumlah inisiatif untuk membantu orang tua, jadi pendidik yang lebih baik lewat Indonesia Bercerita. Tapi mencari modelnya gimana sih melakukan perubahannya itu secara ekosistem, bahkan lebih luas dari perubahan kebijakan kita. Perspektif ekosistem kita itu perlu berubah, sistemnya juga perlu diubah. Tapi kesadaran para pelakunya itu juga perlu berubah. Karena kalaupun ini sederhana sudah ada berapa tahun yang lalu dan sudah ada edaran dari menteri untuk tidak ada ranking kelas. Nah, karena perubahan ekosistem kita butuh banyak pemimpin, agar bisa menggerakkan ekosistem, menggerakkan kesadaran warga masyarakatnya maupun menggerakkan perubahan di level kebijakannya.
Di titik itu kami melihat guru punya potensi kepemimpinan yang besar. Guru itu seringkali memang dilemahkan. Beberapa orang kemudian masuk ke sistem dilemahkan. Kalau kita bicara seperti kelompok sipil yang lain, sejak 65 itu memang ada kanalisasi terhadap kelompok-kelompok sipil termasuk pekerja ada SPSI, petani juga ada. Sejumlah profesi sipil itu mengalami penguatan, guru tidak, jadi kayak di wartawan di era Orde Baru yang diaku cuma PWI. Banyak organisasi yang menggambarkan dinamika masyarakat kelompok sipil. Ada penguatan-penguatan proses yang membuat negara tidak semudah itu mengontrol kelompok sipil tersebut.
Kenapa konsisten? kalau saya salah satunya adalah undang-undang guru. Saya baca naskah akademiknya itu menempatkan guru kesannya sangat kuat untuk mendapatkan guru sebagai objek yang harus dikasihani negara. Kenapa sekarang sudah berkontribusi besar pada bangsa, sudah jadi pahlawan tanpa tanda jasa, yang kasihlah sekarang jasanya,sehingga kalau ini di luar urusan administratif birokrasi,ada pertarungan juga tapi narasi besarnya adalah meskipun mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi yang satu kali gaji pokok itu, posisi politiknya tetap rendah. Sebagai objek semakin kuat.
Praktik itu juga banyak manipulasinya. Semisal sudah dapat tunjangan sertifikasi terus ada menu-menu yang meminta, minta perjalanan sebenarnya panjang dari pusat ke daerah. Kemarin di short cut masuk langsung ke guru untuk menghindari praktik itu. Narasi besarnya masih tetap tidak berubah, guru dibutuhkan sebagai objek.Nah terus apa yang dilakukan oleh kami di Guru Belajar Foundation? Kami pelajari, membangun kesadaran pada guru, bahwa kunci dari profesi guru itu bukan pada jabatan, jadi membedakan antara profesi sama pekerjaan.
Sebagai profesi itu kuncinya ada dua kompetensi sama kapasitasnya. Dari penggunaan kapasitas tersebut, untuk bisa menguasai kunci itu ya belajar. Tugas utama guru itu bukan mengajar. Tugas utamanya itu belajar. Dia belajar dan sebagai pekerjaan pun belajar, karena guru yang belajar itu antusiasme belajarnya akan menular ke anak-anak. Pertanyaannya, kalau ada topik-topik bicara soal kata guru-guru yang belajar itu, misalnya, pingin tahu beneran sebenarnya katak itu bisa melompat berapa meter? Kalau yang guru LKS cuma belajar, katak itu apa definisinya adalah binatang yang hidup di dua alam. Itu saja.
Nah,sebagai profesi guru dia juga akan mendapatkan pengakuan secara alamiah. Sejak kapan ini ? Kalau resminya itu baru 2016 tapi sebelum 2016 itu memang kami bergerak sebagai divisi pelatihan di sekolah Cikal. Jadi dulu itu tugasnya cuma melatih guru-guru internasional di seluruh Indonesia. Kalau yang sekarang ya kalau ada di 150 daerah. Daerah dengan kapasitas yang berbeda-beda. Yang sudah relatif solid itu ada di 145 daerah. Tiap tahun kami mengadakan Temu Pendidikan Nusantara dan itu bukan kerjaan struktural. Jadi kegiatan daerah mana yang mengadakan itu tidak ditentukan oleh pusat. Kegiatan itu membangun relasi dengan para pihak, dengan pemangku kepentingan dan pemerintah dengan mereka sendiri yang melakukan batas inisiatif sendiri. Jadi juga sudah tidak bergantung kepada pusat. Seringkali yang mandiri ini dapat yang lebih banyak daripada yang bisa kami berikan kepada daerah. Bagi mereka, ini memang salah satu petualangan belajar untuk menjadi pemimpin daerah.
Kegiatan-kegiatan yang ada leveling kegiatan ini, mereka mengurusi program di daerahnya masing-masing, kebijakan daerah masing-masing.
Hari belajar sekolah itu yang menentukan regulasinya dari sekolah. Mau 5 hari, 6 hari, mau libur kapan, itu kewenangannya kepala daerah, bukan kewenangan pusat. Artinya, kalau Solo, balik ke Solo, misalnya punya tiga even besar yang perlu dipelajari oleh anak-anak, bisa menjadikan even-even besar itu sebagai hari belajar khusus. Jadi tidak ada kegiatan di sekolah tapi menjadikan tiga even itu sebagai sumber belajar. Apakah itu observasi, apakah itu wawancara, apakah itu tampil di situ. Kalau kita ngomong di daerah nelayan, yang bisa jadi ketika musim angin darat malah justru mereka ini, ketika bapaknya atau orang tuanya melaut di sini malah libur. Kemudian didekatkan ke sana, tapi banyak daerah yang tidak paham bahwa itu adalah kewenangannya.
Jawa Tengah dan Jakarta itu hari sekolahnya berbeda dari masuk sekolahnya, Jakarta sama Tangsel yang sebelahan itu hari masa sekolahnya beda. Daerah selama ini belum sadar bahwa pendidikan dan pengelolaan pendidikan itu adalah kewenangan mereka mulai pengelolaan gurunya sampai pengelolaan satuan pendidikan.
Jadi mereka yang ada Dinas Pendidikan Kota. Tidak hanya menunggu instruksi atau apapun kebijakan dari pusat turun ke bawah. Sektor pendidikan itu sebenarnya strategi kunci untuk Kepala Daerah mencapai tujuan pendidikan, tujuan pembangunan daerah.
Justru harusnya kalau sebagai kepala daerah, pendidikan adalah pilihan strategi kunci bagi kepala daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah artinya kalau daerah itu punya program prioritas, punya tujuan prioritas yang perlu dicapai, kalau melibatkan pendidikan, daya ungkit akan jauh lebih besar dengan catatan: pendidikannya adalah pendidikan kontekstual bukan pendidikan akademis.
Contoh dari Bupati Sleman : Dua yang menarik buat saya satu Revitalisasi Pasar Tradisional dan satunya Sleman Tuntas Sampah.
Pasar seringkali hanya dilihat sekadar pembangunan fisik dan kebiasaan orang. Bisa saja kita membangun fisiknya tapi tidak ada yang datang. Terus akhirnya pedagang itu ada di luar area pasar. Kalau di dalam, tidak ada yang nyari. Itu problem perilaku. Nah ketika kita mendefinisikan revitalisasi pasar tradisional dari problem pembangunan fisik, menjadi problem perilaku itu peran pendidikan kontekstual jadi penting.
Kalau ada puluhan ribu murid melakukan riset, kunjungan ke pasar-pasar yang barusan direvitalisasi, mereka wawancara, melakukan observasi ada interaksi.Mereka ke pasar, mereka bertanya lagi dan menjelaskan rancang sistem parkir di pasar tradisional atau yang canggih. Ini membuka ruang-ruang percakapan tentang program prioritas kepala daerah. Belum lagi kalau ide-ide itu terealisasi meskipun kecil kemungkinannya ya karena itu sekolah. Tapi membuka ruang percakapan itu akan menjadikan program prioritas kepala daerah tidak hanya sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah saja tetapi menjadi bagian percakapan dari masyarakatnya. Kepala daerah tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi, harusnya beda, kalau dia harus membuka kembali, tinggal training penggunaan anggaran.
Adi C. Kristiyanto: Semakin menarik. Jadi memang pendidikan kontekstual itu sangat memberikan keuntungan, baik bagi pemerintah daerah juga kepada masyarakat di daerah tersebut. Dan juga muridnya yang paling utama. Kira-kira siapa ini yang perlu dilibatkan yaagar pendidikan ini benar-benar menjadi satu solusi bagi masyarakat, terutama masyarakat urban dan itu Kota Surakarta?
Bukik Setiawan : Kalau kita kelompok sipil dan kelompok menengah serta kelompok profesi sadar pentingnya pendidikan kontekstual dan berkontribusi untuk mewujudkan pendidikan. Itu sebenarnya bagaimana sih agar anak-anak nantinya kalau memang berminat jadi pengacara itu lebih siap untuk masuk ke jalur hukum. Kelompok itu yang bisa menjadi sumber belajar buat anak-anak. Kalau anak-anak belajar nanti mau menekuni profesi arsitek, itu juga sudah relatif lebih siap. Atau Solo sebagai kota kuliner, juga seperti teman pengusaha kuliner atau atau mungkin bukan pengusaha kulinernya, misal Chef juga. Ada juga yang konsepnya, bagaimana mereka bisa jadi sumber belajar. Nah, kelompok sipil ini, yang perlu perlu berkontribusi bukan semata-mata, mereka harus memberikan kehidupan bangsa. Bukan hanya semata-mata, secara norma, tapi secara bermaknanya adalah setiap kelompok profesi punya tanggung jawab untuk menjaga profesinya.
Dan untuk menjaga profesinya adalah memastikan pendidikan yang tidak sesuai. Saya mengundang rekan-rekan dari berbagai kelompok profesi untuk menyuarakan lebih keras tentang pentingnya pendidikan kontekstual dari perspektif masing-masing. Tidak apa-apa, kita akan ketemu, kita akan berinteraksi, kita akan berdebat dan berdialog di ruang-ruang publik untuk bagaimana mengembangkan pendidikan kontekstual yang sesuai dengan kota Solo. Atau sesuai dengan daerah masing-masing karena setiap daerah pasti punya kelompok profesi dominan yang beda. Kalau di Solo kan kelompok proyeksi petani cuma satu dua tapi saya undang teman-teman kelompok profesi dari berbagai profesi untuk terlibat, untuk menjadi bagian mewujudkan pendidikan kontekstual agar anak-anak kita, anak-anak Solo mendapatkan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. (Ast)