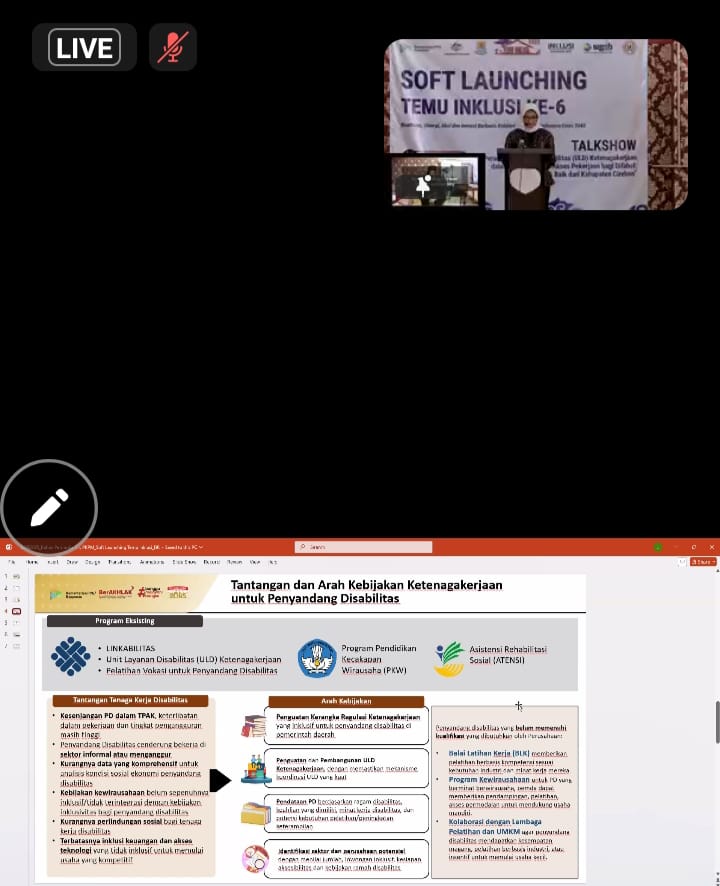oleh : Hisyam Ikhtiar Mulia*
Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) kerap dianggap sebagai pesta demokrasi yang digelar tiap 5 tahun sekali di Indonesia untuk menentukan para pemimpin Negeri selama 5 tahun berikutnya. Namun, apakah demokrasi hanya sebatas pesta pemilihan eksekutif dan legislatif semata? Ini bisa menjadi kekeliruan berpikir kita selama ini. Sejarah mencatat bahwa ide demokrasi, yang disebut sebagai demokrasi radikal bahkan telah muncul sejak zaman Yunani kuno, tepatnya di Negara-Kota Athena (tahun 479-431 sebelum masehi). Namun demikian, demokrasi modern yang kita kenal pada saat ini boleh jadi bersumber pada berhasilnya rakyat Eropa meruntuhkan monarki (sistem kerajaan/feodal) yang ditandai revolusi Prancis pada 1789.
Revolusi Prancis menjadi tonggak munculnya gagasan tentang hak asasi manusia di mana rakyat memilih untuk menentukan nasib bangsa. Meski belum sempurna, demokrasi terus berevolusi, hingga setelah Perang Dunia II (PD II), lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Tentunya, prinsip negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat tercermin oleh bunyi Pasal 21 DUHAM. Selain itu, pasal-pasal lain juga sangat mencerminkan hak kebebasan individu dan perlindungan terhadapnya. Contohnya, Pasal 20 menjamin kebebasan berorganisasi dan berserikat berdasarkan kehendaknya.
Jaminan atas kebebasan dan hak-hak individu juga Kembali dikukuhkan oleh Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kovenan ini bahkan mempertegas soal martabat (dignity) dan kesetaraan hak yang tidak dapat diganggu gugat pada bagian pembukaan. ICCPR Kembali menegaskan hak memiliki opini dan berserikat, tepatnya pada pasal 19 dan 21. Kedua pasal ini memperkuat dalil penjaminan hak beropini dan berorganisasi yang tertera pada DUHAM. Baik DUHAM maupun ICCPR menggunakan diksi ‘setiap orang’ tanpa terkecuali harus dijamin hak-haknya. Kedua dokumen tersebut juga menggunakan diksi “tidak ada seorangpun” yang boleh direnggut hak-haknya.
Memang baik DUHAM dan ICCPR tidak menyinggung secara eksplisit tentang disabilitas/difabel, tetapi bukan berarti seorang difabel tereksklusi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Jauh setelah DUHAM dan ICCPR disahkan, PBB mengeluarkan Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Disabilitas (CRPD) pada 2006, yang memiliki penegasan terhadap hak partisipasi politik dan kehidupan bermasyarakat bagi orang dengan disabilitas, tepatnya pada Pasal 29.
Secara garis besar, pasal ini memandatkan dua hal, yaitu 1) Negara harus menjamin partisipasi penuh dan efektif orang dengan disabilitas untuk terlibat dalam kehidupan politik dan urusan publik sebagaimana orang lain; dan 2) Negara harus aktif mempromosikan lingkungan di mana orang dengan disabilitas dapat berpartisipasi dalam ruang publik tanpa diskriminasi sebagaimana orang lain.
Sejatinya, pasal 29 CRPD adalah Upaya mengembalikan akses ruang publik dan diskrusus politik untuk semua individu, termasuk disabilitas/difabel. Dalam pasal tersebut, jaminan pastisipasi penuh dan efektif orang dengan disabilitas dalam proses politik dan akses ruang publik dapat berbentuk a) memastikan prosedur, sarana-prasarana, serta materi pemilu dapat diakses dan dimengerti dengan mudah; b) menjamin hak atas kerahasiaan dalam memilih tanpa adanya intimidasi, serta hak untuk menjadi pejabat publik dan menjalankan tugasnya serta menyediakan alat bantu untuk menjalankan tugas tersebut bila perlu; dan c) menjamin kebebasan orang dengan disabilitas dalam mengekspresikan keinginan (pilihan politik) serta memperbolehkan mereka dibantu dalam proses pemilihan oleh orang yang mereka pilih sendiri, jika mereka menginginkannya.
Selain partisipasi politik pasal yang sama juga memandatkan negara mempromosikan adanya partisipasi penuh dalam ruang publik. Mandat ini termasuk mendorong para difabel menjadi bagian organisasi non-pemerintah atau asosiasi yang menaruh perhatian pada urusan publik dan politik negara, dan bahkan terlibat dalam aktivitas dan urusan administrasi partai politik. Selain itu, negara juga harus mendorong orang dengan disabilitas/difabel membuat atau bergabung dalam organisasi orang dengan disabilitas untuk merepresentasikan difabel di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.
Menurut penulis, pasal 29 ini memandatkan perubahan pada diskrusus politik dan akses ruang publik negara. Tentunya, perubahan tidak dilakukan dengan maksud mengistimewakan disabilitas/difabel, tetapi demi tercapainya kesetaraan akses, baik dalam menggunakan ruang publik, maupun dalam proses politik. Namun, bagaimanakah sejatinya konsep partisipasi penuh dan efektif dalam politik dan urusan publik, terutama dalam konteks Indonesia? Tulisan ini akan mencoba mengajukan sebuah ide tentang partisipasi politik bagi disabilitas/difabel
Demokrasi Untuk Semua Individu Tanpa Terkecuali
Prinsip demokrasi mengembalikan kuasa tertinggi ke tangan rakyat. Tentunya, konsep-konsep seperti martabat individu, kebebasan, dan kesetaraan hak, bersumber dari pemikiran bahwa setiap individu memiliki hak yang bersifat inheren atau melekat pada dirinya. Dalam teorinya, Locke membahas tentang kontrak sosial yang nantinya berkembang menjadi negara, dihasilkan dari orang-orang yang memiliki hak secara inheren.
Kebebasan Individu dan kepemilikan hak yang inheren tentu saja menjadi pondasi penting berdirinya demokrasi. Pada dasarnya, sekelompok orang di suatu tempat yang sama, yang masing-masing memiliki hak, akan memikirkan cara untuk mengatur bagaimana agar hak mereka tidak berbenturan satu sama lain Ketika beraktivitas. Ide pengaturan tersebut kemudian mendasari apa yang kita ketahui sebagai negara hari ini. Oleh sebab itu, konsep negara harus dipahami sebagai organisasi di mana rakyat, yang masing-masing memiliki hak, memberikan sekelompok orang di antara mereka ‘kekuasaan lebih’ untuk mengatur supaya setiap orang tidak berbenturan Ketika melakukan aktivitas menikmati haknya.
Sejak era John Locke di abad ke-17 konsep demokrasi dan penjaminan hak hari ini memang telah jauh berkembang. Bahkan saat ini terdapat beragam diversifikasi hak untuk kelompok-kelompok yang memiliki sejarah khusus perampasan hak-hak mereka. Kelompok disabilitas/difabel menjadi salah satu yang hak-haknya mulai diperhatikan sejak dekade pertama tahun 2000-an, meski sejatinya advokasi isu disabilitas sudah mulai disuarakan sejak 1970-an. Pengesahan CRPD menjadi tonggak diakuinya hak-hak orang dengan disabilitas. Bahkan, pengesahan CRPD pada 2006 sama bersejarahnya dengan Revolusi Perancis pada 1789, yang berbeda adalah simbol kemenangan terhadap ableisme ini tidak diraih dengan pertumpaham darah. Menurut penulis, jika revolusi perancis adalah simbol kemenangan melawan tirani monarki, maka pengesahan CRPD adalah simbol kemenangan melawan ableisme, yaitu pandangan atau cara berpikir yang diskriminatif terhadap disabilitas/difabel, seperti mengasosiasikan disabilitas dengan penyakit, atau ketidaksempurnaan.
CRPD memberi mandat perubahan sosial yang komprehensif, melalui perubahan paradigma, terutama dalam memandang isu disabilitas. Perubahan yang dimaksud berakar pada perubahan kerangka pikir dari medical model ke social model, serta menuntut adanya inklusi sosial yang komprehensif di mana orang dengan disabilitas/difabel mendapat derajat penikmatan hak yang setara dengan orang lain. Berbagai bentuk inklusi sosial tergambar dalam CRPD, termasuk dalam prinsip general Pasal 3 CRPD, yaitu partisipasi penuh dan efektif, serta inklusi sosial. Partisipasi penuh dan efektif dalam konteks demokrasi dapat diartikan bahwa kontestasi politik harus memungkinkan difabel menjadi kontestan maupun pendukung.
Dalam kaitannya dengan demokrasi, proses politik dan ruang-ruang publik harus memungkinkan disabilitas/difabel terlibat secara aktif, sebagaimana mandat Pasal 29 di atas. Proses politik di sini tentu tidak terbatas pada pemilihan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan legislative (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai “pesta demokrasi yang terlihat” pada perhelatan pemilu 5 tahun sekali. Bukan berarti pemilu 5 tahun sekali tidak penting, tetapi demokrasi harus dimaknai lebih dari itu.
Demokrasi harus dimaknai sebagai sebuah proses yang terjadi setiap hari. Maksudnya, kendati kita telah memilih Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Demokrasi tidak mati suri. Proses demokrasi harus terus berlangsung, salah satunya pada saat perumusan kebijakan. Misalnya, dalam perumusan undang-undang, walau secara hukum normatif hanya perlu persetujuan Presiden dan DPR, bukan berarti masyarakat sipil tidak terlibat sama sekali. Misalnya, dalam perumusan Undan-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tentu terdapat keterlibatan organisasi masyarakat sipil, termasuk difabel.
Memang sudah seharusnya masyarakat sipil, termasuk difabel terlibat aktif dalam menjaga demokrasi tetap hidup, sebagai bentuk partisipasi politik dan akses terhadap ruang-ruang publik. Sudah sepatutnya difabel berperan aktif memberi kritik terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, maupun bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Di samping itu, negara harus menjamin adanya perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan berpendapat terhadap siapapun yang bersuara, termasuk difabel. Tentu saja, Indonesia punya praktik baik dalam keterlibatan difabel dalam proses demokrasi. Tetapi, masih juga terdapat catatan-catatan penting pada kondisi saat ini, demi tergapainya proses demokrasi yang inklusif terhadap difabel.
Demokrasi Indonesia dan Difabel
Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) menjadi momentum demokrasi di Indonesia dengan diakuinya hak-hak politik difabel. Hak-hak politik yang dimaksud terdapat dalam Pasal 13 UU Disabilitas dengan 8 poin (a-h). Sejatinya, sudah banyak yang membahas tentang hak-hak politik difabel, terutama dalam kaitannya terhadap hak-hak difabel sebagai pemilih dalam pemilu. Tanpa mengesampingkan pentingnya menjamin hak-hak difabel dalam partisipasi pemilu, tulisan ini mencoba mengulas sisi lain dari keterlibatan difabel dalam demokrasi.
Penulis percaya bahwa makna demokrasi untuk difabel lebih dari sekadar menjadi pemilih dalam pemilu. Ada begitu banyak ruang dalam demokrasi yang perlu diisi oleh individu difabel di seluruh Indonesia, salah satunya adalah peran aktif dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat berbagai organisasi maupun individu difabel yang terlibat dalam perumusan kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, Hingga pembentukan Kelompok Kerja Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Mental (POKJA P5HAM). Tentunya, terdapat juga upaya advokasi kebijakan oleh organisasi difabel di tingkat daerah.
Selain keterlibatan sebagai masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan, terdapat juga praktik baik advokasi internasional. Misalnya, Perhimpunan Jiwa Sehat bersama LBH Masyarakat, HRWG, dan rekan-rekan lainnya, mengirimkan laporan alternatif implementasi CRPD di Indonesia yang spesifik membahas isu disabilitas psikososial. Laporan serupa juga dibuat oleh beberapa organisasi difabel yang membahas isu disabilitas secara umum. Terdapat juga berbagai advokasi internasional yang dilakukan oleh Agus Hidayat, seorang disabilitas psikososial/mental yang telah banyak berkiprah dalam advokasi disabilitas di dalam dan luar negeri.
Contoh-contoh baik (best practices) keterlibatan aktif difabel dalam demokrasi mengindikasikan difabel sangat mungkin mengisi ruang-ruang demokrasi. Partisipasi difabel terbukti tidak hanya sekadar menjadi pemilih 5 tahunan, tetapi dapat berperan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Sejauh ini, organisasi difabel seperti SIGAB, SAPDA, PPDI, HWDI, PERDIK, dan kawan-kawan turut berkontribusi menyumbang ide dan pemikiran dalam menentukan substansi peraturan perundang-undangan terkait disabilitas di tingkat nasional maupun daerah. Namun, apakah kondisi saat ini adalah versi terbaik keterlibatan difabel dalam demokrasi? Penulis berpendapat masih ada ruang-ruang lain yang dapat diisi oleh difabel di masa depan, salah satunya adalah peran sebagai pejabat yang berwenang menentukan arah kebijakan.
Tidak dapar dipungkiri bahwa saat ini penentuan kebijakan, terlebih peraturan di bawah undang-undang, masih berada dalam genggaman pejabat-pejabat eksekutif. Tentu bukan berarti setiap kebijakan secara sewenang-wenang ditetapkan oleh pemerintah tanpa mendengar suara rakyat. Tetapi Inisiasi pembentukan dan keputusan akhir pengesahan produk kebijakan hampir selalu bergantung pada pemangku kepentingan dalam tubuh eksekutif (pemerintah). Akan sangat berbahaya jika pemangku kepentingan enggan atau tidak sensitif terhadap isu difabel, seperti kejadian Menteri Sosial yang memaksa seorang kawan Tuli untuk berbicara pada seremoni hari disabilitas internasional. Bayangkan bila seseorang yang bahkan tidak memahami perilakunya mempertontonkan ableisme menjadi orang yang menentukan kebijakan terkait difabel, tentu berpotensi memporakporandakan substansi dari aturan yang dibuatnya.
Urgensi bagi difabel untuk meraih posisi penentu kebijakan publik bukan tanpa alasan. Saat ini telah terdapat beberapa figur difabel seperti Sunarman Sukamto (Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden), Jonna Aman Damanik (Anggota Komisi Nasional Disabilitas), Angkie Yudistia (Staf Khusus Presiden Republik Indonesia] sebagai disabilitas yang memiliki posisi cukup strategis dalam pemerintahan. Meski cukup berpengaruh, nama-nama tersebut tetap bukan orang-orang yang menjadi pihak yang berwenang dalam penentuan kebijakan. Absennya representasi difabel sebagai penentu kebijakan dapat berakibat fatal, terutama dalam substansi kebijakan yang akan penulis ulas dalam catatan kritis berikut.
Catatan Kritis Partisipasi Difabel Dalam Demokrasi
Sejak meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang patuh terhadap mandat CRPD, tetapi masih belum cukup. Penelitian dari Agus Hasan Hidayat dan Hisyam Ikhtiar menemukan beragam substansi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap disabilitas psikososial dan masih bertahan hingga hari ini. Salah satu temuannya adalah masih dipertahankannya ketentuan pengampuan pada Pasal 433-460 KUH Perdata yang membuat seseorang dinyatakan tidak cakap hukum dan praktiknya merugikan bagi orang dengan disabilitas psikososial. Mengingat pasal ini adalah produk hukum kolonial, tentu bukan sepenuhnya kesalahan pembuat kebijakan saat ini. Tetapi, sangat disayangkan bahwa pasal pengampuan direplikasi oleh ketentuan yang dibuat setelah ratifikasi CRPD. Bahkan, pada UU Disabilitas Pasal 32 menyatakan penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap hukum.
Keberadaan Pasal 32 UU Disabilitas sebagai ‘perpanajangan tangan’ dari ketentuan pengampuan. Tidak cukup sampai di situ, dalam persidangan uji materiil Pasal 433 KUH Perdata di Mahkamah Konstitusi, pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak DPR seolah sepakat menentang pendapat pihak yang mengajukan gugatan. Baik pemerintah maupun DPR menyatakan pendapat yang senada, yaitu bahwa tidak ada masalah dalam ketentuan pengampuan, karena sudah terdapat proses hukum yang harus dilalui seseorang yang hendak mengampu orang lain. Kenyataan ini mengindikasikan masih belum tercapainya perubahan paradigma komprehensif tentang isu disabilitas, bahkan pada institusi yang berwenang menentukan kebijakan.
Contoh di atas hanyalah satu dari sekian fenomena yang menunjukkan betapa pentingnya pemahaman tentang isu disabilitas bagi penentu kebijakan. Penulis tidak bermaksud mengatakan bahwa non-difabel tidak mungkin memiliki perspektif yang memadai tentang isu disabilitas. Namun, tentu saja sosok terbaik untuk memahami isu disabilitas adalah orang difabel itu sendiri. Ini juga sesuai dengan semboyan “nothing about us without us”. Sampai saat ini sudah banyak bukti tentang kapabilitas difabel dalam merumuskan kebijakan, termasuk yang penulis paparkan di atas. Oleh sebab itu, daripada hanya terus menerus berharap pihak penentu kebijakan memiliki perspektif yang tepat tentang disabilitas, akan sangat jauh lebih baik bila individu-individu difabel mulai membuat strategi untuk dapat duduk di kursi para penentu kebijakan di masa depan.
Penutup
Sangat penting bagi difabel untuk mulai mengambil peran sebagai penentu kebijakan. Tentu saja, jalan menuju cita-cita itu masihlah sangat panjang. Tetapi, cita-cita tersebut tentu bukan hanya mimpi di siang bolong. Dari contoh-contoh figur yang telah disebutkan di atas, tentu sangat memungkinkan bagi difabel untuk memiliki kapabilitas sebagai penentu kebijakan. Kita sebagai difabel tentu punya banyak tugas rumah, salah satunya adalah mengintegrasikan isu disabilitas dengan isu-isu lain seperti isu lingkungan, isu pemerintahan, isu bisnis dan ekonomi, serta isu-isu lainnya.
Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel - SIGAB Indonesia
NLR Indonesia
PPDI Situbondo
Temu Inklusi
#temuinklusi2023 #situbondoinklusi #IndonesiaInklusi #HinggaKitaBebasDariKusta #anakmudabicarainklusi
*naskah ini keseluruhan diambil dari akun Facebook Hisyam Ikhtiar Mulia