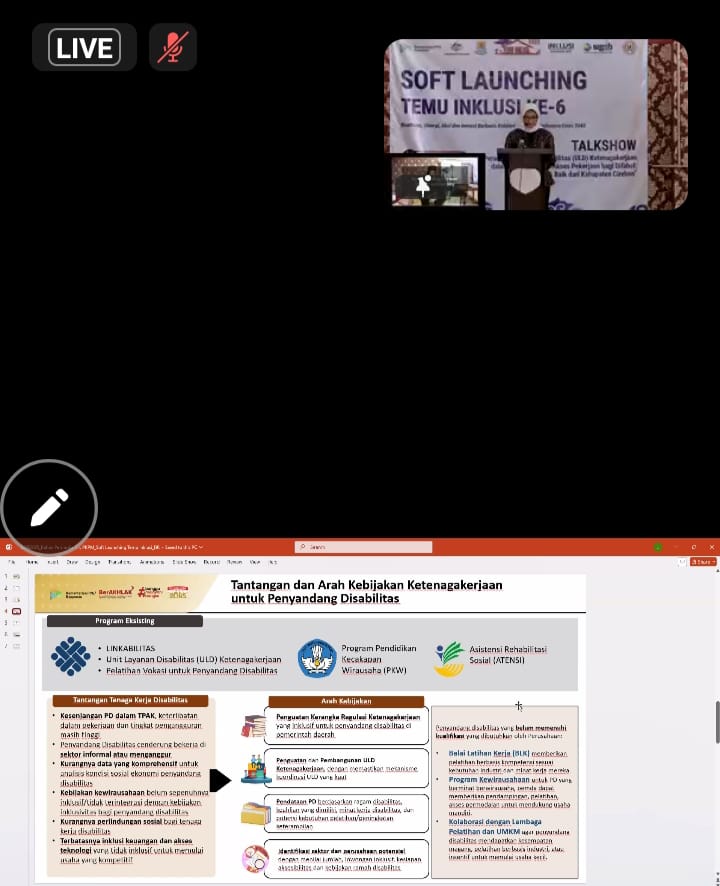Sesuatu yang sangat penting, mungkin untuk sebagian orang, ketika berbicara tentang ibadah saat pandemi COVID-19 adalah adanya bahasa isyarat dengan adanya box kecil di layar. Tapi sebenarnya setiap orang Kristen bisa beribadah, artinya umat dengan disabilitas bukan kali ini saja tetapi sejak zaman dulu sudah terbentuk, dengan mengundang setiap orang dengan disabilitasnya. Saat ini berkembang isu tentang intergeneration worship. “Malam ini kita ngomongin sesuatu yang pernah didengar dan dilihat tetapi belum diobrolkan secara serius,” ungkap Isabella Novsima dalam siaran IG Live akun @teologi_disabilitas bersama Cindy Ginting.
Kenapa penting bicara tentang liturgi dan disabilitas? menurut Cindy, pertama kali ia tertarik berbicara tentang ibadah dan disabilitas, saat kolegium pastoral dan Perjamuan Kudus, ada jemaat disabilitas intelektual yang hadir tetapi langsung dilewatkan. Ia berpikir mungkin karena ada aturan katekisasi, tetapi itu mengganggunya. Ia lantas berpikir kenapa ada aturan yang secara langsung meng-eksklusi teman disabilitas intelektual kemudian membuatnya berpikir, bagaimana melibatkan orang dengan disabilitas intelektual dan disabilitas yang lain yang belum memiliki akses. Saat itu Cindy sedang praktik sebagai mahasiswa teologi.
Ia merasa terganggu lantas berpikir bagaimana dengan keluarga dari orang yang mengalami disabilitas da dari orang yang alami disabilitas itu sendiri? Bagaimana dengan jemaat yang lahir dan dibesarkan di situ tidak punya aspek belong. Bagaimana mereka menjadi anggota komunitas jika kemudian menjadi the other bagi yang lain? Pertanyaan soal belong, bahwa ketika beribadah mereka menjadi anggota dari komunitas itu. Lalu timbul pertanyaan, “kalau seandainya kita jadi aneh bagi yang lain, penting ngga sih ketika beribadah bagian dari komunitas? Bagi yang the other supaya dia ga sendirian?”
Mengutip sebuah tesis, ibadah itu menciptakan sekaligus yang melahirkan komunitas. Cara sederhananya, ketika beribadah yang secara umum berdiri dan duduk, dengan metode : mendengar, membaca, berbicara dan bernyanyi, otomatis hanya ini yang dilakukan : menutup mata, membaca dan mendengar, otomatis ada yang ter-eksklusi. Bagaimana orang dengan disabilitas? Bagaimana dengan ibu yang alami penurunan fungsi tubuh misalnya, yang tidak relate. Maka penting membuat ibadah jadi sangat inklusif, karena ada yang ter-eksklusi. Ibadah adalah sebuah wadah yang memperlihatan dan menciptakan komunitas, bukan menghilangkan hambatan/tantangan tetapi mengingat kembali esensi dari ibadah, dan bagi orang yang seharusnya memiliki dan dimiliki.
Istilah menciptakan komunitas, komunitas bersifat statis, ibadah bersifat konstan kalau komunitas kesannya sudah ada. Semestinya ‘menciptakan’ itu terus-menerus dan ada evaluasi, misal ; oh cara kita berkomunitas tidak dengan meng-eksklusif, tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan. Lantas apa sih komunitas itu yang ingin diciptakan dalam ibadah? Apa yang mau ditiru, nilai utama, untuk mendefinisikan ‘menciptakan komunitas dalam ibadah’. Dari pengalaman Cindy pada Perjamuan Kudus, lakukan ini sebagai peringatan akan ‘aku’, anamnesis, bukan hanya mengingat secara kognitif tetapi menghadirkan kembali. Ketika menghadirkan kembali peristiwa itu bukan hanya secara keterlibatan kognisi, tetapi juga perasaan, sentuhan, tujuan yang mau dicapai.
Semua orang dalam ibadah mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan, bukan hanya untuk orang yang able, tetapi merangkul semua. Tujuan dari menciptakan ibadah yang ramah dan itu melampaui kemampuan intelektual jadi disabilitas intelektual mengalami kehadiran Yesus.
Kebanyakan orang berpikiran inti ibadah adalah kotbah dan berkah. Membayangkan bagi teman disabilitas intelektual, kotbah bukan pengalaman inti, tetapi pengalaman disapa, diberi tatapan hangat, ketika duduk diterima itu juga pengalaman. Bukan hanya bagaimana menghapal ayat berapa sampai berapa, seberapa. “Pengalaman anamnesis itu melampui kognitif kita,”terang Cindy.
Menurut Host acara, Isabella Novsima, ada lagi pemahaman teologi yang menarik, namanya teori akomodasi, Tuhan itu memberikan akomodasi kepada ciptaan dengan cara inisiatif untuk terus berkomunikasi dengan cara yang mampu dipahami oleh ciptaan tersebut. Mungkin teman disabilitas dengan neuro divergen dan autis, cara Tuhan berkomunikasi dengan mereka berbeda. Mungkin Tuhan juga berkomunikasi dengan tanaman, hewan, bisa saja Tuhan berkomunikasi dalam diam, pelukan hangat, tatapan hangat, bukan hanya bepusat pada nyanyian-Nya yang harus sesuai dengan tema. “Kenapa itu dianggap lebih berbobot dari Tatapan yang menerima? Ini penting ketika komunitas diciptakan untuk semangat semua orang, Ibadah inklusif memberi ruang bagi setiap orang yang memiliki kemampuan berbeda,” terang Isabella.
Cindy menambahkan bahwa ibadah multisensori yang melibatkan setiap sensori manusia berupa sentuhan, menghirup aroma, menyentuh, jemaat semuanya melibatkan sensorinya. Di sini umat bukan penonton ibadah tetapi orang yang aktif beribadah, contoh : Perjamuan Kudus, hosti yang dipecahkan berbunyi, itu menolong beberapa teman disabilitas untuk mendengarkan tubuh yang terpecah.
Juga bisa melakukan kotbah yang tidak selalu dengan kata-kata tetapi dengan visual termasuk dekorasi di dalam gereja yang memicu sensori manusia. Jadi ibadah itu tentang rasa, perasaan, dari tulisan dari beberapa momen. Terkait ibadah multisensorik sebenarnya sebagian besar gereja sudah melakukannya, semua senter pada Perjamuan Kudus dan bunyi ‘krek’ roti akses untuk semua. Pengaturan AC, temperatur udara sama penting, bukan hanya tentang akomodasi tetapi untuk teman disabilitas yang memiliki sensorik, ditunjukkan dengan kenyamanan melalui tubuhnya. Ada disabilitas yang tidak verbal, bukan berarti dia tidak cukup mengerti, tetapi tidak bisa menyuarakan.
Lalu bagaimana dengan perasaan yang dimaksud?
Perasaan yang dibangun dalam ibadah, Sense of belonging, adalah tidak ada yang merasa diasingkan, perasaan dilibatkan sehingga tidak ada lagi yang diasingkan. Sensor lainnya adalah kehadiran Yesus sendiri, kadang ada yang mengalami Tuhan secara verbal, ada yang tidak, sehingga perlu dibangun, agar Tuhan bisa diakses bagi setiap orang, terlepas bagimana dia merasakan kehadiran Tuhan itu.
Ada lagi anggapan kalau perasaan di dalam ibadah itu soal merasa diterima apa adanya, Banyak sekali ibadah itu adalah ibadah yang sangat diatur sehingga perasaan umat harus diatur, “pada saat ini kamu harus bersuka cita padahal dia sedang patah hati.” padahal saat dia datang ke gereja dengan tema suka cita. Bukan berarti tema tidak penting. Banyak sekali orang yang memberi ibadah dalam perasaan campur- aduk, yang satu dengan perasaan suka cita, yang lain dengan hancur lebur, bagaimana semua bisa diterima tanpa penghakiman. “Supaya ketidakteraturan itu bisa masuk. Kalau tidak, jangan-jangan kesuksesan hanya untuk merancang ibadahnya saja,”ungkap Isabella.
Pengalaman Cindy saat menulis Perjamuan Kudus dan disabilitas intelektual, ia berkata mungkin katekisasi/sidi dihilangkan saja pada saat itu sebagai syarat Perjamuan Kudus. Hal itu terkait tata gereja, tetapi terkait Perjamuan Kudus, jika anggota sidi maka syarat sidi yang perlu dikritisi, misal kotbah katekisasi yang tidak akses, karena disabilitas intelektual tidak bisa mengikuti score IQ dengan yang lain.
Dari materi yang dipermudah, maka menolong mereka bisa Perjamuan Kudus, diakui sebagai anggota, melayani sebagai penatua, hingga bisa menikah. Aturan dan standar katekisasi, tidak membuat umat disabilitas bukan tidak mungkin, untuk jadi anggota pun juga sulit, maka pertama harus membuat materi khusus untuk disabilitas intelektual seperti yang terjadi di Gereja Ketapang, mereka punya Perjamuan Kudus sendiri, dipisah, satu hal menarik, mereka terbiasa mengenakan dress code dengan warna tertentu misal putih, yang membuat mereka menyadari mereka disayang Tuhan. (Ast)