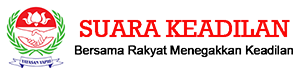Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menjadi salah satu dari 38 RUU usulan untuk masuk ke dalam Prolegnas 2021. Walaupun sempat beberapa kali dilakukan revisi, RUU Ketahanan Keluarga masih menuai kritik bukan saja dari beberapa anggota fraksi namun juga dari kalangan masyarakat sipil. Kritik inipun berdasarkan pada berbagai pertimbangan terutama terhadap hak-hak perempuan. Terlebih ketika saat ini banyak kelompok masyarakat yang sedang berjuang untuk mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, mengingat sebelumnya RUU ini dengan mudahnya dikeluarkan dari prolegnas. Beberapa pihak menyatakan mendukung keberadaan RUU Ketahanan Keluarga ini, namun tidak sedikit pula yang menolak.
Dilatarbelakangi oleh banyak hal itulah Yayasan YAPHI kemudian menyelenggarakan diskusi kritis via Zoom bertema “Menilik RUU Ketahanan Keluarga” yang diikuti oleh staf dan jaringan pada, Selasa (15/12) dan dimoderatori oleh Aniek Tri Maharni. Nunung Purwanti, pemantik diskusi saat mengawali pembicaraan mengungkapkan bahwa dasar pencetus adanya RUU ini hanya berbicara orang per orang. Padahal setiap individu dalam keluarga memiliki masing-masing kebutuhan, seperti dalam Undang-Undang PKDRT yang dipahami sebagai permasalahan individu, dan hanya mengatur tentang perempuan saja. Artinya definisi kekerasan yang ada dalam UU PKDRT dilihat dari sisi perempuan saja, dan bukan berbasis gender.
Dalam RUU Ketahanan Keluarga, sesuatu perbuatan yang menimbulkan kekerasan seksual disebut sebagai penyimpangan seksual dan harus dilakukan konsultasi. Menurut Nunung Purwanti bagaimana menyelesaikan hal ini jika mengatasnamakan keluarga? Siapakah yang ada di garda depan? Perempuan yang mendapatkan kekerasan di dalam rumahnya sendiri, keberadaannya dinafikan. Padahal semestinya relasi perempuan dalam keluarga kedudukannya setara. Perbuatan Kekerasan Seksual istilahnya diganti dengan penyimpangan seksual. Nunung juga menyoroti pasal-pasal yang menyebut tentang kewajiban anak, bukan hak. Dan semua hal di dalam keluarga diatur oleh negara. “Bisa-bisa negara ini jadi totaliter,” ungkapnya.
Haryati Panca Putri, Direktur YAPHI menyoroti bahwa dalam RUU ini perempuan diposisikan timpang dalam keluarga, apalagi jika terjadi kekerasan seksual dikatakan sebagai penyimpangan seksual. Ia menduga RUU Ketahanan Keluarga mengadopsi Perda yang sudah berlaku yakni Perda DIY nomor 7 tahun 2018 dan Perda Jawa Tengah nomor 2 tahun 2018. Menurutnya di dalam RUU ini juga menyebutkan terkait ketangguhan keluarga, lalu indikatornya seperti apa? Jika dikatakan harmonis, lalu harmoninya seperti apa? Karena di dalam keluarga misalnya terjadi istri dan suami terjadi kesenjangan pendidikan, apakah kemudian bisa dikatakan tidak harmonis? Kemudian muncul lagi istilah keluarga sejahtera yang dibentuk atas perkawinan yang sah. Ia juga menambahkan bagaimana jika ada kasus suami yang tidak memberi pelayanan kepada istri? Mengapa hanya perempuan saja yang dituntut lalu bagaimana suami yang mengambil peran gender, ini membuktikan jika rasa keadilan tidak ada oleh negara.
Lain lagi pernyataan dari Ines Ige Santika, salah seorang peserta diskusi, bahwa urgensi pembentukan RUU Ketahanan Keluarga dan Naskah Akademik (NA) dan RUU-nya tidak memuat tentang perlindungan perempuan dan anak. Ia membaca rumusan RUU ini seperti membaca pelajaran PPKN yang terus diulang, termasuk yang ia soroti seperti pelajaran pra nikah. Dan beberapa di antaranya yang ditulis di sini sudah ada di Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang BKKBN. “Saya pikir hal ini terkait bagaimana cara mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah, Oh ya satu catatan lagi bahwa yang diatur di ketentuan pidana hanya tiga, ”jelas Ines.
Hal senada juga dikatakan oleh Adi Kristiyanto, bahwa RUU Ketahanan Keluarga bisa jadi program pemerintah untuk dilakukan seperti PKH, RTLH, program pra nikah, karena sangat cocok dengan program itu. Menurutnya lagi, perlu ditinjau ulang apakah RUU ini menguntungkan atau malah merugikan masyarakat. Sependapat dengan Adi, Garindra Herayukana menyatakan apakah RUU ini menguntungkan atau merugikan, dan apakah peletakan posisi itu di masyarakat sudah benar? Karena hanya akan menghasilkan bentuk kekerasan struktur yang baru.
Indiera Hapsari, perwakilan dari jaringan masyarakat basis menyatakan bahwa menyimak RUU Ketahanan Keluarga dan membandingkan dengan UU Cipta Karya yang sudah tidak jelas peran perempuan dalam aksesnya ke ranah publik. Ia menambahkan pada pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga penekanannya lebih kepada norma-norma agama, atau memakai unsur norma agama untuk mengatur perempuan. Ia mengajak jika masyarakat menolak maka ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan turut mengkampanyekan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menolak Undang-Undang Cipta Karya dan RUU Ketahanan Keluarga dan menyerukan segera disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
Joshua dari Rumah Impian menyoroti Perda DIY nomor 7 tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ia tergelitik karena waktu pencanangannya tidak ada sosialisasi, sekali ada namun yang mengundang dari partai tertentu. Menurutnya, sebenarnya masalah kemiskinan lebih besar dari ketahanan keluarga dan di tingkat daerah saja lebih membingungkan daripada nasional. Lalu siapakah yang akan menjadi leading sector? Jika masalah keluarga miskin di Yogya saja untuk urusan menikah secara resmi masih menemui kendala. “Ini akan bertentangan dengan HAM,”ungkapnya.
Pada pasal 55 RUU Ketahanan Keluarga menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan memonitor data keluarga dan mengakses informasi apapun yang mereka perlukan. “Ini sangat mengerikan. Jelas sekali bahwa pasal tersebut riskan disalahgunakan dan mudah terjadi kebocoran data,” terang Christina Vera.
Yohanes Prima Cahya dari Yayasan YAPHI melihat di konsideran ada unsur-unsur liberalisme, bahwa keluarga itu untuk memproduksi tenaga kerja dengan rencana negara yang besar yakni globalisasi sebab keluarga bagian terkecil dari negara. Ia juga mengkritisi bahwa keluarga yang disebut dalam RUU ini adalah keluarga yang dianggap ‘normal’, lalu bagaimana jika ada anggota keluarga yang difabel? Bagaimana pula jika dalam keluarga tersebut kepala keluarganya adalah perempuan atau perempuan berstatus janda?
Selain hal-hal di atas, narasi kritis atas RUU Ketahanan Keluarga juga datang dari Hastowo Broto Laksono, salah seorang peserta. Menurutnya, setiap Undang-undang harus memuat asas materiil sesuai yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan. Dalam hal ini RUU Ketahanan Keluarga masih mengesampingkan asas keadilan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Ketika mendefinisikan kriteria tempat tinggal yang layak sedemikian rupa pada pasal 33 RUU Ketahanan Keluarga tentunya belum menunjukkan kedua asas tersebut.
Masih dijelaskan oleh Hastowo bahwa pada pasal 36 RUU Ketahanan Keluarga disebutkan pemerintah memfasilitasi tempat tinggal layak huni untuk keluarga. Pertanyaan besarnya apakah ketika nanti RUU ini berlaku dapat terlaksana dengan baik atau seperti regulasi yang lain, yang sebelumnya, yang hanya menjadi tulisan di atas kertas. Ia menambahkan berdasar pasal 96 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Per-Undang-Undangan disebutkan masyarakat berhak memberikan masukan secara tertulis dalam pembentukan perundang-undangan yang dapat dilakukan melalui ; a. rapat dengar pendapat umum, b. kunjungan, c. sosialisasi, d.seminar, lokakarya dan/diskusi. Maka menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan hal ini dalam menyusun RUU Ketahanan Keluarga. (Hastowo Broto Laksito/Astuti)