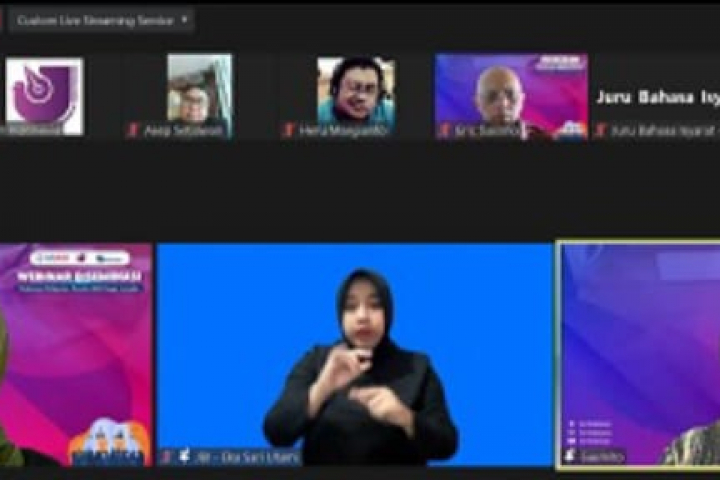Memaknai Kata Merdeka Bagi Difabel
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 288
Merdeka berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta ‘mahardika’ yang berarti kaya, sejahtera dan kuat. Dalam Bahasa Indonesia atau Melayu bermakna bebas dari segala belenggu (kekangan), aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu.
Mengoyak Akar "Pencacatan" Secara Sosial Menuju Inklusi Disabilitas
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 150
Apa yang tergambar dalam pikiran kita ketika diminta untuk membayangkan ‘orang normal’?
Sebagian besar kita pasti akan membayangkan sosok berjenis kelamin Perempuan atau laki-laki yang memiliki wajah lengkap dengan mata yang bisa melihat, mulut yang bisa berbicara, memiliki kedua telinga yang bisa mendengar, beraktifitas dengan kedua tangan dan kakinya yang lengkap tanpa perlu menggunakan alat bantu atau bantuan dari orang lain.
Gambaran seperti inilah yang selama ini diyakini oleh banyak orang sebagai sebuah kebenaran atas definisi ‘normal’. Keyakinan ini tentu tidak muncul begitu saja, namun berawal dari lingkungan sekitar yang secara sadar atau tidak membentuk pemahaman tersebut. Sebagai contoh, sering kita dengar ungkapan “kita harus bersyukur, dilahirkan dengan tubuh yang lengkap dan normal” atau ketika melihat orang dengan disabilitas netra atau pengguna kursi roda yang memiliki prestasi kita sering melihat respon orang-orang sekitar yang berujar “Itu lihat. Mereka yang nggak normal aja bisa, masak kita yang normal nggak bisa” dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan serupa yang pada akhirnya menyiratkan definisi ‘orang normal’.
Pemahaman yang sudah tertanam ini, akhirnya goyah dengan pemahaman baru yang didapat dalam sebuat sesi tentang mengenal Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Sesi yang dipaparkan oleh Pamikatsih dari Jaringan Visi Solo Inklusi bertempat di Yayasan YAPHI pada tanggal 16 Agustus 2023, membawa setiap peserta untuk beranjak dari pemahaman yang selama ini sudah mengakar kuat. Sesi ini dihadiri oleh orang-orang dengan ragam disabilitas seperti disabilitas rungu wicara, disabilitas netra, disabilitas daksa, dan disabilitas mental serta orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus.
Di awal sesi, peserta diminta untuk menuliskan persoalan yang dihadapi oleh disabilitas. Rata-rata menuliskan bahwa disabilitas sering menghadapi persoalan terkait dengan hambatan mobilitas karena banyak tranportasi dan tempat umum yang belum aksesibilitas, adanya diskriminasi diberbagai bidang seperti Pendidikan dan pekerjaan, serta kebijakan negara yang belum mengakomodir hak-hak disabilitas. Dari jawaban-jawaban tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada tiga hambatan atau persoalan utama yang dihadapi oleh disabilitas yaitu tidak adanya rehabilitasi dan alat bantu, hambatan fisik, serta hambatan struktur.
Solusi atas persoalan-persoalan tersebut memang sudah nampak diupayakan, namun masih cenderung parsial dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya adanya jalan landai ditempat-tempat umum yang dibangun dengan kemiringan yang cukup tajam sehingga membahayakan pengguna kursi roda, belum lagi jika diujung jalan atau ditengah jalan ada penghambat lainnya seperti pohon; atau guiding blok untuk tuna netra yang sering kali berujung pada selokan atau pohon; atau transportasi umum yang belum tersedia alat bantu; dan masih banyak lagi. Jadi solusi yang diupayakan tanpa diikuti perubahan pola pikir dan pola perilaku tidak akan berdampak signifikan.
Lebih dalam, ibu Pamikatsih mengenalkan tentang konsep pikir ‘Pencacatan Secara Sosial’. Konsep ini terbentuk dari tiga hal utama yaitu tradisi dan budaya, agama, dan kecerdasan. Pertama adalah Tradisi dan budaya, masyarakat secara luar khususnya di Indonesia masih sering mengaitkan kondisi disabilitas seseorang dengan mitos yang dipercayai, seperti pengalaman ibu Pamikatsih yang sering mendapatkan labelling bahwa apa yang dia alami adalah akibat dari ibunya memotong kaki ayam pada saat dia dikandungan dan tentu cerita serupa sering kita dengar. Kedua adalah Agama, tidak jarang dalam ajaran agama menyebut bahwa kondisi disabilitas adalah salah satu wujud dari hukum karma atas kesalahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas atau oleh orang tuanya terdahulu. Ketiga adalah Kecerdasan, hal ini dimaksudkan karena setiap orang yang tumbuh dari tradisi dan agama akan terbiasa dengan pola pikir yang terbentuk dalam memandang kondisi disabilitas sehingga ketika orang-orang tersebut duduk diposisi pengambil kebijakan maka tentu pola yang sama akan diterapkan dalam setiap kebijakan yang dibentuk. Ketiga hal inilah yang kemudian semakin menggiring definisi ‘normal’ dan ‘cacat’.
Konsep 'Pencacatan' secara sosial dapat terlihat dari respon yang muncul dari seseorang bertemu dengan penyandang disabilitas, bermula dari pandangan yang terfokus kepada kondisi fisik disabilitas kemudian muncul perasaan kasihan selanjutnya diolah oleh otak dan memunculkan Tindakan memberi pertolongan atau bantuan. Pola seperti inilah yang akhirnya secara sadar atau tidak membentuk pola pikir penyandang disabilitas, mereka semakin terbelenggu dengan labelling ‘ab-normal’ dan justru semakin membentuk kepribadian disabilitas yang tidak percaya diri, menangisi kecacatannya, menolak berbagai kesempatan karena merasa diri tidak mampu dan cenderung memilih untuk menyendiri.
Hampir semua negara anggota PBB mengakui bahwa hak asasi penyandang disabilitas masih sangat terabaikan, unuk itulah mengapa Gerakan GEDSI ada sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas secara holistik. Jika saat ini faktanya banyak kebijakan negara yang tidak ramah disabilitas dan mau tidak mau disabilitaslah yang diminta untuk menyesuaikan maka konsep inklusi sosial berfokus kepada perubahan kebjiakan menuju kebijakan negara yang inklusi.
Dalam konsep GEDSI ada sebuah pendekatan yang dinilai efektif untuk diterapkan, yaitu Pendekatan Jalur Kembar (Twin Track Approach). Pendekatan yang pertama adalah penyertaan difabel yang dapat dilakukan dengan cara memfasilitasi proses penyertaan difabel dalam proses Inklusi dengan soft skill training dan pengembangan karakter difabel dan pendekatan yang kedua adalah Aksesibilitas Oleh Masyarakat dengan melibatkan prakarsa masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas fisik dan non-fisik. Jika pendekatan ini diterapkan maka penyandang disabilitas akan dapat berpartisipasi secara penuh dalam kesejahteraan hidup.
Dalam konsep Disability Sosial Inklusi ada 4 pilar yang harus berperan secara harmonis, yaitu: pemerintah, professional dan NGO, Masyarakat, serta penyandang disabilitas dan keluarganya. Untuk menjelaskan pemahaman ini, ibu Pamikatsih menggunakan analogi kue bolu. Kue bolu terdiri dari beberapa bahan yang tidak boleh dilewatkan dalam proses pembuatannya karena jika tidak maka kue bolu bukanlah kue bolu. Maksud dari analogi ini adalah ketika bahan pembuat kue bolu masih terpisah maka akan terlihat tepung, telur, gula, dan mentega dan pada kondisi ini belum bisa dikatakan bahwa keempat bahan tersebut adalah kue bolu. Diperlukan proses pencampuran dan pemasakan sehingga akhirnya bisa dikatakan kue bolu. Demikian juga dalam mewujudkan sosial inklusi, jika masing-masing pilar masih menggunakan ego dan pemahaman masing-masing maka sosial inklusi akan sulit terwujud. Oleh karena itu sinergi antar pilar-pilar tersebut menjadi kunci dalam Gerakan Disability Sosial Inklusi.
Perwujudan Inklusi Sosial tidak bisa dilakukan secara parsial sehingga dalam pembangunannya pun harus dilakukan analisis secara menyeluruh dengan melibatkan keempat pilar sehingga dapat tercipta lingkungan sosial yang positif, pembangunan fisik dan penyusunan program yang terintegrasi dan berkualitas sehingga semua orang dapat berpartisipasi secara penuh. Inilah yang disebut Disability Sosial Inklusi Berbasis Kawasan. (Dorkas Febria Krisprianugraha)
Yayasan YAPHI Dampingi Anak-anak Jemaat GKJ Slogohimo Edukasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Seksual
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 197
Mahas, salah seorang anak, jemaat sekolah Minggu Gereja Kristen Jawa Slogohimo, Wonogiri, tampak riang gembira ketika menerima arahan para pendamping dari Yayasan Yaphi yang pada siang hari itu berkegiatan di gereja. Tak hanya Mahas namun lebih dari 30 anak lainnya mengikuti acara yang dihelat akhir Juli tersebut. Bermain dan bergembira adalah salah satu syarat agar hak mereka terlindungi. Belajar dengan syarat hati harus bergembira tidak mesti disampaikan dengan cara kaku dan normatif.
Politik untuk Difabel Bukan Sekadar Ikut Pemilu
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 322
oleh : Hisyam Ikhtiar Mulia*
Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) kerap dianggap sebagai pesta demokrasi yang digelar tiap 5 tahun sekali di Indonesia untuk menentukan para pemimpin Negeri selama 5 tahun berikutnya. Namun, apakah demokrasi hanya sebatas pesta pemilihan eksekutif dan legislatif semata? Ini bisa menjadi kekeliruan berpikir kita selama ini. Sejarah mencatat bahwa ide demokrasi, yang disebut sebagai demokrasi radikal bahkan telah muncul sejak zaman Yunani kuno, tepatnya di Negara-Kota Athena (tahun 479-431 sebelum masehi). Namun demikian, demokrasi modern yang kita kenal pada saat ini boleh jadi bersumber pada berhasilnya rakyat Eropa meruntuhkan monarki (sistem kerajaan/feodal) yang ditandai revolusi Prancis pada 1789.
AJI Diseminasikan Buku Pedoman Peliputan Pemilu 2024
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 157
AJI Indonesia menggelar diseminasi buku Pedoman Peliputan Pemilu 2024 bagi Jurnalis pada Senin, 31 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari penerbitan buku dan lokakarya peliputan isu Pemilu 2024. AJI menilai penerbitan buku panduan ini sangat penting sebagai upaya peningkatan kapasitas bagi jurnalis dan media di tahun politik ini. Tidak hanya aspek teknis tapi juga sisi etika.
- Pers Rilis Tanggapan Atas Pemberitaan Terkait Inventarisasi dan Penyitaan Aset Terpidana Kasus Korupsi, Benny Tjokro
- YAPHI Merangkai Kebhinekaan dengan Lakukan Safari
- SAPDA Apresiasi 65 Pengadilan Inklusif Ramah Disabilitas
- Workshop Literasi Digital Inklusi Disabilitas; Upaya Mendorong Disabilitas Mandiri dan Berdaya